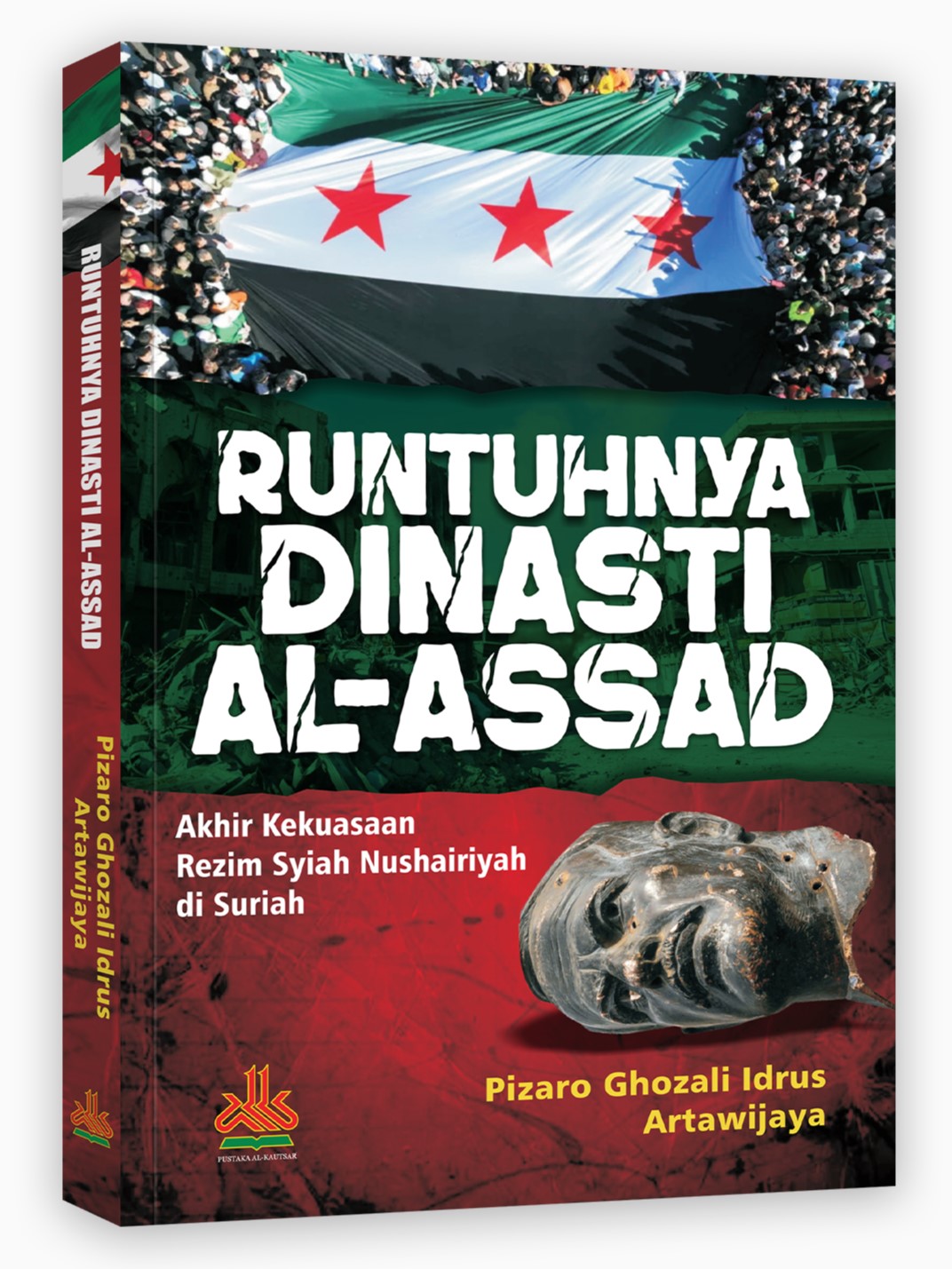Oleh: Hisham Jaafar*
Dua pertanyaan besar kini menghantui kesadaran kita bersama. Yang pertama, sebagaimana terangkum dalam judul tulisan ini: bagaimana dunia gagal menghentikan genosida di Gaza?
Yang kedua, yang seolah luput dari perhatian publik Arab dan Muslim: bagaimana kita sendiri gagal menghentikan genosida yang telah berlangsung lebih dari 600 hari?
Hidup kita terus berjalan seperti biasa, sementara jumlah anak-anak, perempuan, dan orang tua yang gugur terus bertambah setiap hari.
Atas pertanyaan pertama, sejumlah jawaban mulai muncul, terutama dari kalangan penulis dan akademisi di Barat.
Literatur yang membahas kegagalan komunitas internasional mulai bermunculan, dan tampaknya akan terus bertambah seiring dibukanya akses ke wilayah Gaza bagi jurnalis, peneliti, dan lembaga-lembaga sipil ketika perang usai.
Upaya ini kiranya akan menjadi pelengkap bagi literatur penting sebelumnya yang membahas tragedi Holocaust.
Namun di dunia Arab, belum ada upaya kolektif yang setara. Diskursus semacam ini masih mengandalkan inisiatif individu, tanpa dukungan sistematis dari institusi akademik dan riset.
Padahal, tragedi Gaza bukan satu-satunya. Sebelumnya terjadi pula genosida lain, termasuk yang kini masih berlangsung di Sudan.
Ke depan, tragedi kemanusiaan serupa sangat mungkin berulang karena akar struktural yang memungkinkan kekejaman semacam itu masih bercokol.
Bahkan, semakin menguat seiring dengan dominasi kapitalisme global dan kegagalan hukum internasional dalam menegakkannya secara adil.
Kapitalisme genosida
Genosida di Gaza bukanlah peristiwa tunggal yang dapat dipahami semata dari dimensi politik atau militer.
Ia merupakan gejala kompleks dari sebuah proyek kolonialisme pemukim yang telah lama berakar dan kini berkembang dalam bentuk paling brutal: kapitalisme genosida.
Ia berlangsung karena adanya kepentingan ekonomi, keterlibatan korporasi multinasional, dan dukungan sistemik dari negara-negara besar, disertai upaya dehumanisasi terhadap rakyat Palestina serta penguasaan atas narasi dan bahasa publik global.
Laporan terbaru dari Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, memaparkan secara gamblang bagaimana genosida bisa menjadi ladang keuntungan bagi banyak perusahaan.
Laporan itu bertajuk “From Occupation Economy to Genocide Economy”, disampaikan kepada Dewan HAM PBB dalam sesi ke-59 yang berlangsung antara 16 Juni hingga 11 Juli 2025.
Albanese mengembangkan basis data berisi hampir 1.000 entitas bisnis yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan internasional di Palestina.
Data ini dikumpulkan dari lebih dari 200 kontribusi berbagai pihak. Ironisnya, beberapa hari setelah laporan ini dirilis, Amerika Serikat (AS) justru menjatuhkan sanksi terhadap Albanese, menuduhnya berupaya menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan perusahaan Amerika serta Israel.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa sejak lama, kolonialisme dan genosida berjalan seiring dalam skema “kapitalisme rasial kolonial”.
Dalam konteks Palestina, perusahaan-perusahaan berperan penting dalam menopang sistem apartheid dan pendudukan ilegal Israel.
Mereka terlibat dalam proses pemindahan paksa dan penggantian populasi, dengan tujuan menghapuskan eksistensi rakyat Palestina.
Pasca 7 Oktober 2023, infrastruktur pengendalian dan eksploitasi yang telah dibangun selama beberapa dekade berubah menjadi sistem ekonomi-politik yang dimobilisasi secara total untuk melakukan penghancuran massal.
Perusahaan-perusahaan yang dulunya mendapat untung dari “ekonomi pendudukan”, kini menuai laba dari “ekonomi genosida”.
Sebagaimana disebut dalam laporan, genosida ini terus berlangsung karena ia menguntungkan banyak pihak.
Laporan tersebut menguraikan dengan detail sektor-sektor industri yang terlibat dalam genosida ini. Industri persenjataan menjadi tulang punggungnya.
Perusahaan seperti Elbit Systems dan Israel Aerospace Industries menjadi aktor utama, didukung oleh perusahaan global seperti Lockheed Martin yang menyuplai jet tempur F-35.
Alat utama dalam kampanye pemboman intensif yang menjatuhkan lebih dari 85.000 ton bom ke wilayah Gaza.
Dari sisi teknologi, perusahaan seperti IBM, Hewlett Packard, Microsoft, Google (Alphabet), Amazon, dan Palantir Technologies memasok infrastruktur komputasi awan, kecerdasan buatan, dan sistem pengawasan untuk kepentingan militer dan intelijen Israel.
Bahkan, CEO Palantir secara terang-terangan mengatakan bahwa sebagian besar rakyat Palestina adalah “teroris”, menunjukkan adanya pengetahuan dan niat dari level eksekutif tertinggi terhadap penggunaan kekuatan secara tidak sah.
Sektor konstruksi juga turut ambil bagian. Perusahaan seperti Caterpillar, HD Hyundai, dan Volvo Group telah lama menyuplai alat berat untuk penghancuran rumah dan infrastruktur Palestina.
Pascaserangan 7 Oktober, alat-alat ini digunakan untuk menghancurkan lanskap perkotaan Gaza, menjadikannya tidak layak huni dan mencegah warga kembali ke tanah mereka.
Penguasaan atas sumber daya vital pun dijadikan senjata genosida. Perusahaan air nasional Israel, Mekorot, misalnya, mengoperasikan pipa di Gaza hanya pada kapasitas 22 persen.
Pengendalian pasokan air ini digunakan sebagai alat pembunuhan massal. Perusahaan energi global seperti Chevron, BP, dan Glencore juga terlibat dalam menopang konsumsi energi militer dan sipil Israel, yang mendukung aneksasi dan penghancuran kehidupan di Gaza.
Sektor lain, dari pertanian, logistik, hingga pariwisata, juga tak luput. Perusahaan seperti Netafim dan Tnuva diuntungkan oleh kolonisasi lahan.
Amazon dan Booking.com mendukung ekonomi permukiman dengan menjual dan memasarkan produk serta properti yang berasal dari wilayah pendudukan. Airbnb bahkan dituduh “mencuci laba” dari kejahatan perang Israel.
Akhirnya, sektor keuangan memainkan peran kunci dalam membiayai seluruh mekanisme ini.
Bank-bank besar seperti BNP Paribas dan Barclays, manajer aset seperti BlackRock dan Vanguard, serta perusahaan asuransi global seperti Allianz dan AXA, menyalurkan dana miliaran dolar ke dalam obligasi pemerintah Israel serta perusahaan yang terlibat langsung dalam pendudukan dan genosida.
Bahkan lembaga amal berbasis agama pun ditengarai menjadi “penyandang dana utama” proyek-proyek ilegal ini.
Putusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang menyebut keberadaan Israel di Palestina sebagai bentuk kolonialisme ilegal memberikan landasan hukum yang tegas. Tetapi dunia masih bungkam.
Genosida di Gaza adalah gambaran telanjang dari dunia yang gagal menjalankan hukum internasional, gagal mengedepankan kemanusiaan, dan gagal mengendalikan kapitalisme predator yang kini menemukan panggungnya dalam penderitaan orang lain.
Pertanyaan awal pun kembali menggema: mengapa dunia gagal menghentikan genosida ini? Namun lebih dari itu, sebagai bagian dari dunia Islam dan komunitas Arab, kita perlu bertanya: mengapa kita sendiri tidak berbuat cukup? Mengapa kita tetap diam, sementara reruntuhan Gaza memanggil nurani kita hari demi hari?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa lahir dari keberanian menatap kebenaran dan kehendak untuk tidak menjadi penonton sejarah.
Sebab jika kita gagal kali ini, sejarah akan mencatat bahwa kita bukan hanya abai, tetapi juga turut menjadi bagian dari kejahatan itu—meski dalam diam.
Dehumanisasi dan kuasa atas narasi
Salah satu pilar utama yang memungkinkan genosida di Gaza berlangsung dengan impunitas adalah penghilangan sisi kemanusiaan rakyat Palestina dan penguasaan mutlak atas narasi publik.
Didier Fassin, seorang antropolog, sosiolog, sekaligus dokter asal Prancis, dalam bukunya yang terbit akhir tahun lalu, menyebut fenomena ini sebagai bentuk pengunduran moral dan persetujuan diam-diam atas pemusnahan Gaza.
Persetujuan ini, kata Fassin, bersifat pasif—melalui ketidakpedulian—dan sekaligus aktif—melalui pembenaran terbuka.
Narasi yang mendominasi ruang publik global tidak hadir secara netral. Ia dibentuk, dikendalikan, dan diarahkan sedemikian rupa untuk mengubah “ekonomi pendudukan” menjadi “ekonomi genosida”.
Hal ini dilakukan dengan manipulasi bahasa, penghapusan konteks sejarah, bias pemberitaan media arus utama, serta penindasan sistematis terhadap suara-suara yang menolak ketidakadilan.
Dalam konstruksi narasi tersebut, tuntutan atas gencatan senjata kerap dilabeli sebagai sikap “anti-Semit”.
Kritik terhadap pemerintah Israel, terutama yang diarahkan pada tokoh-tokoh dari sayap kanan ekstrem, langsung dicap sebagai ujaran kebencian.
Menyebut adanya “genosida” bisa berujung pada pengucilan sosial, stigma, atau bahkan tindakan hukum.
Di sinilah terjadi “kematian bahasa”—bahasa dipaksa tunduk pada logika penguasa. Kosakata dan tata kalimat dibentuk untuk menutup ruang diskusi, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan. Nilai-nilai dibalikkan.
Militer yang menghancurkan ribuan rumah dan membunuh warga sipil disebut “bermoral”. Penyerangan terhadap permukiman sipil disebut “respons”.
Dan agresi brutal selama berbulan-bulan disebut “perang Israel versus Hamas”, seakan-akan seluruh rakyat Gaza adalah bagian dari pertempuran itu.
Beberapa laporan dari ruang redaksi media Amerika menyebutkan adanya instruksi eksplisit untuk membatasi penggunaan kata-kata seperti “genosida” atau “pembersihan etnis”.
Istilah “kamp pengungsi” atau “wilayah pendudukan” disisihkan. Bahkan kata “Palestina” pun disebutkan seminimal mungkin.
Label “terorisme” hanya diterapkan pada aktor non-negara yang menyerang negara, sementara kekerasan oleh negara terhadap warga sipil disebut “kontra-terorisme”—walaupun korban jiwa justru lebih banyak datang dari pihak yang diserang. Ini adalah bentuk lain dari normalisasi kekerasan.
Narasi dominan juga mengabaikan sejarah. Cerita sering dimulai dari 7 Oktober 2023, menghapus konteks puluhan tahun pendudukan, blokade, dan penindasan terhadap rakyat Palestina.
Mengingatkan pada konteks ini dianggap sebagai “pembenaran” atas aksi kekerasan, seolah-olah hanya ada dua pilihan: menjadi pendukung korban atau pembela kekerasan.
Tak sedikit politisi Israel yang menyatakan terang-terangan bahwa “tidak ada yang disebut sebagai sejarah Palestina”, atau bahkan “tidak ada yang disebut bangsa Palestina”.
Pengakuan historis terhadap pengusiran warga Palestina, sebagaimana pernah disampaikan oleh tokoh militer Israel Moshe Dayan pada 1956, kini ditolak mentah-mentah.
Media arus utama di Barat secara umum mereproduksi narasi dari pihak pendudukan, sementara keraguan terus-menerus ditujukan pada informasi dari warga Palestina.
Pemberitaan sering kali diikuti disclaimer seperti “menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas”, seakan menegaskan bahwa data yang dikutip tidak dapat dipercaya—padahal data dari otoritas Palestina telah lama digunakan oleh PBB dan lembaga internasional lain.
Padahal, kenyataannya, angka korban di Gaza kemungkinan besar lebih tinggi dari yang dilaporkan, karena banyak jenazah masih tertimbun reruntuhan dan korban tak terdata akibat kekurangan fasilitas.
Pembunuhan terhadap jurnalis Palestina, pembatasan terhadap jurnalis asing, dan penyensoran berita dari Gaza semakin memperburuk situasi.
Akibatnya, banyak laporan dan gambar hanya bisa muncul melalui media sosial dan saluran alternatif.
Penindasan akademik dan pembungkaman suara
Penolakan terhadap perang dan seruan untuk damai pun tidak luput dari represi. Demonstrasi damai dibubarkan, diskusi publik dibatalkan, dan individu yang mengingatkan pada sejarah Palestina dihukum secara sosial dan profesional.
Kritik terhadap kebijakan Israel atau ideologi Zionisme segera diidentikkan dengan anti-Semitisme. Imbasnya, banyak akademisi kehilangan kontrak kerja, pameran dibatalkan, hingga visa ditolak.
Setelah 7 Oktober, sensor diri semakin meluas di kalangan akademisi dan mahasiswa akibat tekanan dari kelompok pro-Israel, politisi, dan donatur institusi pendidikan tinggi.
Di beberapa kasus, mahasiswa pro-Palestina dikeluarkan, dosen dipecat, dan rektor dipaksa mundur.
Ironisnya, kekerasan fisik terhadap demonstran pro-Palestina—termasuk yang berasal dari komunitas Yahudi—kerap diabaikan oleh aparat, bahkan korban justru ditangkap.
Di ruang publik kampus, mahasiswa dan akademisi yang menolak genosida kerap difitnah sebagai pemicu kekerasan atau penyebar kebencian.
Universitas, yang seharusnya menjadi pusat nalar dan nilai kemanusiaan, justru memainkan peran aktif dalam menopang struktur kekerasan.
Beberapa bekerja sama dengan lembaga Israel yang terlibat dalam sistem apartheid dan genosida, terutama dalam riset teknologi senjata dan pengawasan. Semua ini dibungkus dalam retorika “netralitas akademik”.
Penguasaan narasi ini memberikan legitimasi terhadap kekerasan terhadap warga Palestina, menghapus suara mereka, dan mengaburkan kejahatan internasional yang tengah berlangsung. Inilah bentuk kekerasan yang paling halus—tetapi juga paling membekas.
Dukungan politik dan dana yang tak terbatas
Dunia Barat, terutama ASdan sejumlah negara Eropa, memberikan dukungan hampir tanpa syarat terhadap Israel.
Bantuan militer terus mengalir, bahkan setelah Mahkamah Internasional menyatakan adanya “risiko nyata terjadinya genosida”.
Dukungan ini tidak lepas dari kepentingan industri militer, yang menjadikan Gaza sebagai ladang uji coba senjata baru.
Tapi ada juga alasan ideologis—keinginan negara-negara Eropa untuk “menebus dosa sejarah Holocaust”—yang ironisnya, justru menambah penderitaan bangsa lain.
Di baliknya terdapat pula motif geopolitik, keuntungan ekonomi, dan bias rasial terhadap dunia Arab dan Muslim yang menguat pasca 11 September.
Didier Fassin menyebut ini sebagai bentuk “penebusan dosa lewat perantara”, yang justru membuka jalan bagi terjadinya “Nakba kedua” terhadap rakyat Palestina.
Genosida di Gaza bukan sekadar akibat dari kekerasan bersenjata, tetapi buah pahit dari sistem global yang membiarkan kapitalisme, kolonialisme, dan rasialisme bertaut menjadi satu.
Ia terjadi karena adanya keuntungan ekonomi, dukungan negara-negara besar, pengendalian narasi, pembungkaman intelektual, dan pelemahan nilai-nilai kemanusiaan.
Yang paling menyesakkan adalah: tragedi ini terjadi di tengah masyarakat global yang mengklaim dirinya sebagai penjaga hak asasi manusia.
Dunia gagal bukan karena tak tahu, tetapi karena memilih untuk tidak peduli. Dan sebagian dari kita, dengan diam dan pasif, menjadi bagian dari kegagalan itu.
*Hisham Jaafar adalah seorang jurnalis dan peneliti asal Mesir. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Mada dan bekerja sebagai Konsultan Senior di Pusat Regional untuk Mediasi dan Dialog serta Konsultan di Pusat Dialog Kemanusiaan (HD). Ia juga merupakan pendiri dan Ketua Dewan Direksi Yayasan Mada untuk Pengembangan Media. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Kaifa Fasyila al-Ālam Fī Waqfi al-Ibādah al-Jamā’iyyah Fī Ghazah?”.