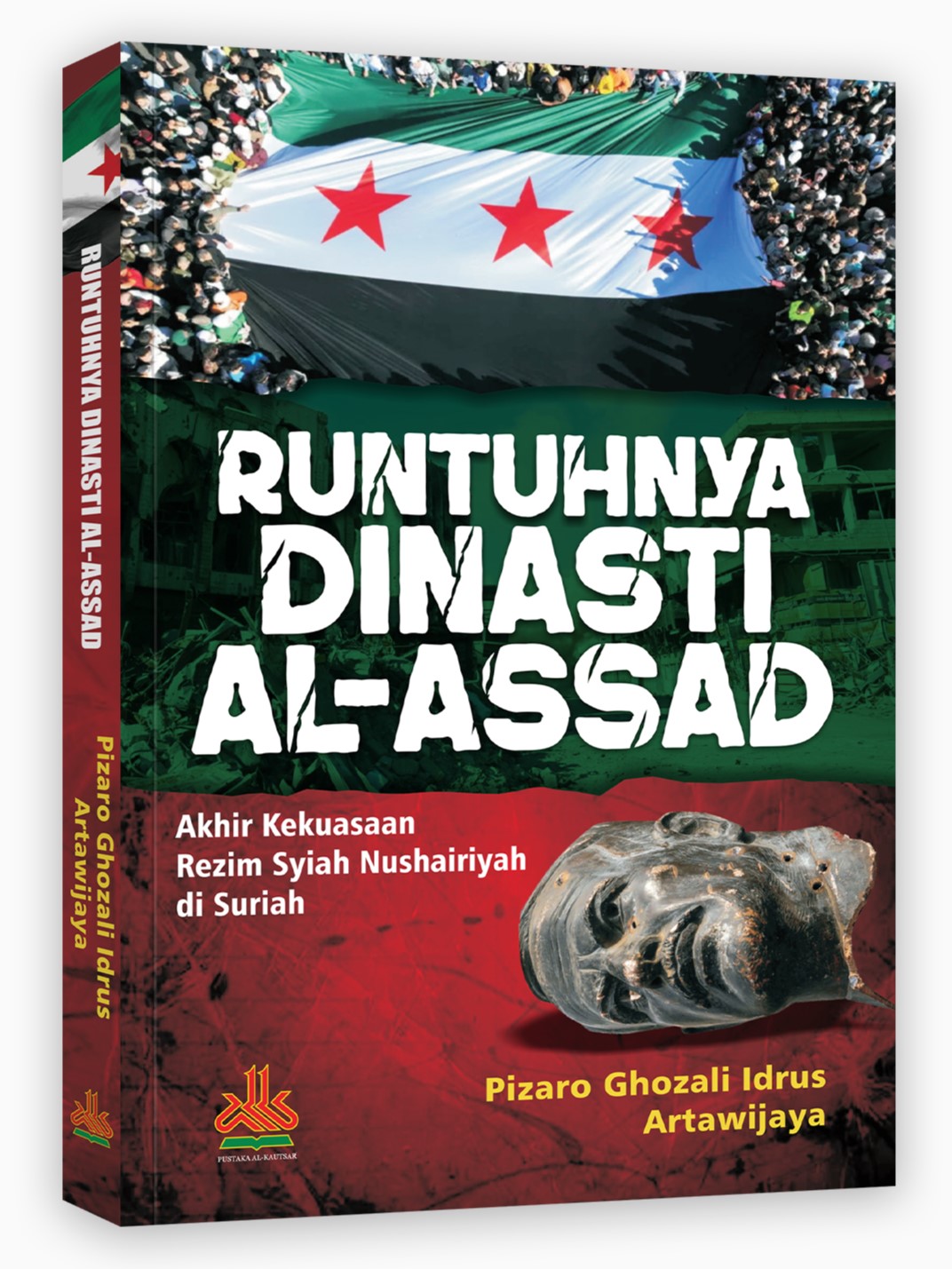Berita pengakuan Inggris atas negara Palestina kini menjadi sorotan utama media internasional.
Namun, respons terhadap langkah ini masih beragam. Bagi sebagian orang Palestina, keputusan tersebut hanyalah sekadar tinta di atas kertas, tanpa dampak nyata bagi penderitaan mereka.
Sementara itu, pihak lain menyambutnya dengan harapan, menilai pengakuan tersebut bisa membuka jalan bagi terobosan politik di tingkat internasional terkait isu Palestina.
Namun, pengakuan ini tidak bisa dilepaskan dari jejak sejarah panjang Inggris di tanah Palestina.
Di baliknya membayang sebuah dosa lama: lahirnya Deklarasi Balfour tahun 1917, yang hingga kini dianggap sebagai awal tragedi bangsa Palestina.
Saat itu, di tengah masa awal mandat Inggris di Palestina, Menteri Luar Negeri Arthur Balfour menyatakan janji untuk mendirikan “tanah air bagi bangsa Yahudi” di Palestina.
Deklarasi itu kemudian membuka pintu lebar bagi kolonisasi zionis, mempercepat arus migrasi Yahudi ke tanah Palestina historis, sekaligus memberi legitimasi bagi kelompok bersenjata Zionis yang didukung penuh oleh tentara dan pemerintah Inggris.
Dari sana pula, babak-babak kelam pun dimulai. Berbagai aksi kekerasan, pengusiran, dan pembantaian terhadap rakyat Palestina terjadi dengan perlindungan kolonial Inggris.
Bahkan, saat rakyat bangkit melawan—seperti dalam Pemberontakan Al-Buraq 1929 maupun Revolusi Besar 1936—pemerintah mandat Inggris justru bertindak represif, memadamkan perlawanan rakyat dengan tangan besi.
Kini, ketika dunia menyaksikan genosida yang masih berlangsung di Gaza serta perampasan tanah di Tepi Barat, pengakuan Inggris atas Palestina dibaca sebagai sinyal bahwa isu ini kembali menduduki posisi penting dalam agenda global.
Ribuan aksi solidaritas yang meletus di berbagai kota besar dunia, menyerukan penghentian perang dan keadilan bagi Palestina, menjadi tanda bahwa opini publik internasional semakin sulit diabaikan.
Palestina kembali di panggung dunia
Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Wasil Abu Yusuf, menilai bahwa dunia kini mulai melihat Israel bukan lagi sebagai “benteng demokrasi” di Timur Tengah, melainkan sebagai negara yang justru mengguncang stabilitas kawasan.
Hal itu, ujarnya, tampak dari rangkaian serangan Israel terhadap negara-negara di sekitarnya, mulai dari Lebanon dan Suriah, berlanjut ke Yaman, hingga terakhir menjangkau Qatar.
Menurut Abu Yusuf, pengakuan Inggris atas negara Palestina memang penting sebagai modal diplomasi.
Tetapi yang lebih mendesak adalah menghentikan genosida yang masih berlangsung, mencegah rencana pengusiran massal, serta menghentikan seluruh bentuk agresi terhadap rakyat Palestina.
“Kami berbicara dengan sangat jelas bahwa keputusan-keputusan legitimasi internasional yang menjamin hak-hak bangsa Palestina adalah jalan menuju stabilitas kawasan ini,” tegas Abu Yusuf.
Karena itu, ia menekankan, pengakuan Inggris harus dibaca sebagai bagian dari kesadaran global akan pentingnya menjaga kestabilan sebuah wilayah yang memiliki arti strategis bagi banyak negara di dunia.
Ia pun mengingatkan agar langkah ini tidak berhenti pada simbol semata, melainkan disertai mekanisme nyata untuk mewujudkan kedaulatan Palestina di lapangan.
Nada optimisme serupa disampaikan Husam Zomlot, Duta Besar Palestina untuk Inggris.
Dalam pidatonya saat pengibaran bendera Palestina di gedung Kedutaan Besar Palestina di London, tak lama setelah pengakuan itu diumumkan, Zomlot menegaskan bahwa setelah satu abad penyangkalan, pemerintah Inggris akhirnya mengambil langkah mengakui negara Palestina.
Ia menyebut momen itu sebagai “upaya memperbaiki kesalahan sejarah”.
Zomlot menambahkan, pengakuan tersebut adalah sebuah titik balik bersejarah, sekaligus tantangan untuk menghadirkan kebenaran dan menolak genosida, pendudukan, serta upaya sistematis menghapus identitas bangsa Palestina.
Langkah yang belum cukup
Meski diapresiasi sebagai terobosan diplomatik, pengakuan Inggris terhadap Palestina dinilai belum cukup untuk menutup luka sejarah.
Abd al-Rahim al-Shubaki, Guru Besar Ilmu Politik Universitas al-Najah, menegaskan bahwa langkah ini memang penting, tetapi tidak mampu menebus dosa besar Inggris melalui Deklarasi Balfour 1917.
“Kita bisa melihat pengakuan ini sebagai koreksi dalam lintasan politik Inggris, namun itu tidak berarti penghapusan tanggung jawab atas kesalahan masa lalu,” ujarnya.
Shubaki menilai, dengan latar belakang historis Inggris yang pernah menolak hak-hak rakyat Palestina di era mandat.
Pengakuan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan atas tanggung jawab historisnya terhadap lahirnya konflik yang berkepanjangan.
Ia menambahkan, posisi Inggris secara tradisional maupun saat ini memiliki bobot politik yang signifikan di panggung internasional.
Karena itu, langkah ini berpotensi mendorong negara lain—baik di Eropa maupun di luar Eropa—untuk mengikuti jejak yang sama, sehingga memperkuat posisi isu Palestina dalam perbincangan global.
Namun, Shubaki mengingatkan, langkah ini tetap tidak bisa dipisahkan dari kenyataan pahit bahwa Inggris-lah yang melahirkan Deklarasi Balfour.
“Pengakuan ini bisa dibaca juga sebagai manuver politik,” katanya, terutama dalam konteks berubahnya sikap generasi muda Eropa setelah 7 Oktober.
Generasi baru itu, menurutnya, mulai membaca narasi Palestina dengan kacamata yang berbeda, cenderung berpihak pada rakyat Palestina, dan memberi tekanan pada pemerintah mereka.
Negara-negara Barat, termasuk Inggris, pada akhirnya berusaha merespons perubahan opini publik tersebut.
Dalam pandangan Shubaki, yang paling dibutuhkan Palestina saat ini adalah tekanan nyata terhadap Israel untuk duduk di meja perundingan yang mengarah pada lahirnya negara Palestina, meskipun Israel hampir pasti menolak pengakuan tersebut.
Ia menekankan bahwa rakyat Palestina harus mampu menjadikan pengakuan Inggris sebagai modal politik di dalam arena politik Inggris sendiri.
Tujuannya, untuk menekan Israel melalui sanksi serta memperkuat tuntutan atas hak mereka: kedaulatan, stabilitas, penentuan nasib sendiri, dan berdirinya negara Palestina merdeka.
Simbolik atau koreksi arah?
Pandangan lebih kritis datang dari Rula Shadid, peneliti politik sekaligus direktur bersama Palestinian Institute for Public Diplomacy.
Menurutnya, pengakuan Inggris dalam bentuk saat ini hanyalah sebuah langkah simbolik tanpa makna substantif.
“Jika ditimbang dalam konteks sejarah Palestina saat ini, pengakuan ini tidak membawa bobot nyata untuk menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Padahal, penghentian pembantaian itu semestinya menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Shadid menilai, keputusan Inggris justru lebih mencerminkan upaya untuk menghindari tindakan yang benar-benar berdampak. Ia menyinggung kontradiksi yang nyata.
“Meski di media tampak ada kemarahan Israel, faktanya Inggris masih menjadi salah satu pendukung terbesar pendudukan. Bahkan sampai hari ini, ada tentara Israel yang mendapat pelatihan di akademi militer Inggris. Itu kemunafikan politik,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa rakyat Palestina pada saat ini membutuhkan pengakuan yang menjamin hak mereka untuk melakukan perlawanan dalam segala bentuknya, tanpa dicabut legitimasi perjuangannya.
Menurutnya, pengakuan yang disertai syarat bahwa Otoritas Palestina adalah satu-satunya wakil sah rakyat Palestina justru berbahaya bagi gerakan pembebasan.
Terlebih di tengah krisis representasi, demokrasi, dan pluralisme yang sedang dihadapi rakyat Palestina dalam hubungannya dengan Otoritas Palestina.
Ada pula kekhawatiran yang nyata di tengah masyarakat Palestina: jangan sampai pengakuan itu justru mereduksi hak-hak mereka dan melemahkan narasi perlawanan.
“Hari ini, rakyat Palestina yang berjuang di lapangan bukan demi mewujudkan solusi dua negara, melainkan untuk menghentikan genosida, menghentikan ekspansi permukiman, serta membebaskan anak-anak mereka dari penjara Israel,” tambah Shadid.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan isi pengakuan Inggris. Tidak ada kejelasan mengenai batas wilayah negara Palestina, maupun otoritas apa yang akan memerintahnya.
Bahkan, Shadid menilai berbahaya jika pengakuan ini berangkat dari kerangka solusi 2 negara, sebab pada kenyataannya tidak ada lahan nyata yang tersisa untuk mendirikan sebuah negara.
Karena itu, menurutnya, langkah yang lebih mendesak bukan sekadar pengakuan, melainkan aksi nyata: memutuskan hubungan politik, sosial, dan akademik dengan Israel; menarik investasi dari wilayah pendudukan; mengisolasi Israel di lembaga-lembaga internasional seperti PBB, FIFA, hingga universitas; serta memastikan adanya komitmen global yang serius untuk menegakkan putusan Mahkamah Pidana Internasional.