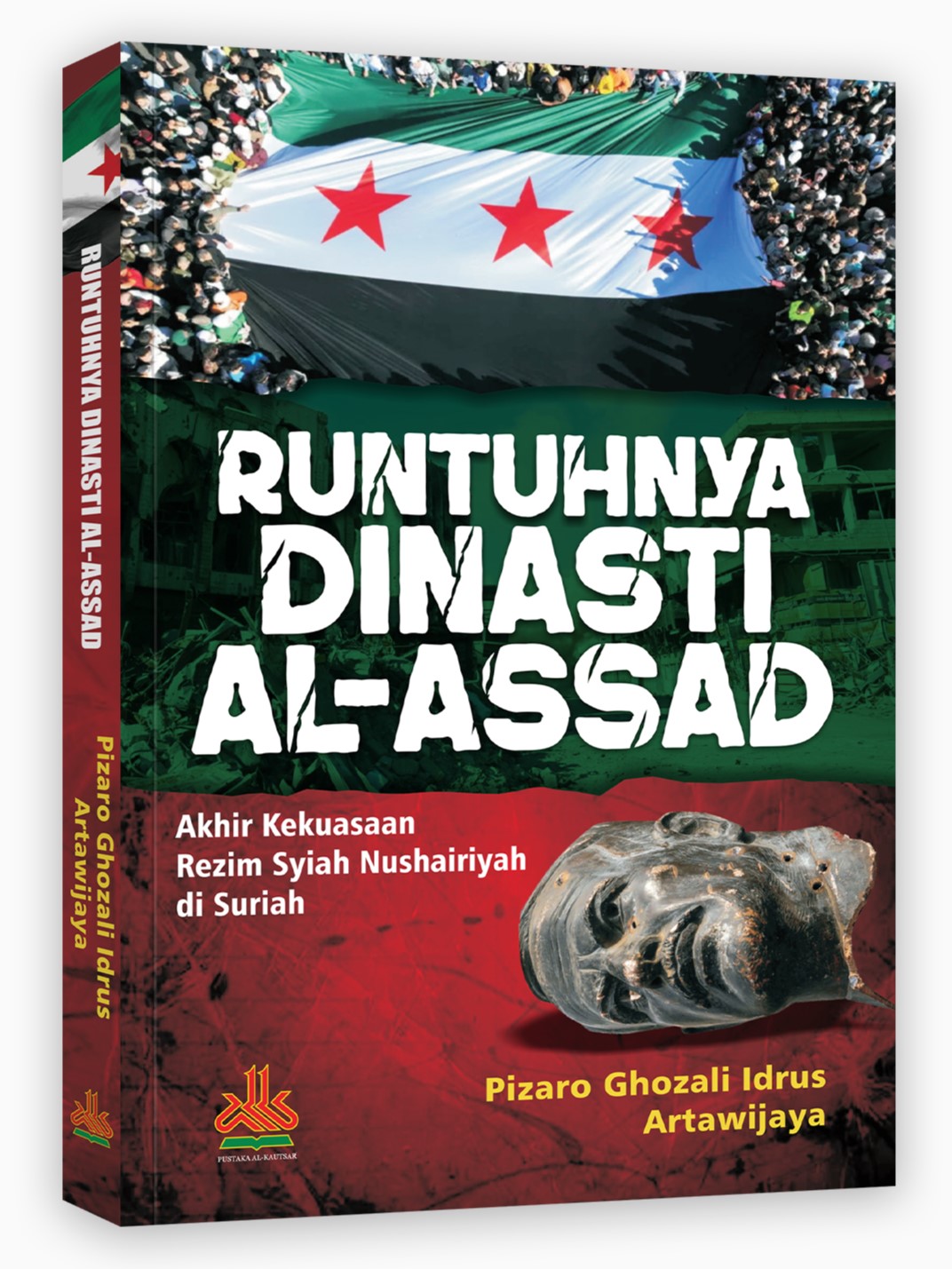Isu perlucutan senjata Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan di Gaza kembali menjadi sorotan besar bagi Israel dan negara-negara pendukungnya, khususnya Amerika Serikat (AS).
Hal ini setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rancangan resolusi yang diajukan Washington mengenai penghentian agresi Israel di Jalur Gaza.
Dalam rancangan itu, salah satu poin paling menonjol ialah pembentukan kekuatan stabilisasi internasional bersifat sementara di Gaza.
Pasukan ini dirancang berada di bawah satu komando terpadu dengan mandat melucuti senjata kelompok-kelompok bersenjata, melindungi warga sipil, serta melatih kepolisian Palestina, dengan koordinasi bersama Mesir dan Israel.
Sikap Israel di satu sisi tegas: perlucutan senjata Hamas adalah syarat utama. Di sisi lain, Hamas menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak mempertahankan senjata hingga terwujud negara merdeka.
Pertarungan dua posisi ini semakin memperjelas paradoks yang berlangsung di lapangan.
Hukum internasional mengakui hak rakyat terjajah untuk melakukan perlawanan, tetapi praktik di lapangan kerap memperlihatkan standar ganda.
Yaitu, perlawanan dikriminalisasi, sementara kekuatan militer negara pendudukan terus memperoleh legitimasi dan dukungan.
Hukum internasional yang tak netral
Secara normatif, kerangka hukum yang mengatur perlawanan bersenjata sangat dibatasi oleh tafsir keamanan yang dominan.
Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 memang mengakui legitimasi perlawanan terhadap pendudukan dalam situasi konflik bersenjata.
Namun, implementasi pengakuan tersebut kerap tunduk pada kepentingan politik dan keamanan negara-negara besar.
“Legitimasi hukum tidak selalu berubah menjadi perlindungan nyata ketika pertimbangan keamanan negara-negara besar beririsan dengan aturan hukum internasional,” tegas Peneliti Adam Roberts dalam studinya “Resistance Against Military Occupation”.
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam laporan resminya mengenai perlucutan senjata juga menyoroti pentingnya pelaksanaan yang berlandaskan prinsip kemanusiaan yang ketat.
Menurut ICRC, program perlucutan senjata harus dilakukan oleh lembaga hukum dan kemanusiaan yang diakui, dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas, agar hasilnya memperkuat struktur institusional pascakonflik—bukan sekadar menurunkan tingkat persenjataan.
Standar ganda: Senjata Palestina vs persenjataan Israel
Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan Israel berada di peringkat ke-15 dunia dalam impor senjata periode 2020–2024, yakni sekitar 1,9 persen dari total impor senjata global.
AS menyumbang sekitar 66 persen dari total impor tersebut, disusul Jerman dengan 33 persen.
Sementara itu, pihak Palestina justru diminta membongkar struktur militernya dan menyerahkan senjata.
Ketimpangan ini menyoroti perbedaan standar yang jelas: pihak yang lebih lemah dipaksa melucuti diri, sementara pihak yang lebih kuat dipersenjatai negara-negara besar.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, sejumlah unsur dianggap harus terpenuhi:
- Mekanisme internasional independen untuk memantau arus senjata, sejalan dengan prinsip traceability dalam Perjanjian Perdagangan Senjata.
- Menjamin kemampuan perlindungan warga sipil, sehingga pihak yang lebih lemah tidak kehilangan kapasitas pertahanan dasar.
- Mengaitkan langkah-langkah keamanan dengan peta jalan politik yang menjamin keseimbangan kekuatan dan akuntabilitas, bukan syarat sepihak yang justru melemahkan satu pihak.
Bukan resep siap pakai
Sederet pengalaman dunia kerap dijadikan rujukan—misalnya perlucutan senjata Jerman dan Jepang pasca Perang Dunia II.
Namun berbagai penelitian terbaru menegaskan bahwa model semacam ini tidak bisa diterapkan secara langsung pada konteks lain, termasuk Gaza.
Jerman dan Jepang kala itu tunduk pada pengaturan yang sangat ketat, termasuk pembatasan kedaulatan politik.
Jepang, misalnya, dipaksa menerima konstitusi baru yang secara eksplisit meniadakan perang sebagai hak kedaulatan, kecuali kekuatan pertahanan terbatas.
Untuk memahami variasi hasil perlucutan senjata, pengalaman global dapat dibagi ke dalam tiga jalur utama:
- Perlucutan senjata di bawah pengawasan asing dan rekonstruksi negara
Model ini biasanya menghasilkan biaya kedaulatan yang sangat tinggi.
- Jerman
Setelah perang, Jerman menjalani proses denazifikasi, pembongkaran lembaga pemerintahan, rekonstruksi konstitusi, serta pembatasan ketat terhadap kemampuan militer sebelum akhirnya diperbolehkan memiliki angkatan bersenjata terbatas dalam kerangka NATO.
- Jepang
Konstitusi 1947, yang diberlakukan oleh pendudukan Amerika Serikat, memuat Pasal 9 yang melarang Jepang memiliki kekuatan militer ofensif. Jepang kemudian bergantung pada payung keamanan AS.
- Irak
Perlucutan senjata setelah invasi 2003 dilakukan di bawah kendali penuh pasukan pendudukan.
Rekonstruksi institusional berjalan tetapi menghasilkan negara dengan struktur keamanan rapuh dan otoritas nasional yang terbatas.
- Perlucutan senjata setelah terwujud tujuan politik dan kedaulatan nasional
Dalam model ini, perlucutan senjata berjalan sukses karena didahului oleh legitimasi politik nasional.
- Aljazair
Proses perlucutan senjata dimulai hanya setelah proklamasi kemerdekaan 1962. Pasukan Front Pembebasan Nasional kemudian digabungkan ke dalam Angkatan Darat Aljazair.
- Irlandia Utara
Menurut riset Chatham House, penyerahan senjata dilakukan dalam kerangka kesepakatan politik yang seimbang dan legitimasi institusi lokal.
- Afrika Selatan
Setelah runtuhnya apartheid, sayap militer Kongres Nasional Afrika dilebur ke dalam lembaga keamanan negara. Keberhasilan proses ini terkait langsung dengan tercapainya sistem politik demokratis.
- Perlucutan senjata teknis tanpa agenda politik: Hasilnya rawan
Model ini menghasilkan institusi keamanan yang rapuh.
- Angola
Menurut laporan Uni Afrika, perlucutan senjata sebelum terbentuknya otoritas nasional yang kuat berujung pada kegagalan reintegrasi pejuang dan ketidakstabilan keamanan.
- Namibia
Riset Universitas Windhoek (2019) menunjukkan bahwa tanpa kesepakatan politik komprehensif, perlucutan senjata menciptakan kekosongan kelembagaan dan hambatan ekonomi bagi bekas kombatan.
- Bosnia
Laporan International Center for Transitional Justice (2009) mencatat bahwa tidak adanya kerangka politik institusional pascaperang menyebabkan lembaga keamanan pascaperlucutan senjata rentan dan tidak stabil.
Pengalaman Palestina: Celah kelembagaan dan penolakan populer
Dalam konteks Palestina, studi Palestine Center for Political and Social Studies (2025) menunjukkan bahwa pemusatan senjata pada aparat yang terikat koordinasi keamanan dengan Israel justru menciptakan celah kelembagaan.
Sekitar 68 persen warga Palestina menolak intervensi kekuatan asing untuk melucuti Hamas—cerminan penolakan publik terhadap replikasi model kontrol keamanan eksternal.
Meski demikian, Otoritas Palestina menyambut baik persetujuan Dewan Keamanan untuk rencana AS dan menyatakan kesiapannya menjalankan kerangka kebijakan sesuai keputusan tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan pentingnya penerapan segera kesepakatan itu.
Faksi perlawanan dan masa depan senjata di Gaza
Kelompok-kelompok perlawanan menolak Resolusi DK PBB 2803, menyebutnya sebagai bentuk pengawasan internasional atas Gaza.
Mereka menegaskan bahwa hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan dijamin hukum internasional, dan bahwa senjata perlawanan merupakan jaminan hak itu.
Riset Peace Research Institute Oslo (PRIO) tahun 2023 oleh Josephine dan Ricardo memperkuat pandangan tersebut.
Kajian itu menegaskan bahwa perlucutan senjata tanpa kerangka politik menyeluruh akan menghasilkan kekosongan keamanan dan struktur kelembagaan rapuh—persis seperti yang diperingatkan para pemimpin faksi.
Dengan kata lain, setiap upaya melucuti senjata perlawanan di Gaza tanpa kerangka politik yang sah berisiko mengulang kegagalan banyak model di berbagai negara lain.