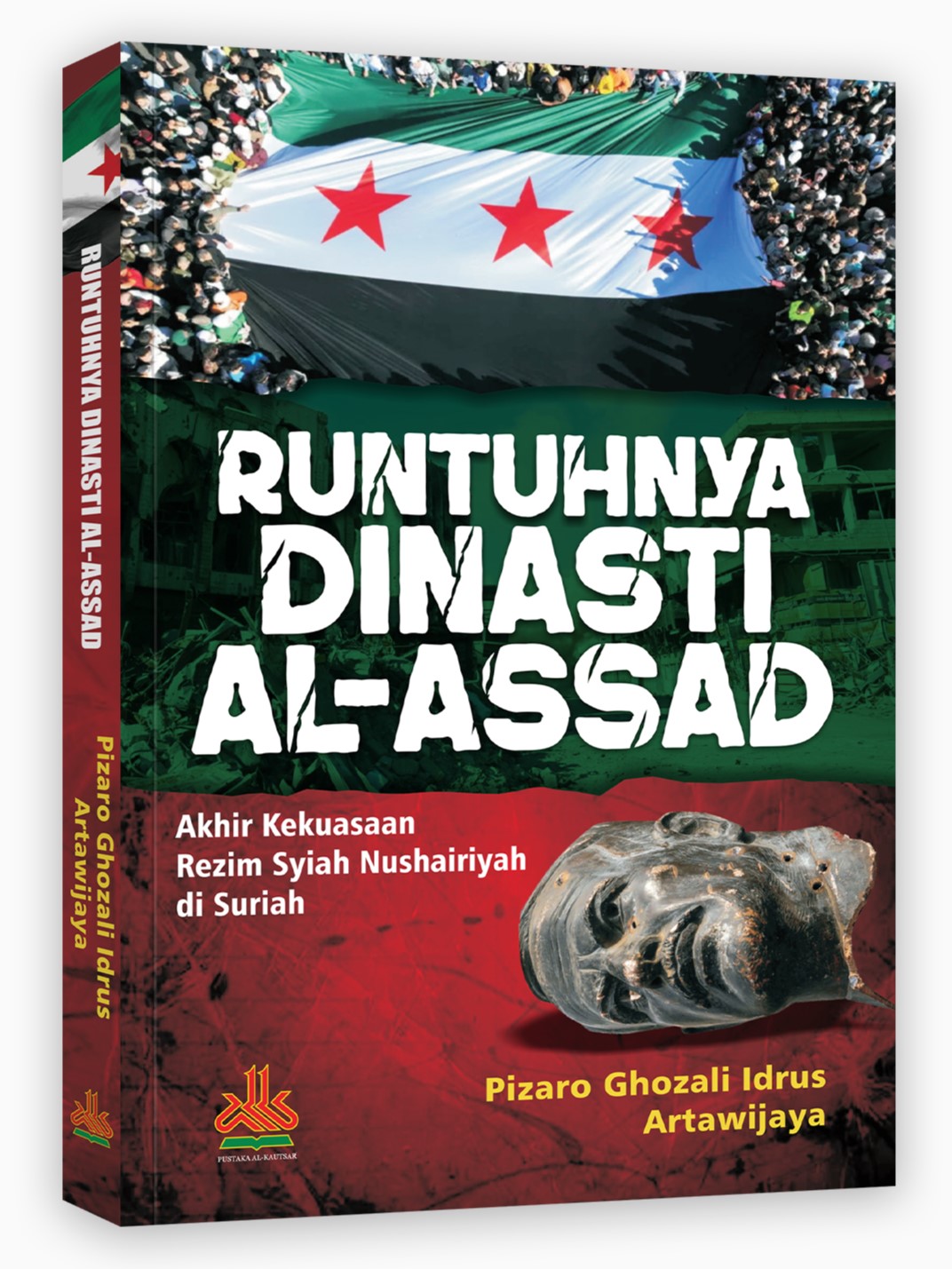Israel memperlihatkan wajah terburuknya dengan menggunakan senjata kelaparan terhadap warga sipil di Jalur Gaza.
Kebijakan itu dijalankan secara sistematis, terprogram, bahkan dengan bantuan kecerdasan buatan.
“Ini adalah kejahatan yang lengkap dalam semua unsurnya, dilakukan di hadapan dunia,” ujar Direktur Pusat Studi al-Zaytouna, Mohsen Saleh.
Pernyataan itu menggambarkan kegagalan hukum internasional dalam menghadapi praktik genosida dan kelaparan yang menimpa penduduk Gaza.
Padahal, teks hukum internasional jelas melarang penggunaan kelaparan sebagai alat perang dan menegaskannya sebagai bentuk kejahatan perang sekaligus genosida.
Namun, kenyataan di Gaza menunjukkan bahwa norma hukum itu tengah menghadapi ujian terberatnya.
Apakah persoalannya terletak pada kelemahan instrumen hukum internasional itu sendiri? Atau pada absennya kemauan politik untuk menegakkan hukum? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mengemuka dalam diskusi bertajuk “Menelantarkan Warga Gaza antara Kejahatan Israel dan Tanggung Jawab Internasional” yang diselenggarakan Pusat Studi al-Zaytouna.
Dalam pengantar diskusi, Saleh mengingatkan bahwa sekitar 470.000 penduduk Gaza—sebagian besar anak-anak dan perempuan—berada di ambang kematian akibat kelaparan.
Sementara itu, 2,4 juta warga Palestina terus hidup dalam cengkeraman blokade yang menutup akses pangan, obat-obatan, dan air bersih.
“Kejahatan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa intervensi nyata dari masyarakat internasional,” tegasnya.
Fakta dan kesenjangan
Guru besar hukum internasional, Mohammad al-Mousa, menegaskan bahwa praktik kelaparan sistematis terhadap penduduk Gaza dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang yang jelas dilarang Konvensi Jenewa.
Dalam kondisi tertentu, hal itu bahkan bisa masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida, apabila terbukti ada niat penghancuran yang disengaja.
Menurut al-Mousa, instrumen hukum internasional sejatinya kaya dengan aturan. Mulai dari Konvensi Jenewa, prinsip-prinsip panduan seperti San Remo Manual, hingga Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional.
Namun, tragedi di Gaza menunjukkan adanya jurang besar antara teks hukum internasional yang ideal dengan praktik hukum internasional yang tunduk pada kalkulasi kekuatan dan kepentingan politik.
“Karena itu, kita tidak bisa berhenti pada pembacaan teks. Diperlukan pendekatan yang lebih praktis,” ujarnya.
Beberapa langkah yang ditawarkan antara lain, menganalisis kerangka normatif tentang hak atas bantuan kemanusiaan, membongkar kesenjangan dalam penerapannya, membaca kesenjangan itu dari perspektif pascakolonial dan pendekatan dunia ketiga.
Selain itu, juga merumuskan langkah konkret untuk memperkuat akuntabilitas dan akses kemanusiaan.
Al-Mousa menekankan, hal yang paling mendasar adalah menelaah unsur-unsur kejahatan: apakah ada niat, konteks, dan cakupan yang cukup untuk menyatakan bahwa kelaparan ini sekadar pelanggaran, ataukah sudah merupakan kejahatan internasional dengan elemen yang lengkap.
Ketiadaan kemauan politik
Sementara itu, pengacara sekaligus dosen hukum tata negara, Adel Yameen, menilai kondisi kemanusiaan di Gaza sebagai salah satu krisis paling serius dalam sejarah kontemporer.
Warga sipil, ujarnya, tengah menghadapi situasi yang mematikan akibat blokade, pembunuhan massal, upaya genosida yang nyata.
Selain itu, juga kebijakan kelaparan yang disertai pelarangan masuknya bahan-bahan vital, pembatasan pasokan dasar, dan berulang kali dicegahnya akses pangan, air, maupun obat-obatan.
Yameen menegaskan, praktik blokade dan kelaparan ini jelas dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan ketentuan hukum internasional.
Ia menambahkan, Mahkamah Pidana Internasional berwenang menuntut pertanggungjawaban para pejabat Israel, sekalipun Israel sendiri bukan negara pihak dalam Statuta Roma.
Ia juga mengingatkan bahwa San Remo Manual mengenai bantuan kemanusiaan, serta teori tentang tindakan balasan kemanusiaan, memberikan ruang bagi negara-negara lain untuk menyalurkan bantuan darurat ke Gaza, bahkan tanpa persetujuan dari pihak pendudukan Israel.
Namun, menurut Yameen, hambatan terbesar justru bukanlah ketiadaan aturan, melainkan absennya mekanisme pelaksanaan dan kemauan politik internasional.
“Masyarakat internasional memiliki perangkat hukum yang lengkap, tetapi tidak mampu menggunakannya,” ujarnya.
Hukum yang tunduk pada tekanan politik
Ahlem Baydoun, pakar hukum internasional di Universitas Lebanon, menilai serangan terhadap warga sipil yang mengantre bantuan kemanusiaan bukan hanya kejahatan perang, melainkan sudah masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.
Menurut Baydoun, aksi itu tidak sekadar pembunuhan terhadap mereka yang mencari pertolongan, melainkan sebuah pola yang dirancang untuk menebar ketakutan, memperluas kelaparan.
Selain itu, juga menyingkirkan penduduk—baik dengan cara pembantaian maupun memaksa mereka mengungsi.
“Apa yang terjadi di depan pusat-pusat distribusi bantuan adalah rangkaian kejahatan: mulai dari hukuman kolektif, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, hingga genosida dan pembersihan etnis,” ujarnya.
Baydoun mengingatkan, Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus-kasus tersebut, apalagi Palestina resmi menjadi anggota sejak 2015.
Selain itu, opsi pembentukan pengadilan internasional ad hoc, seperti halnya Nuremberg dan Tokyo, juga terbuka.
Namun, ia mengakui, praktik peradilan internasional kerap terpengaruh tekanan politik, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat tertindas terhadap kebermaknaan keadilan global.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh negara pendudukan tidak mengenal kedaluwarsa.
“Tidak ada tempat yang bisa membatasi penuntutan para pelaku. Artinya, setiap negara memiliki kewenangan untuk menahan mereka berdasarkan hukum internasional, baik publik maupun privat,” katanya.
Tanggung jawab internasional
Dalam sesi penutup, Elissar Farhat, akademisi hukum dan ilmu politik, menekankan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab melindungi warga sipil Gaza dan mencegah genosida melalui kelaparan, sesuai prinsip Responsibility to Protect (R2P).
Namun, mekanisme hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB justru berubah menjadi alat untuk melumpuhkan setiap upaya nyata.
Farhat menyerukan pengaktifan kembali mekanisme Uniting for Peace di Majelis Umum PBB, disertai tekanan diplomatik dan gerakan masyarakat sipil agar bantuan kemanusiaan dapat masuk secara berkelanjutan.
Menurutnya, berdiam diri pada teks hukum semata hanya akan mempertegas kegagalan lembaga-lembaga internasional.
Ia menegaskan, Gaza telah memperlihatkan dengan gamblang batas-batas sistem hukum internasional yang ada.
Karena itu, diperlukan pendekatan baru—kritis sekaligus praktis—agar hukum internasional kembali menjalankan fungsinya sebagai pelindung kemanusiaan, bukan sekadar alat yang tunduk pada neraca kekuatan global.