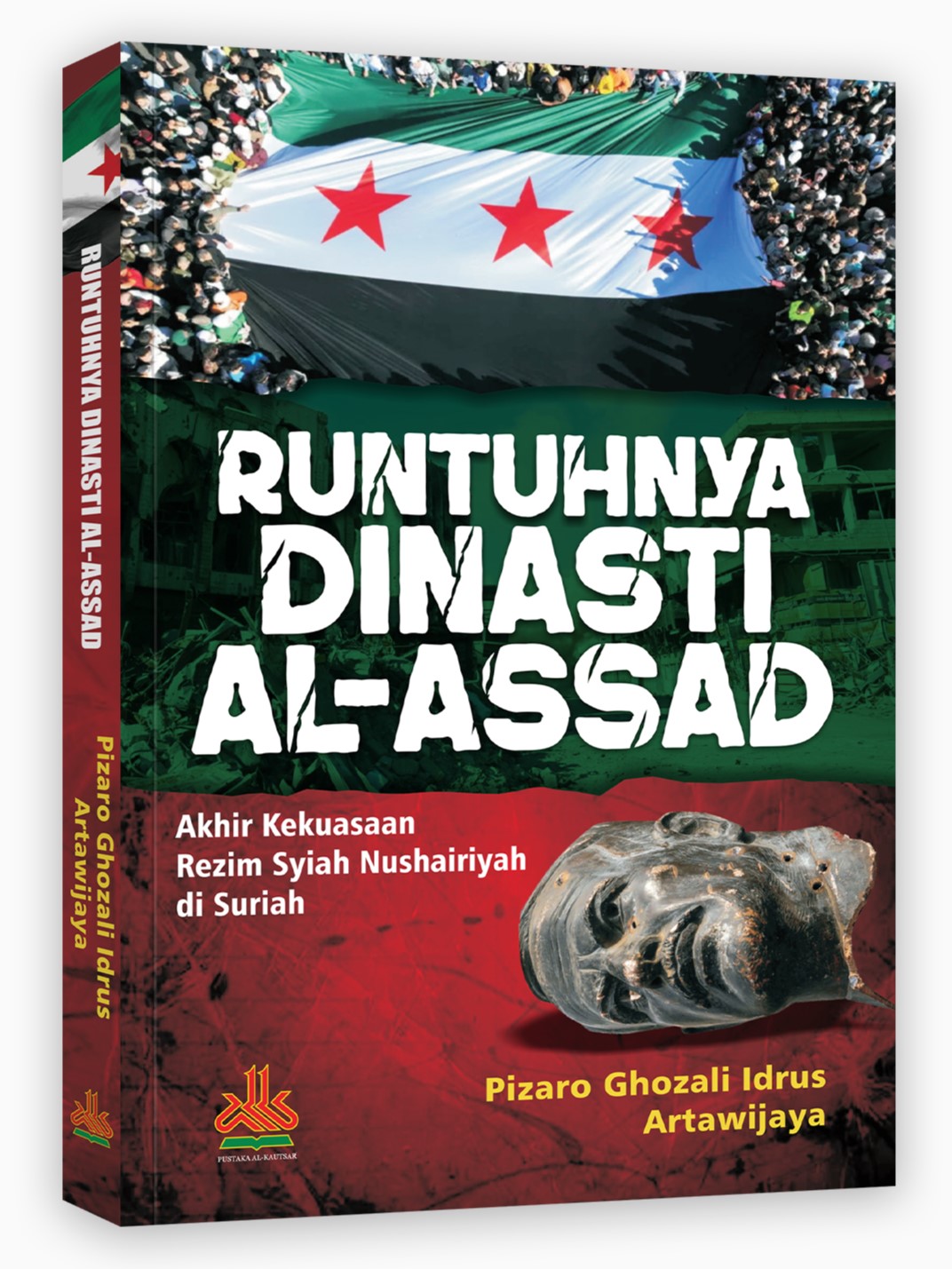Di beranda kantor Al Jazeera di jantung Kota Ramallah, pot berisi tanaman mint mengering. Tak seorang pun dari tim redaksi bisa lagi menjangkaunya sejak kegiatan mereka dibekukan oleh keputusan ganda.
Larangan dari otoritas pendudukan Israel dan pembatasan dari Otoritas Palestina, yang diberlakukan sejak September 2024 hingga hari ini.
Masih di tempat yang sama, sebagian gambar mendiang jurnalis Shireen Abu Akleh yang selamat dari perusakan tentara Israel terus menatap ke arah pusat Kota Ramallah.
Kehidupan di sana tampak berjalan seperti biasa, padahal Palestina sedang melalui salah satu babak paling kelam dalam sejarahnya.
Kontras yang mencolok ini mencerminkan betapa kompleksnya tumpang tindih antara kekuasaan dan penindasan, yang telah menjadi bagian dari lanskap politik di Tepi Barat sejak berakhirnya Intifadah Kedua.
Di bawah dominasi sistem yang terus mengatur hidup rakyat Palestina secara menyeluruh, pusat-pusat kota bisa terlihat “tenang”—bahkan di tengah gelombang genosida.
Manusia memang tak bisa memilih di mana dan kapan ia dilahirkan, atau bagaimana sejarah besar menyapunya.
Namun, yang selalu menjadi miliknya adalah kemampuan memilih: bagaimana ia memberi makna pada dirinya sendiri dan bagaimana ia merespons sejarah yang sedang berlangsung di hadapannya.
Tulisan ini menelusuri bagaimana jurnalisme Palestina dijalankan di Tepi Barat pada masa genosida yang kini sedang berlangsung.
Di tengah hantaman sejarah besar, jurnalis Palestina tak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga sedang berjuang mempertahankan ruang hidup masyarakatnya melalui cerita.
Di ruang redaksi: Antara abstraksi dan kepadatan
Perang menciptakan percepatan berita yang luar biasa. Tak jarang, jurnalis Palestina tenggelam dalam banjir informasi dan tekanan liputan.
Hanya suara ketukan papan ketik, dering telepon, dan musik pembuka siaran berita yang terdengar.
Ada kalanya malam-malam yang sepi menimbulkan rasa waswas. Namun, dari keheningan yang mencekam itu, muncul ruang batin tempat rasa takut, harapan, dan kemarahan berkelindan.
Dalam kondisi seperti ini, jurnalis kerap dipaksa mengubah kisah-kisah yang begitu dalam—tentang manusia, tentang tanah—menjadi satu paragraf pendek bernama “berita”.
Berhadapan setiap hari dengan rincian peristiwa yang membanjiri ruang redaksi, jurnalis perlahan membuka “mata ketiga”.
Ia mulai melihat simpul-simpul tersembunyi yang menghubungkan duka rakyat dan tarik-menarik kekuasaan.
Ia mulai memahami bahwa proyek-proyek politik yang bertarung sering kali menciptakan derita massal untuk membungkam kata “tidak” terhadap kezaliman.
Ketika genosida dimulai, Israel dengan cepat mempercepat strategi militer dan politiknya untuk melumpuhkan segala potensi perlawanan di Tepi Barat.
Ratusan pos pemeriksaan dan pembatas wilayah memecah belah komunitas Palestina, menjadikannya terisolasi satu sama lain dan rentan terhadap kekerasan para pemukim, yang dilindungi oleh militer Israel.
Ribuan penangkapan dan penggerebekan malam hari berlangsung tanpa henti. Namun, dari semua itu, yang paling mencengangkan adalah banalitas pembunuhan yang terjadi hampir setiap hari.
Seolah ingin menormalkan kematian mendadak dan menanamkan ketakutan dalam benak setiap orang Palestina.
Di tengah semua ini, jurnalis Palestina dituntut untuk terus menghasilkan berita. Namun tantangan terbesarnya bukan sekadar kecepatan, melainkan bagaimana tidak kehilangan detil—detil yang menjadikan setiap kisah bagian dari narasi perjuangan masyarakat Palestina.
Suatu pagi di bulan Januari 2024, dari kota Jenin datang kabar bahwa sebuah drone Israel menembaki sekelompok pemuda yang sedang menghangatkan diri di sekitar api unggun. 4 dari mereka adalah saudara kandung: Hazza, Rami, Ahmad, dan Alaa Najeh Darwish.
Seorang ibu kehilangan empat anaknya sekaligus. Tragedi ini bukan hanya soal duka pribadi, melainkan bagian dari strategi sistematis untuk menanamkan rasa takut kepada siapa pun yang ingin mengatakan “tidak”.
Dari luka sebesar itu, dunia seakan tak peduli. Rencana kekuatan global berlomba masuk dari celah yang terbuka oleh kekerasan.
Sementara itu, jurnalis Palestina dituntut untuk menyampaikan keseluruhan cerita: untuk tetap hidup, dan menjaga agar kisah itu pun tetap hidup.
Karena dari keberlangsungan cerita itulah harapan bagi masa depan komunitas mereka dapat terus bertahan.
Namun, budaya media arus utama cenderung mengarahkan berita agar cepat dikonsumsi. Padahal di Palestina, jurnalis terpecah antara logika industri media yang menuntut efisiensi, dan tanggung jawab moral untuk menjaga makna dan konteks.
Suatu malam, di ruang redaksi, datang kabar duka dari kota Dura, sebelah barat daya Hebron. Seorang pemuda bernama Mahmoud al-Hroub ditembak mati oleh penembak jitu Israel.
Bagi seorang jurnalis Palestina, kabar ini menggemakan kenangan 21 tahun silam. Ia masih kecil saat itu, duduk di bangku kelas tiga SD, mengenakan mantel warna ceri, menatap foto seorang anak syahid bernama Mahmoud—nama yang sama dengan pamannya, dan kini, dengan pemuda yang baru saja gugur.
Bagaimana mungkin semua ini dirangkum hanya dalam satu baris: “Seorang pemuda Palestina gugur ditembak penembak jitu Israel”?
Lebih dari satu setengah tahun perang ini telah berlalu—perang yang bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi juga mengguncang nilai, makna, dan kesadaran kolektif.
Ada satu perang lain yang lebih senyap: perang melawan kebiasaan, melawan ketumpulan, melawan pelupaan. Perang agar kesadaran tak mati oleh statistik dan headline.
Jurnalis Palestina berada di garis depan dalam pertempuran ini—berusaha menjaga akal dan nurani tetap terhubung pada rasa sakit, dan pada kebebasan.
Ia harus terus memiliki keberanian untuk menyebut kejahatan sebagai kejahatan, bahkan jika terlihat “sepele” dibandingkan dengan kehancuran di Gaza.
Justru karena kedahsyatan tragedi di Gaza, ada risiko besar bahwa kekejaman di tempat lain—termasuk di Tepi Barat—dianggap biasa. Sebuah normalisasi yang berbahaya. Karena itulah, suara jurnalis Palestina tak boleh padam.
Hati yang bertahan di tengah kepungan
Pada Januari 2023, rumah milik Basma Sa’diyah di Kamp Pengungsi Jenin berubah menjadi puing. Bangunan itu runtuh sebagian, menjadi tumpukan reruntuhan yang mengenaskan.
Mesin jahit dan kios kecil tempat ia dan saudara perempuannya menggantungkan hidup turut hancur.
Gudang bahan makanan keluarga pun tak luput dari kehancuran—ruang yang sebelumnya menyimpan kebutuhan dasar selama setahun itu kini porak-poranda.
Basma—masih terjebak dalam keterkejutan dan amarah—menerima tamu yang hilir mudik, ada yang datang menenangkan, ada pula yang menawarkan bantuan memperbaiki kerusakan.
Di antara para tamu itu, hadir pula tim jurnalis yang datang meliput kehancuran rumahnya, bekas dijadikan markas militer oleh tentara Israel.
Di lantai atas rumah, para serdadu meninggalkan coretan penuh umpatan dan ancaman pembunuhan di dinding.
Di gudang makanan, minyak goreng, deterjen, dan selimut dicampuradukkan dengan sengaja hingga tak ada yang bisa diselamatkan.
Namun, yang paling menyakitkan bukan hanya kerusakan fisik—melainkan kemarahan yang meledak dalam diam di dada Basma. Sakit yang bahkan bisa dirasakan oleh siapa saja yang mendengar kisahnya.
Meski demikian, ia tetap memerhatikan para jurnalis di rumahnya. Ia tahu siapa yang belum sempat disuguhi karena terlalu sibuk, dan membawakan sendiri jamuan ke tangan mereka. Di tengah reruntuhan dan luka, ia menjaga adab dan kehormatan.
Kelembutan semacam ini, yang lahir dari keteguhan hati dan kesadaran kultural, tidak boleh hilang dalam ingar-bingar narasi besar.
Kisah seperti ini penting untuk dicatat—karena ia menjadi saksi bahwa nilai-nilai masyarakat Palestina tetap bertahan, bahkan di tengah upaya penghapusan eksistensi mereka.
Penyingkiran lapangan, penyingkiran kemungkinan
Pada 15 Januari 2023, catatan harian seorang jurnalis Palestina merekam hal yang ganjil sekaligus memilukan:
“Menjelang fajar, Shireen Abu Akleh datang dalam mimpiku. Ia tampak tenang, lembut, berdiri di dapur indah yang disinari cahaya matahari pagi. Ia membuat roti dengan cara yang anggun dan diam. Dapur itu berada di tengah medan perang yang penuh dentuman dan reruntuhan. Tapi Shireen tetap membuat roti, diam dan damai, seolah perang tak pernah ada.”
Namun, sebelum matahari tenggelam di hari yang sama, kabar duka datang: Samer Abu Daqa, jurnalis Al Jazeera di Khan Younis, gugur dalam serangan udara.
Ia menyusul Shireen, menambah panjang deretan jurnalis Palestina yang gugur dalam tugas. Di kantor Al Jazeera di Ramallah, foto Samer kini terpampang berdampingan dengan foto Shireen.
Setelahnya, foto-foto lain terus bertambah—hingga lebih dari 210 jurnalis Palestina gugur sejak perang dimulai.
Di Jenin, jasad jurnalis perempuan Shatha al-Sabbagh diangkat rekan-rekannya yang dulu menemaninya di lapangan.
Ia tewas oleh peluru yang diduga dilepaskan aparat Otoritas Palestina, menurut pernyataan keluarganya. Shatha, seperti jurnalis lain, bercita-cita muncul dalam satu bingkai bersama rekan-rekannya—tapi bukan sebagai jenazah.
Pertanyaan berat pun muncul: “Di pundak siapa kelak jenazahku akan dibawa? Oleh peluru siapa?” Pertanyaan-pertanyaan ini berputar terus dalam benak jurnalis Palestina, yang terus mencoba menyalakan harapan, walau realitas semakin gelap.
Lebih dari sekadar kehilangan ratusan insan media, mesin perang Israel telah merampas kemungkinan: kemungkinan kolaborasi lintas wilayah, ruang temu antara jurnalis Gaza dan Tepi Barat.
Seandainya tak ada pemisahan paksa yang berlangsung lebih dari seperempat abad ini, mungkin ada ruang untuk pertemanan, karya bersama, dan jaringan solidaritas. Tapi semua itu kini telah disingkirkan oleh tembok dan darah.
Tidur yang tidak pernah penuh
Bagi jurnalis Palestina, hubungan dengan tidur dan pagi hari selalu erat dengan kesiapsiagaan. Pagi-pagi mereka kerap dibangunkan oleh kabar duka.
Seperti ketika Shireen Abu Akleh gugur di Jenin dalam sebuah serangan pagi hari. Atau baru-baru ini, ketika fotografer Fatima Hassouna meninggal di Gaza.
Tidur kini menjadi jeda yang tak pernah benar-benar menenangkan. Sejenak mata terpejam, lalu kabar baru datang, menghantam kesadaran seperti kapak.
Misalnya saat kabar kematian Hamzah Wael al-Dahdouh—jurnalis muda, anak dari jurnalis veteran Al Jazeera, Wael al-Dahdouh—datang menyayat. Wajahnya kini tergabung dalam jajaran foto-foto para syuhada media.
Menjadi jurnalis di Palestina hari ini berarti harus terus berjuang melawan pertanyaan mengerikan: “Siapa selanjutnya?” Dan lebih dari itu, berharap agar tak perlu menambahkan satu bingkai foto lagi.
Beberapa bulan kemudian, di akhir Juli 2024, setelah meliput intens pembunuhan kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran, seorang jurnalis tertidur kelelahan.
Ia lalu terbangun oleh kabar gugurnya rekannya, jurnalis senior Ismail al-Ghoul. Tidak ada kata-kata yang cukup menggambarkan getirnya perasaan itu.
Kesedihan yang menghantam bagai longsor. Saat itu, bahkan air mata pun bingung harus turun dengan cara apa.
Israel tidak hanya membunuh mereka yang hidup, tapi juga menghabisi kemungkinan. Namun dari kehampaan ini, muncul kemungkinan lain: keberanian untuk mengabadikan yang masih tersisa.
Seandainya tidak ada pemisahan, mungkin para jurnalis dari Gaza dan Tepi Barat bisa duduk bersama di ruang redaksi, berbagi kisah dan mimpi.
Tapi sejarah dan kekuasaan telah merampas ruang itu—sehingga hari ini, satu-satunya ruang bersama yang tersisa adalah duka.
Namun bahkan dari duka, mereka masih melaporkan. Masih merekam. Masih percaya bahwa dunia perlu tahu.
Meluas ke dalam, selamat ke luar
Di sebuah kawasan pinggiran di sisi timur Kota Al-Bireh, seorang jurnalis perempuan Palestina mengemudi pelan, melintasi jalan yang membelah satu-satunya bukit yang belum tertelan oleh hutan beton yang kini mendominasi Ramallah dan Al-Bireh.
Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, jiwanya terkikis oleh liputan-liputan mendesak yang tak kunjung usai—oleh peristiwa-peristiwa yang terlalu cepat, terlalu berat, dan terlalu dekat.
Tak ada waktu untuk jeda. Tak ada ruang untuk lari ke desa-desa dan pemandangan alam yang menenangkan. Kota terasa sempit, sama sempitnya dengan waktu.
Lama-lama, jalanan itu pun lengang. Hanya beberapa anak kecil yang bermain bola, menjadikan jalan sebagai kerajaan mereka sendiri. Sebuah mobil dari sekolah mengemudi perlahan, lalu tiba-tiba berbalik arah.
Sang pelatih mengisyaratkan kepada jurnalis itu: di ujung jalan, ada pos militer. Melanjutkan berarti membuka kemungkinan disapa peluru—satu atau lebih.
Kota hari itu seolah menekan dari segala penjuru. Jantung sang jurnalis berdegup mencari satu-satunya gunung tempat burung masih bisa terbang bebas, seperti yang selalu ia bayangkan.
Dan di saat itu juga, bait puisi karya Walid Saif menyeruak ke dalam kesadarannya, seperti tangan yang diulurkan dalam gelap:
“Dan aku adalah terbang menuju langit, aku adalah batas-batas yang terbuka,
dalam sekejap yang melahirkan waktu tapi tak dikungkung olehnya.
Aku adalah ruang bagi siapa saja yang tujuan-tujuannya terlalu tinggi dan tak lagi muat dalam ruang.”
Tepi Barat kini telah dijadikan ladang peluru. Maka, pertanyaannya: ke mana hendak meluas seorang jurnalis yang jiwanya telah digerus oleh kepungan dan kesunyian?
Jawabannya: ke dalam. Ke puisi. Ke ranah batin.
Itulah perluasan yang masih mungkin—al-ittisāʿ nahwa ad-dākhil—melebar ke dalam diri sendiri.
Kemampuan membangun semesta batiniah yang lapang, tempat peristiwa-peristiwa bisa dilihat sebagai bagian dari hikmah semesta. Dunia batin yang tak menafikan rasa sakit, tapi juga tidak meniadakan hidup.
Pelebaran ini, atau keselamatan ke dalam diri, menjadi satu-satunya bentuk perlawanan yang masih tersisa.
Ia adalah kekuatan sunyi yang membuat jurnalis Palestina tetap mampu berdiri—tetap mampu mencatat, tetap mampu bertanya, tetap mampu menyusun narasi atas pembantaian yang mencoba menghapus eksistensi mereka dalam diam.
Sampai tiba saatnya mimpi Shireen Abu Akleh terwujud. Mimpi seluruh tubuh jurnalistik Palestina: meliput detik-detik kebebasan tanah air mereka.