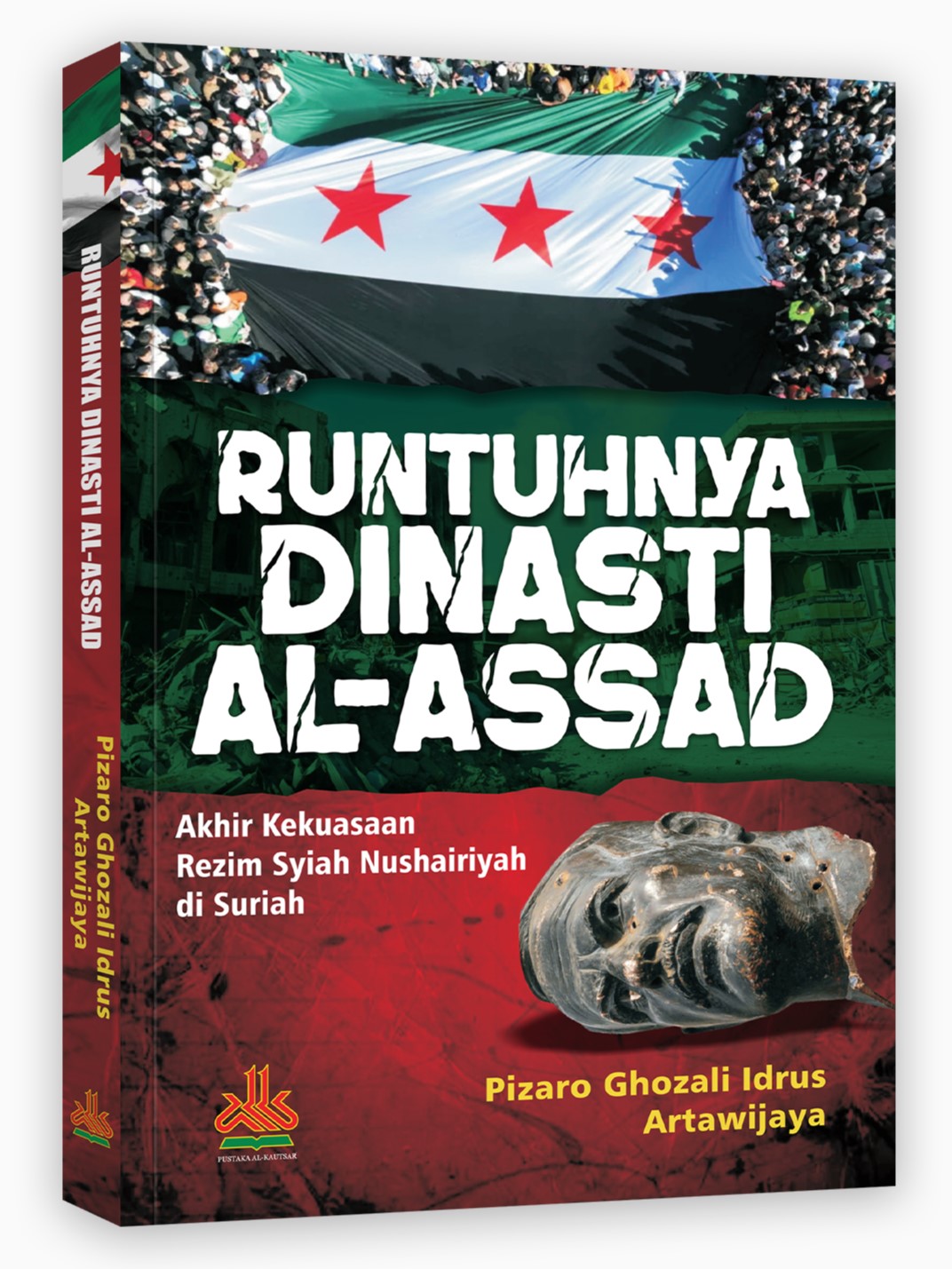Oleh: Ahmed Al-Atawneh*
Sejak awal agresi Israel ke Jalur Gaza yang meletus pada Oktober 2023 dan berkembang menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di abad ini, Amerika Serikat (AS) tampil sebagai aktor kunci.
Tidak hanya sebagai mediator atau fasilitator dalam upaya gencatan senjata, tetapi juga sebagai pihak yang—secara langsung maupun tidak—terlibat dalam dinamika dan arah perang.
Dalam berbagai perjanjian dan negosiasi gencatan senjata, Washington tak jarang menyebut dirinya sebagai penjamin atau pengawas pelaksanaan kesepakatan.
Namun di saat yang sama, AS tetap menjadi mitra strategis dan pendukung utama militer Israel.
Hubungan ini bahkan tampak kian erat dan terbuka, tidak hanya dalam bentuk bantuan senjata, tetapi juga dukungan politik dan diplomatik secara menyeluruh.
Lebih dari itu, sejumlah pengamat dan laporan menunjukkan bahwa berbagai konflik di kawasan—termasuk agresi terhadap Yaman dan ketegangan dengan Iran—pada hakikatnya juga mencerminkan kepentingan dan peran aktif AS, dengan Israel sebagai ujung tombaknya di medan perang.
AS memainkan peran ganda dalam perang ini. Ketika situasi menuntut respons militer, Washington mengirim kapal induk, kapal perang, hingga sistem persenjataan mutakhir ke kawasan.
Bahkan dalam beberapa kesempatan, seperti serangan ke wilayah Yaman dan Suriah, pesawat tempur Amerika dilaporkan langsung melakukan serangan dari berbagai pangkalan di dunia.
Sebaliknya, ketika diperlukan pendekatan diplomatik atau hukum internasional, Washington mengaktifkan mesin politiknya.
Baik melalui Departemen Luar Negeri, Dewan Keamanan Nasional, maupun dalam forum-forum internasional seperti PBB.
Tujuannya, untuk mengarahkan narasi, melindungi kepentingan sekutunya, serta menghambat setiap langkah yang bisa membatasi ruang gerak militer Israel.
Dalam konteks Gaza, AS menempatkan dirinya sebagai mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata.
Namun, peran ini dinilai sebagian pihak justru sebagai bagian dari strategi untuk mengelola perang, bukan menghentikannya.
Bukannya menghentikan kekerasan, proses negosiasi justru digunakan untuk mempertahankan tekanan terhadap kelompok perlawanan Palestina dan memuluskan agenda politik serta militer Israel.
Tiga hal mencerminkan sikap ambigu Washington:
Pertama, keselarasan visi antara pemerintah AS dan Israel terhadap tujuan akhir perang, terutama dalam hal “penghapusan total” kekuatan perlawanan Palestina, pembongkaran struktur politik dan militernya, serta kontrol penuh atas Jalur Gaza.
Hal ini menjadikan negosiasi yang berjalan tak berujung pada penghentian perang secara permanen ataupun penarikan penuh pasukan Israel, melainkan fokus pada pembebasan sandera Israel dan upaya membuka celah untuk perubahan demografi dan politik di Gaza.
Kedua, di hadapan publik, terutama pada masa pemerintahan Biden, AS menampilkan citra sebagai pihak yang peduli terhadap penyelesaian damai dan perlindungan warga sipil.
Namun secara paralel, Washington tetap melanjutkan bantuan militer secara masif dan menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan resolusi yang dapat menghentikan pembantaian dan blokade di Gaza.
Ketiga, keterlibatan penuh Amerika dalam proses negosiasi dan perumusan isi kesepakatan, di mana pihak AS kerap dianggap bukan lagi penengah, melainkan rekan strategis Israel.
AS disebut menyusun taktik dan bahkan redaksi teks perjanjian bersama Tel Aviv, menjebak kelompok perlawanan dalam pilihan-pilihan sulit yang—jika ditolak—akan memunculkan kesan bahwa mereka menolak perdamaian dan membiarkan rakyatnya terus menderita.
Dengan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan fundamental: Apakah benar AS menginginkan perang di Gaza berakhir, atau justru mengelolanya agar berlangsung sesuai kepentingan strategisnya?
Apa pun jawabannya, yang nyata adalah: penderitaan warga sipil Palestina terus berlangsung.
Rumah sakit lumpuh, bahan pangan dan bahan bakar menipis, dan ribuan keluarga terjebak dalam reruntuhan konflik tanpa kepastian kapan dan bagaimana semuanya akan berakhir.
Dalam setiap babak negosiasi yang menyertai agresi Israel atas Jalur Gaza, AS tak sekadar tampil sebagai mediator.
Ia, dalam banyak kasus, juga menyusun draf kesepakatan bersama Israel, lalu mengajukannya kepada pihak Palestina—khususnya Hamas—dengan mengesankan seolah dokumen itu lahir dari proses yang seimbang. Namun kenyataannya, tidak demikian.
Salah satu bukti nyata adalah insiden seputar proposal yang dibawa oleh Bishara Bahbah, mewakili mediator Amerika, Steven Wikoff dalam putaran perundingan terakhir.
Usulan yang diajukan Bahbah sempat didiskusikan dengan para pemimpin Hamas dan akhirnya mendapatkan persetujuan.
Tapi kemudian, baik Israel maupun AS justru menolaknya. Tak berhenti di situ, Hamas malah dituduh keras kepala dan tak bersedia menerima “proposal asli” yang diklaim berasal dari Weikoff.
Insiden semacam ini mencerminkan pola yang lebih luas: penolakan konsisten oleh Amerika dan Israel terhadap keterlibatan pihak lain dalam proses perundingan.
Usulan untuk melibatkan negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, atau Turki sebagai penjamin kesepakatan damai selalu dimentahkan.
Hanya Amerika, ditambah mediator regional seperti Mesir dan Qatar, yang diizinkan berada di meja perundingan.
Dengan demikian, Israel tetap bisa memaksakan kehendaknya tanpa adanya pengawasan atau pembatasan sejati dari komunitas internasional.
Dalam beberapa kesempatan, faksi-faksi Palestina telah mengajukan rancangan solusi politik yang komprehensif.
Salah satu yang terbaru adalah “Kesepakatan Paket Menyeluruh” (Comprehensive Package Deal) yang diumumkan oleh Hamas.
Proposal ini mencakup pertukaran tahanan secara menyeluruh, penghentian perang secara permanen, penarikan penuh militer Israel dari Gaza, pembentukan otoritas sipil Palestina yang disepakati bersama, serta keterlibatan pihak internasional dan regional untuk menjamin implementasinya.
Tetapi lagi-lagi, inisiatif ini ditolak—pertama-tama oleh Washington, sebelum kemudian juga oleh Tel Aviv.
Bahkan tidak diberi ruang untuk didiskusikan lebih lanjut dalam kerangka perundingan formal.
Lebih jauh lagi, AS tidak pernah, sekalipun, mendorong pendekatan politik yang menjamin adanya pemerintahan sipil Palestina di Gaza.
Sebaliknya, sejumlah pernyataan dan ancaman yang muncul dari kalangan pembuat kebijakan AS justru sejalan, bahkan kadang melampaui posisi Israel.
Yaitu, mulai dari gagasan pemindahan paksa warga Gaza (deportasi), kontrol penuh atas wilayah tersebut, hingga ide absurd menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”.
Semua ini tidak hanya mengabaikan hak-hak rakyat Palestina, tetapi juga secara terang-terangan mengancam eksistensi mereka di tanahnya sendiri.
Di ranah hukum internasional, dukungan Amerika kepada Israel pun sangat kentara. Tekanan terhadap negara-negara yang menggugat Israel di Mahkamah Internasional, seperti Afrika Selatan, serta sanksi terhadap pejabat Mahkamah Pidana Internasional yang menyelidiki kejahatan perang di Gaza, menjadi bukti konkret bahwa Washington tak segan menggunakan kekuatannya untuk melindungi sekutunya dari akuntabilitas global.
Dari semua bukti itu, satu kesimpulan kian terang: AS bukan sekadar mediator, melainkan aktor utama dalam agresi terhadap Gaza—dan lebih luas lagi, terhadap kawasan Timur Tengah.
Perang ini adalah bagian dari proyek strategis Amerika untuk merancang ulang tatanan kawasan sesuai dengan kepentingan hegemoniknya, dengan menjadikan Israel sebagai pusat dari arsitektur kekuasaan itu.
Dengan demikian, peperangan yang terjadi bukan hanya soal konflik Israel-Palestina. Ia adalah mekanisme untuk memperbarui dominasi Amerika, menegaskan peran tunggalnya dalam urusan kawasan, serta memperkuat Israel sebagai instrumen kolonial-imperialis yang siap digunakan untuk jangka panjang.
Berdasarkan kenyataan ini, muncul urgensi untuk mengevaluasi total pendekatan terhadap proses perdamaian. Ketergantungan penuh pada AS sebagai penengah bukan hanya tidak realistis, tetapi berbahaya.
Karena itu, bangsa Palestina dan dunia Arab-Islam harus mulai membangun poros alternatif: menjajaki mediator baru, menggalang dukungan diplomatik dari negara-negara non-Barat, dan membentuk jaringan solidaritas yang lebih luas.
Lebih dari itu, harus ada kesadaran kolektif bahwa ancaman dari dominasi Amerika ini tidak berhenti di Gaza.
Ia menjalar ke kawasan lain, menciptakan ketidakstabilan yang menyentuh jantung keamanan nasional banyak negara Arab dan Muslim.
Jika negara-negara di kawasan ini menyadari bahwa masa depan mereka sedang dipertaruhkan, maka inilah saatnya untuk bertindak bersama.
Bukan sekadar untuk membela Palestina, tetapi untuk mempertahankan eksistensi dan kemerdekaan kawasan dari proyek-proyek hegemonik global yang terus berjalan tanpa henti.
*Ahmed Al-Atawneh merupakan Direktur Pusat Visi untuk Pengembangan Politik. Ketua Dewan Pembina Universitas Hebron, Palestina. Ia juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Hebron. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Kaifa Adārat Amrīkā Ta’āmaluhā Ma’a Ḥarbi Ghazah”.