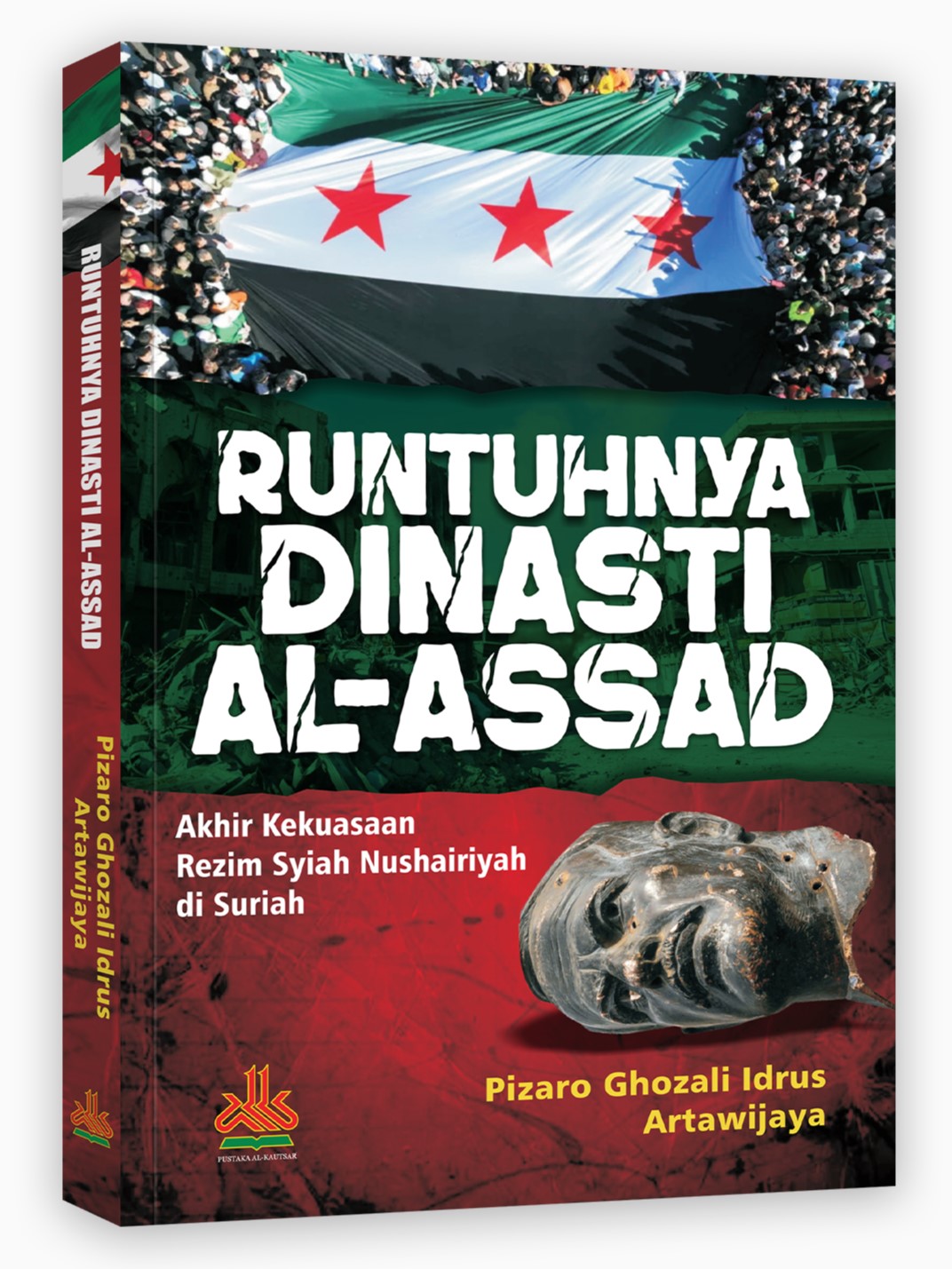Oleh: Saeed Al-Hajj*
Keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai Jalur Gaza membuka jalan menuju fase kedua “Rencana Damai Trump”, sebuah langkah yang sarat risiko bagi masa depan persoalan Palestina.
Deretan tanda tanya pun kini mengemuka terkait cara implementasi keputusan itu serta peluang keberhasilannya.
Tidak mengherankan jika faksi-faksi Palestina segera mengeluarkan peringatan tentang konsekuensi yang mungkin timbul.
Mengapa demikian?
Pada Selasa dini hari lalu, Dewan Keamanan mengadopsi rencana Presiden AS Donald Trump terkait Gaza melalui pengesahan rancangan resolusi yang diajukan Washington.
Sebanyak 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan memberikan persetujuan, sementara Rusia dan Tiongkok memilih abstain.
Hasil itu terbilang cepat dan mulus—jauh di luar perkiraan banyak pihak yang sebelumnya menilai proses akan tersendat, terutama karena adanya usulan tandingan dari Rusia.
Namun ada 2 faktor utama yang mendorong hasil tersebut: tekanan intensif dari pemerintahan AS agar resolusi disahkan.
Selain itu dukungan dari 8 negara Arab dan Islam yang sejak awal menyatakan menerima kerangka “Rencana Trump”.
Rusia dan Tiongkok sejatinya memiliki banyak alasan untuk menolak. Rancangan resolusi itu tidak memuat komitmen eksplisit terhadap “solusi dua negara” dan sejumlah ketentuannya dinilai terlalu kabur.
Selain itu, kedua negara waspada terhadap langkah AS yang kembali mengambil peran dominan di kawasan.
Namun dukungan “kelompok delapan negara” dan persetujuan dari otoritas Palestina menempatkan resolusi tersebut seolah telah memperoleh legitimasi kolektif.
Ruang manuver Rusia dan Tiongkok pun menyempit; keduanya tidak ingin tampak lebih “keras” dibanding negara-negara Arab sendiri.
Karena itu, usulan Rusia tidak pernah menjelma hambatan nyata, dan baik Moskwa maupun Beijing juga tidak menggunakan hak veto.
Keduanya cukup menyampaikan kekhawatiran bahwa resolusi tersebut dapat “memperburuk krisis”.
Sebagian pihak menilai dukungan negara-negara Arab didorong oleh keinginan menghindari benturan langsung dengan Washington.
Ada harapan bahwa penghentian serangan dan stabilisasi gencatan senjata harus diutamakan untuk mencegah kembalinya tingkat kekerasan seperti sebelumnya.
Tak tertutup kemungkinan bahwa dukungan itu lahir dari kesepakatan tersirat atau janji-janji yang diberikan AS mengenai mekanisme implementasi resolusi tersebut.
Namun semua itu tidak meniadakan implikasi serius pada jangka panjang apabila resolusi dilaksanakan apa adanya.
Keseimbangan kekuatan akan selalu condong ke arah Israel yang memperoleh dukungan penuh dari AS.
Terlebih lagi, dalam setiap tahapan implementasi, Presiden Trump tampak memberi sinyal kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa kelanjutan operasi militer tetap terbuka.
Risiko yang mengintai
Tidak berlebihan bila isi resolusi ini digambarkan berpotensi membawa dampak destruktif. Pertama-tama, teks resolusi menggeser narasi perang.
Israel digambarkan sebagai pihak yang diserang, sementara konteks pendudukan dan kehancuran besar yang menimpa Gaza tidak mendapatkan ruang.
Istilah “terorisme” menjadi fokus, bukan blokade, bukan serangan berkepanjangan, bukan pula ribuan korban sipil.
Dengan demikian, pihak Palestina, secara tersirat, diposisikan sebagai pihak yang harus “menghentikan kekerasan” dan “menata ulang” diri mereka melalui rangkaian reformasi.
Sebaliknya Israel menjadi mitra dalam semua mekanisme yang dibentuk—mulai dari komite pemilihan otoritas Palestina hingga pembentukan pasukan keamanan.
Secara politik, resolusi ini menunjukkan kemunduran dari prinsip “solusi dua negara” yang selama puluhan tahun menjadi landasan diplomasi internasional.
Sebagai gantinya, muncul gagasan abstrak mengenai “jalur menuju penentuan nasib sendiri” yang mungkin, suatu hari nanti, menghasilkan negara Palestina.
Itu pun hanya bila otoritas Palestina menjalankan “reformasi secara menyeluruh” dan ada kemajuan signifikan dalam pembangunan kembali Gaza—syarat-syarat yang ditetapkan sepenuhnya oleh AS dan Israel.
Resolusi itu juga memisahkan Gaza dari Tepi Barat dan memperlakukannya sebagai entitas terpisah, berada dalam orbit internasional penuh, di bawah semacam bentuk “perwalian global”.
Di atasnya akan berdiri sebuah “Dewan Perdamaian” yang digambarkan sementara, tetapi berpotensi menjadi permanen.
Di bidang keamanan, Pasukan Stabilitas Internasional yang diatur dalam resolusi memiliki mandat “menstabilkan lingkungan keamanan” dengan cara “mengosongkan Gaza dari senjata”, termasuk menghancurkan seluruh infrastruktur militer faksi-faksi perlawanan.
Dengan kata lain, pasukan internasional diharapkan melaksanakan tugas-tugas yang selama ini gagal dicapai Israel secara penuh.
Tanpa standar yang jelas maupun daftar negara peserta, rancangan ini lebih menyerupai perluasan “Pusat Koordinasi AS” ketimbang pembentukan pasukan perdamaian PBB.
Secara operasional, kekhawatiran terbesar adalah bahwa resolusi ini dapat menjadi alat legitimasi bagi pendudukan berkepanjangan.
Tidak ada peta jalan, tidak ada batas waktu, dan penarikan pasukan bergantung pada kesepakatan antara Israel, pasukan internasional, negara-negara penjamin, dan AS.
Semuanya kembali ditautkan pada satu syarat: “penyelesaian proses pelucutan senjata”.
Pada tahap tertentu, struktur semacam ini berpotensi mempertahankan pendudukan atau bahkan membagi Gaza secara de facto.
Sebagaimana pernah diisyaratkan oleh dokumen awal Rencana Trump yang menempatkan masuknya bantuan hanya melalui wilayah yang dikuasai tentara Israel.
Ini dapat menghasilkan pembelahan jangka panjang di sekitar “garis kuning”.
Kemungkinan arah perkembangan
Faksi-faksi Palestina menerima fase pertama rencana Trump dengan pemahaman bahwa mereka menghadapi situasi sangat sulit dan jalur yang tak sepenuhnya dapat dihindari.
Ada kesadaran bahwa Washington akan mendorong transisi cepat menuju fase kedua sebagaimana tercantum dalam teks rencana itu.
Artinya, perang belum sepenuhnya berakhir—hanya berubah bentuk dan babaknya.
Dalam pernyataan yang dirilis seusai keputusan Dewan Keamanan, kelompok-kelompok Palestina—terutama Hamas—menolak resolusi itu.
Penolakan itu karena dianggap melegitimasi “perwalian internasional” atas Gaza serta membuka pintu bagi pengaturan jangka panjang di luar kerangka nasional Palestina.
Namun nada pernyataan mereka tidak mengarah pada eskalasi atau ancaman konfrontatif.
Strategi perlawanan tampaknya bertumpu pada sejumlah prinsip: memastikan gencatan senjata tidak runtuh, menghindari kembalinya pola pembunuhan massal.
Selain itu, fokus pada penyelesaian krisis kemanusiaan—mulai dari masuknya bantuan hingga rekonstruksi—dan menahan diri dari pernyataan bernada ancaman agar tidak dipersalahkan jika perjanjian gencatan buyar.
Di atas semua itu, ada keyakinan bahwa implementasi resolusi pada akhirnya akan menghadapi hambatan besar di bidang politik maupun keamanan.
Pengalaman panjang Palestina menunjukkan bahwa keputusan Dewan Keamanan bukanlah teks sakral.
Kompleksitas lapangan, tumpang tindih kepentingan berbagai pihak, dan ketegangan politik yang terus bergerak sering kali membuat implementasi berbeda jauh dari rumusan awal.
Beberapa negara bahkan telah menyampaikan keengganan mengirim pasukan ke wilayah yang belum benar-benar stabil. Risiko korban dan beban politik di dalam negeri menjadi pertimbangan serius.
Di sisi lain, gagasan pelucutan senjata atau pembubaran faksi-faksi perlawanan sejak lama tidak memiliki landasan sosial maupun politik di Palestina.
Penolakan terhadap gagasan itu sangat kuat—baik di tingkat organisasi, elit politik, maupun masyarakat.
Pada titik ini, implementasi resolusi hampir pasti harus berhadapan dengan realitas bahwa pihak yang distigmatisasi Israel sebagai “teroris” justru akan menjadi salah satu pihak yang diajak bernegosiasi di lapangan.
Media AS bahkan menyebut kemungkinan adanya pertemuan antara utusan khusus AS, Bill Wechtow, dan pimpinan Hamas, sebuah skenario yang ironis karena bertentangan dengan semangat resolusi itu sendiri.
Hingga kini pun belum jelas apakah delapan negara Arab dan Islam yang mendukung resolusi telah menerima jaminan tertulis atau lisan dari AS mengenai mekanisme pelaksanaannya.
Penjelasan mengenai hal itu tampaknya baru akan terlihat dalam waktu dekat.
Penutup: Antara bahaya dan kemungkinan
Tidak ada satu pun resolusi PBB yang pernah berhasil menyelesaikan persoalan Palestina secara tuntas, begitu pula yang satu ini.
Namun, hal itu tidak berarti risiko resolusi tersebut dapat diabaikan. Justru sebaliknya: ia membawa konsekuensi serius bagi masa depan resistensi Palestina, bagi nasib Gaza, dan bagi kemungkinan lahirnya negara serta realisasi hak menentukan nasib sendiri.
Sekali lagi, keputusan internasional bukanlah takdir final. Keseimbangan kekuatan memang menentukan banyak hal, tetapi bukan segalanya.
Persoalan Palestina terlalu panjang, terlalu dalam, dan terlalu kompleks untuk ditentukan oleh satu resolusi, apalagi resolusi yang lahir dalam kondisi timpang.
Yang jelas, resolusi ini menandai babak baru dalam perjalanan pergulatan panjang rakyat Palestina.
Babak yang menuntut strategi baru, perangkat perlawanan baru, dan pemahaman lebih jernih terhadap dinamika regional maupun internasional yang terus bergerak.
*Saeed Al-Hajj merupkan peneliti yang berspesialisasi dalam urusan Turki, isu Palestina, dan urusan regional. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Khuṭṭah Trāmb al-Tsāniyyah ‘Alā al-Abwāb”.