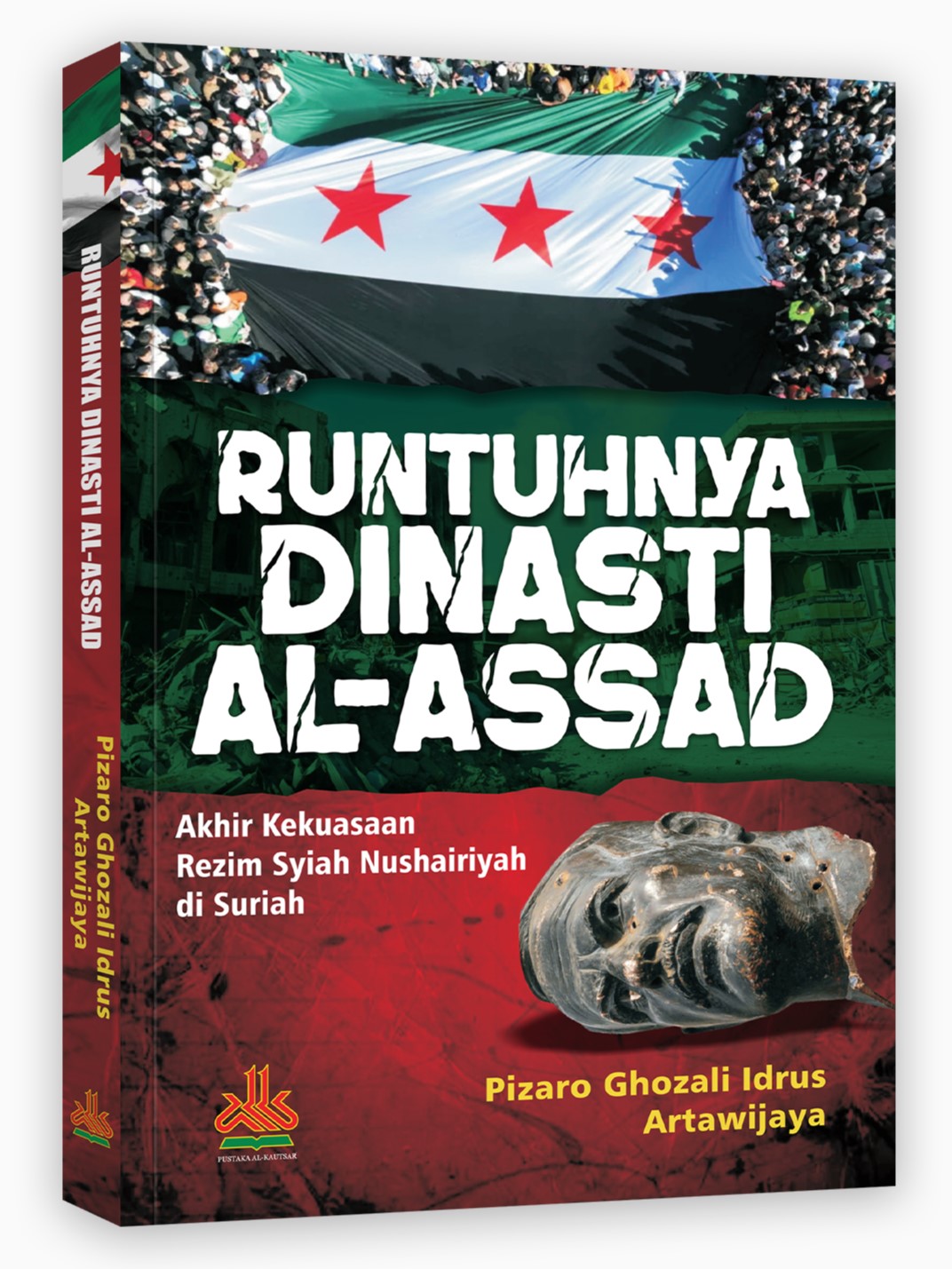Oleh: Oraib al-Rantawi*
Gaza tampaknya berada di ambang babak akhir dari perang panjang yang melilitnya selama lebih dari 20 bulan.
Perang pengepungan, pembersihan, pemusnahan, dan kelaparan yang dilancarkan terhadap wilayah kecil yang padat penduduk ini kini tampaknya tengah menuju titik penghabisan.
Gaza bersiap untuk menghitung jumlah syuhada, korban luka, serta mereka yang hilang—dan tampaknya angka yang akan muncul jauh lebih besar dari yang telah diketahui selama ini.
Namun, jika berkaca pada pengalaman masa lalu bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahan sayap kanan ultra-nasionalis yang dipimpinnya—pemerintahan yang dikenal tidak menepati janji dan kerap mengingkari kesepakatan—maka tak ada tempat bagi optimisme yang berlebihan.
Harapan akan akhir penderitaan Gaza harus tetap bersandar pada kenyataan, dan baru bisa diyakini jika benar-benar terwujud dalam realitas di lapangan.
Meski demikian, harapan akan segera berhentinya bencana kemanusiaan ini memang tetap ada—meski sifatnya relatif dan bersyarat. Ada sejumlah faktor, baik dari luar maupun dalam, yang mendukung harapan tersebut.
Namun ada pula faktor-faktor yang bisa membuat harapan itu pupus sebelum sempat tumbuh.
Lima alasan untuk optimisme
Setidaknya ada 5 faktor yang membuat peluang kali ini tampak berbeda dari sebelumnya:
Pertama, dan yang paling utama, adalah dampak dari perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
Netanyahu dan kelompok sayap kanannya kini bisa mengklaim kemenangan “bersejarah”, meskipun diselimuti banyak retorika dan pembesaran makna.
Kemenangan simbolik yang gagal diraih Netanyahu dari Gaza kini dicoba untuk dibentuk dari Iran, Lebanon, dan Suriah.
Narasi ini menjadi penyeimbang atas kebuntuan dan kegagalan mereka di Gaza. Survei opini publik di Israel menunjukkan bahwa Netanyahu dan partainya memperoleh dorongan elektoral dari perang tersebut.
Dalam konteks ini, kesepakatan pertukaran sandera dan penghentian perang bisa menjadi pintu masuk bagi Netanyahu untuk mempertahankan keunggulan politiknya, sebelum dukungan itu menguap akibat jebakan dan kerugian di medan yang tak berujung.
Kedua, Netanyahu tampaknya telah menemukan “jaring pengaman” bagi masa depan politik dan pribadinya, bukan dari dalam negeri Israel, tetapi dari luar: Donald Trump.
Presiden AS itu memberikan “pelampung” yang telah lama ditunggu, dengan mengintervensi jalannya proses hukum di Israel.
Trump mengancam akan menciptakan kekacauan besar jika pengadilan terhadap Netanyahu terus berlanjut.
Langkah itu seolah menjadikan Israel sebagai “republik pisang”, negara yang sistem hukumnya tunduk pada restu luar negeri.
Namun dari perspektif Gaza, yang penting adalah bahwa ketakutan Netanyahu akan masa depan pascaperang perlahan memudar.
Jika keberuntungan memihak, ia akan maju dalam pemilu mendatang—lebih siap dan lebih kuat dibanding masa-masa sebelumnya, bahkan sejak peristiwa 7 Oktober lalu.
Kini, Netanyahu memiliki ruang lebih luas untuk melepaskan diri dari tekanan sekutunya maupun manuver para rivalnya.
Ia paham bahwa “kesepakatan” adalah satu-satunya jalan keluar. Gagal mencapai itu berarti mempertaruhkan hubungannya dengan Gedung Putih, kehilangan kredibilitas yang sempat ia bangun melalui serangan terhadap Iran, dan kembali menempatkan dirinya di bawah bayang-bayang meja hijau.
Ketiga, “maestro” perang dan gencatan senjata di Washington kini melihat Gaza dalam perspektif yang lebih luas—melampaui isu sandera dan gencatan senjata semata.
Washington memandang Gaza dalam kerangka regional: stabilitas keamanan, prospek ekonomi, dan peluang strategis jangka panjang.
Presiden AS saat ini, yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung damai dan pengejar Nobel, mengambil risiko besar dengan melawan Iran.
Kini ia ingin memetik hasilnya dengan merampungkan berbagai kesepakatan besar dalam satu waktu—di mana Israel menjadi bagian dari proses percepatan normalisasi dan meraih keuntungan ekonomi besar.
Ini adalah agenda besar yang tak dapat ditangani oleh visi sempit tokoh-tokoh ekstrem kanan seperti Itamar Ben Gvir maupun Bezalel Smotrich.
Netanyahu, sang “pahlawan perang dan perdamaian” dalam istilah Trump, dianggap sebagai mitra strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan proyek-proyek itu.
Maka tak mengherankan jika isu ini menjadi bahan utama dalam pertemuan Trump-Netanyahu baru-baru ini dan kemungkinan akan kembali dibahas dalam pertemuan mereka berikutnya.
Tidak ada satu pun faktor, baik proses hukum internal maupun dinamika politik domestik Israel, yang boleh menghalangi jalannya proyek ini.
Keempat, militer Israel sendiri sudah mulai menyuarakan bahwa perang telah melampaui tujuannya.
Dalam penilaian militer, antara dua pertiga hingga tiga perempat wilayah Gaza sudah mereka kuasai.
Melanjutkan operasi untuk merebut seluruh Gaza akan membahayakan nyawa para sandera, memerlukan waktu berbulan-bulan, dan memakan korban manusia serta biaya ekonomi yang sangat besar.
Kerugian yang diderita militer Israel selama bulan Juni saja lebih besar dibanding jumlah sandera yang masih hidup.
Tentara mengalami kelelahan fisik dan psikologis akibat lamanya perang dan kerumitannya.
Memang, sebelumnya tentara sudah mengeluh, namun suara mereka tidak didengar oleh kepemimpinan politik yang terjebak dalam agenda sendiri. Tapi setelah perang terhadap Iran, mungkin suasana mulai berubah.
Kelima, gelombang protes di jalanan tidak lagi terbatas pada keluarga sandera, tetapi mulai melibatkan keluarga para prajurit yang bertugas di Gaza.
Semakin banyak tentara Israel yang pulang dalam peti jenazah, dan ribuan lainnya mengalami luka fisik maupun trauma psikologis berat—sebagian bahkan menuju pada kondisi cacat permanen.
Masyarakat Israel mulai merasa bahwa harga yang mereka bayar terlalu tinggi untuk tujuan-tujuan perang yang mereka anggap tidak berkaitan langsung dengan keamanan mereka.
Perangkap dan tantangan di jalan damai
Meski sejumlah faktor menunjukkan adanya celah menuju kesepakatan di Gaza dan sekitarnya, bukan berarti jalan itu kini terbentang luas dan mulus. Realitas politik Israel tetap kompleks dan penuh jebakan.
Dalam watak dasarnya, Benjamin Netanyahu sejatinya tak jauh berbeda dari para pemimpin sayap kanan ekstrem lainnya seperti Itamar Ben Gvir atau Bezalel Smotrich.
Hanya saja, Netanyahu jauh lebih piawai dalam membungkus ekstremismenya dengan gaya diplomatik yang lihai dan penuh manuver.
Koalisi ultranasionalis yang menjadi penopang kekuasaannya masih memiliki kekuatan untuk melumpuhkan jalannya pemerintahan dan Knesset.
Jika kelompok sayap kanan ini bersatu dengan faksi ultraortodoks yang tengah murka karena tuntutan-tuntutan mereka tak terpenuhi, maka stabilitas politik Israel bisa terguncang.
Sementara itu, skenario penyelamatan Netanyahu dari jerat hukum masih belum final. Opsi “amnesti dengan syarat mengundurkan diri dari politik” masih menjadi wacana terbuka.
Begitu pula pemilu dini: apakah akan digelar atau tidak, dalam kondisi seperti apa, dan dengan hasil seperti apa, semuanya masih bersifat spekulatif.
Lebih penting lagi, tak seorang pun tahu pasti apa sebenarnya yang ada dalam benak Donald Trump. Apa isi “paket besar” yang tengah ia siapkan untuk Gaza dan kawasan di sekitarnya? Apakah rencana yang ia pikirkan hari ini akan tetap sama besok, jika dinamika baru muncul?
Belum jelas pula bagaimana Trump memandang Gaza dan perlawanan di dalamnya, bagaimana ia membaca peta kekuasaan di Tepi Barat, bagaimana ia menilai masa depan Otoritas Palestina, serta visi macam apa yang ia susun bagi tatanan kawasan ke depan.
Tiap satu dari pertanyaan ini cukup untuk membalik seluruh kalkulasi politik di kawasan.
Melihat kondisi di tingkat Palestina, regional, dan—yang lebih krusial lagi—dari perspektif AS terhadap Israel, maka dapat diperkirakan bahwa kesepakatan apa pun yang hendak dicapai tidak akan datang dalam satu tahap penuh.
Melainkan akan dibagi ke dalam beberapa tahap terpisah namun saling terhubung, dalam kerangka visi umum yang lebih longgar dan penuh prinsip-prinsip umum.
Dalam konteks inilah, muncul kemungkinan kesepakatan bertahap yang diawali dengan versi modifikasi dari Rencana Biden–Netanyahu atau rencana Weitzman.
Sebuah gencatan senjata selama 60 hari yang disertai dengan pembebasan semua sandera serta masuknya bantuan kemanusiaan bisa menjadi pintu masuk bagi visi AS yang lebih luas.
Dalam tahap ini, Washington akan berkomitmen untuk mengejar penyelesaian menyeluruh mengenai penghentian perang dan skenario pascaperang, sambil mendorong negara-negara Arab lain untuk bergabung dalam kerangka normalisasi “Abraham”.
Israel mungkin akan menerima gagasan ini tanpa secara resmi menyatakan penghentian permanen atas perang.
Namun akan menjadi pengetahuan umum bahwa Israel tidak akan melanjutkan agresinya.
Alasannya sederhana: melanjutkan perang akan bertentangan dengan ambisi besar sang “man of the deal” di Gedung Putih.
Trump telah berhasil “menaruh Netanyahu di bawah ketiaknya”. Tak pernah sebelumnya pengaruh Washington atas dapur pengambilan keputusan Israel sedemikian besar dan mendalam.
Ia berharap Netanyahu akan menjadi mitra dalam mewujudkan agenda-agenda besar itu—dengan imbalan perlindungan dari proses hukum serta dukungan penuh dalam perang maupun “perdamaian paksa” dengan pihak-pihak Arab, termasuk Iran.
Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Trump berupaya menenangkan kubu sayap kanan yang lebih ekstrem dari Netanyahu.
Berapa harga yang harus dibayar oleh rakyat Palestina dari kantong Yerusalem dan Tepi Barat demi menjaga stabilitas koalisi Netanyahu? Dan sejauh mana Otoritas Palestina akan sanggup dan bersedia menyesuaikan diri dengan visi semacam itu?
Pertanyaan besar lainnya: bagaimana reaksi negara-negara Arab yang memiliki bobot geopolitik di kawasan? Apakah mereka akan tetap berpegang pada Inisiatif Perdamaian Arab yang diadopsi tahun 2002, ataukah mereka akan menurunkan standar ke tingkat yang jauh lebih rendah, terutama setelah “Poros Perlawanan” melemah akibat perang-perang dua tahun terakhir?
Menutup catatan ini, Gaza mungkin memang tengah melangkah ke arah akhir penderitaan dan awal pemulihan.
Namun Palestina, sebagai sebuah bangsa dan perjuangan, masih berdiri di gerbang babak strategis baru.
Babak yang ditandai dengan bentuk, cara, dan narasi baru dari konflik panjangnya.
Adapun “perdamaian yang berdasar pada keadilan”, tampaknya belum akan hadir dalam waktu dekat. Ia masih terperangkap dalam permainan lama: jual beli ilusi yang terus dipertontonkan di panggung politik global.
*Oraib al-Rantawi adalah penulis dan analis politik Yordania. Pendiri dan Direktur Jenderal Pusat Studi Politik Al-Quds. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Kaifa Nafhamu Qarār Trāmb bisyani Gazah?”.