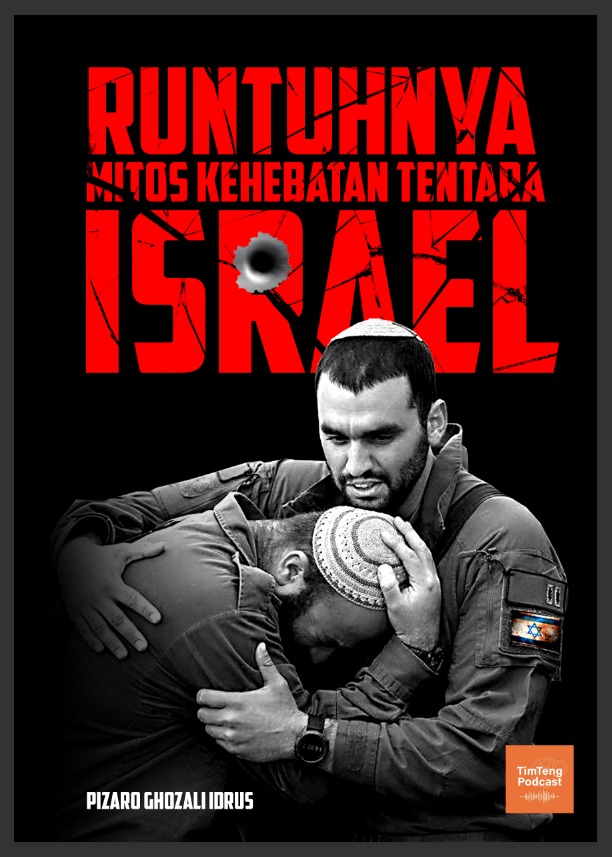Sejak berdirinya pada 14 Mei 1948, Israel tak pernah berhenti mengambil setiap langkah yang dapat menjamin kendali penuh atas sumber daya air Palestina, sekaligus menafikan hak-hak dasar warga Palestina atas air bersih.
Untuk mencapai tujuan itu, otoritas pendudukan menerbitkan serangkaian perintah militer yang secara efektif menempatkan sebagian besar sumber air Palestina di bawah kontrolnya.
Selain itu, Israel juga secara sistematis merusak infrastruktur air di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat Palestina terhadap air bersih dan layak konsumsi.
Air dalam pikiran Zionisme
Sejak awal berdirinya gerakan Zionis, air telah menempati posisi strategis dalam pandangan geopolitik para pendirinya.
Hal itu berakar pada klaim keagamaan dan historis yang menyatakan bahwa “Tanah yang dijanjikan” membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Suriah dan Irak.
Gagasan tersebut mulai mendapat bentuk yang lebih konkret sejak Kongres Zionis Pertama di Basel, Swiss, tahun 1897.
“Di kongres ini, kita telah meletakkan dasar bagi negara Yahudi dengan batas utara yang mencapai Sungai Litani,” tegas Theodor Herzl, sang pendiri gerakan Zionis dalam forum itu.
Pada awal abad ke-20, gerakan Zionis mengirim tim ahli dan komisi ilmiah ke Palestina untuk mempelajari potensi sumber daya air dan kemungkinan memanfaatkan aliran Sungai Yordan.
Pada tahun 1903, gerakan tersebut mencoba berkoordinasi dengan pemerintah Inggris agar mengirimkan tim teknis.
Tujuannya, guna meneliti potensi pengalihan sebagian aliran Sungai Nil ke Semenanjung Sinai, yang kemudian dapat dialirkan ke wilayah Negev untuk dikembangkan dan dijadikan kawasan permukiman Yahudi.
Kemudian, pada 18 Januari 1919, Zionis menekan para peserta Konferensi Perdamaian Paris agar batas wilayah Palestina mencakup hulu Sungai Yordan, Sungai Litani, dan dataran Hauran di Suriah.
Namun, tuntutan itu ditolak, terutama oleh pihak Prancis yang saat itu telah menempatkan Suriah dan Lebanon di bawah mandatnya.
Pada 30 Oktober 1920, pemimpin Zionis Chaim Weizmann mengirim surat kepada Perdana Menteri Inggris David Lloyd George, menyatakan bahwa aliran Sungai Yordan dan Yarmouk tidak akan cukup memenuhi kebutuhan “negara Yahudi”, dan karena itu, air Sungai Litani perlu dimasukkan untuk menutupi kekurangan tersebut dan menjamin pasokan bagi wilayah Galilea.
Pada tahun 1941, David Ben-Gurion, kepala Komite Eksekutif Badan Yahudi di Palestina, menegaskan hal serupa.
“Kita harus memastikan bahwa air Sungai Litani berada dalam batas negara Yahudi agar kelangsungan hidupnya terjamin,” katanya.
Proyek-proyek awal penguasaan air
Selama masa mandat Inggris atas Palestina, gerakan Zionis mengirim sejumlah tim Yahudi untuk melakukan survei sumber air dan merancang proyek-proyek pengelolaan air yang dapat menunjang koloni pemukim Yahudi.
Berbagai proyek dirancang dengan tujuan utama menguasai sumber daya air di kawasan itu.
Beberapa proyek paling menonjol pada masa itu antara lain:
- Proyek Rutenberg (1927)
Proyek ini memberikan hak konsesi pemanfaatan air kepada sebuah perusahaan Yahudi, yang memberi gerakan Zionis kendali atas bagian penting dari sumber daya air Palestina.
- Proyek Ionides (1939)
Rencana ini mengusulkan pengalihan sebagian aliran Sungai Yarmouk melalui kanal yang melintasi wilayah Yordania, untuk mengumpulkan air dari lembah-lembah Zalqaab dan Arab, menyimpan kelebihan air Yarmouk di Danau Tiberias, serta menyalurkan air dari sumber Ras al-Ain ke kota-kota Yerusalem, Jaffa, dan Tel Aviv.
Rencana itu juga memberi Inggris hak untuk menyerahkan konsesi eksploitasi air sungai Yordan, Yarmouk, Na’aman, dan Auja kepada perusahaan-perusahaan Zionis.
- Proyek Lowdermilk (1944)
Proyek ini menaksir total aliran Sungai Yordan mencapai 1,8 miliar meter kubik per tahun. Sebanyak 800 juta meter kubik di antaranya direncanakan untuk mengairi 540.000 dunam (1 dunam = 1.000 m²), sedangkan 1 miliar meter kubik sisanya untuk produksi listrik.
Proyek itu merekomendasikan agar seluruh pengelolaan diserahkan kepada otoritas Yahudi.
Gagasan ini kemudian diwujudkan melalui Proyek Hays (1944), yang menitikberatkan pada pemanfaatan aliran Sungai Yordan untuk mendukung pembangunan permukiman Israel.
Penguasaan air setelah berdirinya Israel
Setelah Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada 1948, pemerintah barunya segera mengesahkan keputusan penting pada Agustus 1949 yang disebut “Nasionalisasi Air”.
Keputusan itu menyatakan bahwa “segala sumber air adalah milik negara dan hanya negara yang berhak mengatur penggunaannya; individu tidak berhak memiliki atau memperdagangkannya.”
Pelaksanaan keputusan ini diserahkan kepada Menteri Pertanian, dibantu oleh seorang Komisioner Air yang bertugas mengatur izin pengambilan air dalam jumlah tertentu oleh individu atau kelompok.
Israel sejak dini memusatkan perhatian pada kawasan Lembah Yordan, dan melalui diplomat Moshe Sharett, membahas dengan utusan Amerika Eric Johnston pentingnya menjamin kendali Israel atas seluruh sumber air.
Termasuk Sungai Litani, sambil mengupayakan agar batas geografis Israel dapat disesuaikan dengan sebaran sumber air tersebut.
Antara 1953 dan 1955, Johnston menyusun apa yang dikenal sebagai “Rencana Air Terpadu Lembah Yordan”, yang bertujuan mengatur penggunaan air antarnegara di kawasan itu.
Dalam rancangan tersebut, warga Palestina di Tepi Barat dijatah antara 200 hingga 320 juta meter kubik air per tahun. Namun, Israel menolak mematuhi ketentuan itu.
Pada tahun 1964, Israel merebut bagian air yang semestinya menjadi hak Palestina dengan mengalirkannya ke Danau Tiberias, lalu memompanya ke wilayah Israel melalui “Saluran Nasional Air”.
Langkah ini menyebabkan turunnya permukaan air Sungai Yordan dan meningkatnya kadar garam di dalamnya.
Israel juga memompa lebih dari 450 juta meter kubik air setiap tahun ke wilayah Negev dan daerah pesisir selatan.
Pada tahun 1955, Ben-Gurion kembali menegaskan bahwa Israel sedang berperang dengan bangsa Arab demi air. Nasib Israel bergantung pada hasil perang ini.
“Jika kita gagal, maka kita tak akan bertahan di Palestina,” tegasnya.
Antara tahun 1950 dan 1957, Israel berhasil mengeringkan Danau Huleh di Galilea.
Setelah itu, proyek besar lain dikenal sebagai “Rencana Smith” atau “Rencana Tujuh Tahun” (1953–1960) dilaksanakan untuk meningkatkan produksi air dari 810 juta meter kubik pada 1953 menjadi 1,73 miliar meter kubik pada 1960.
Setelah kekalahan negara-negara Arab dalam Perang Juni 1967, Israel segera bergerak menguasai hampir seluruh sumber air Palestina.
Pompa-pompa air dihancurkan, lahan pertanian di sepanjang Sungai Yordan rusak berat, dan banyak daerah kehilangan pasokan utama air irigasi.
Menjelang akhir tahun itu, Israel membentuk komisi khusus untuk meneliti potensi eksploitasi sumber daya alam di wilayah pendudukan, termasuk sumur-sumur air di sekitar Betlehem, yang kemudian dimasukkan ke dalam batas permukiman Gush Etzion.
Otoritas pendudukan juga dengan sengaja mendirikan permukiman di atas cekungan-cekungan air utama di Tepi Barat, menguras sumber air secara besar-besaran, dan merusak ribuan hektar lahan pertanian milik warga Palestina.
Sebuah laporan rahasia yang diungkap kolumnis militer Zeev Schiff di harian Haaretz pada 6 Oktober 1999 menyebutkan bahwa Israel harus tetap menguasai wilayah tertentu di Tepi Barat.
Tujuannya, untuk mencegah warga Palestina menggunakan air tanah secara berlebihan, karena sumber itu juga menjadi pemasok utama bagi Yerusalem dan dataran pesisir.
Perintah militer untuk kuasai air Palestina
Sejak 1967, Israel menerbitkan sejumlah perintah militer yang dirancang untuk menempatkan seluruh sumber air di bawah kendalinya dan mencabut hak-hak air warga Palestina.
Berikut adalah beberapa ketentuan paling penting yang dikeluarkan setelah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza:
- Perintah Militer No. 1 (7 Juni 1967)
Menetapkan bahwa seluruh sumber air di wilayah pendudukan dianggap sebagai milik Negara Israel.
- Perintah Militer No. 92 (15 Agustus 1967)
Memberikan kewenangan penuh kepada seorang “Perwira Air Israel”—yang ditunjuk oleh pengadilan Israel—untuk mengatur seluruh urusan yang berkaitan dengan air di wilayah pendudukan.
- Perintah Militer No. 58 (19 Agustus 1967)
Melarang keras pembangunan fasilitas air baru tanpa izin resmi. Perwira air Israel memiliki hak menolak permohonan izin tanpa perlu memberikan alasan apa pun.
- Perintah Militer No. 158 (1 Oktober 1967)
Menempatkan semua sumur, mata air, dan proyek-proyek air di bawah kekuasaan langsung gubernur militer Israel.
- Perintah Militer No. 291 (akhir 1967)
Menegaskan bahwa seluruh sumber air di wilayah Palestina menjadi milik negara, sesuai dengan undang-undang air Israel tahun 1959.
- Perintah Militer No. 948 (14 November 1974)
Mewajibkan setiap warga Gaza memperoleh izin dari gubernur militer Israel sebelum menjalankan proyek yang berkaitan dengan air.
- Perintah Militer No. 498 (14 November 1974)
Terdiri atas 43 pasal. Pasal 16 (a) menetapkan bahwa otoritas berwenang dapat mengeluarkan instruksi mengenai sumber atau wilayah tertentu yang melarang pengambilan, pemompaan, atau penggunaan air tanpa izin resmi.
Pasal 20 memberi wewenang kepada otoritas tersebut untuk setiap saat membatalkan atau mengurangi volume air yang tertera dalam izin pengambilan air.
Dengan serangkaian regulasi ini, Israel tidak hanya memonopoli sumber daya air, tetapi juga mengendalikan seluruh aspek penggunaannya—mulai dari eksplorasi hingga distribusi—di wilayah pendudukan.
Air dalam meja perundingan Palestina–Israel
Dalam Perjanjian Oslo (1993), Israel untuk pertama kalinya mengakui adanya hak-hak air bagi rakyat Palestina.
Salah satu pasalnya menyebut bahwa Israel mengakui hak-hak air warga Palestina di Tepi Barat.
Namun, isu air tetap dikategorikan sebagai bagian dari “isu status akhir”, bersama dengan topik-topik seperti perbatasan, pengungsi, dan Yerusalem.
Dengan kata lain, persoalan ini ditunda penyelesaiannya dan tidak menjadi bagian dari kesepakatan Oslo yang ditandatangani pada 13 September 1993.
Dalam Perjanjian Gaza–Jericho (1994), air juga kembali disebut, tetapi hanya sebatas pelimpahan sebagian kewenangan teknis kepada Otoritas Palestina—tanpa menyentuh isu kedaulatan dan kepemilikan sumber air.
Tahun berikutnya, Perjanjian Oslo II (1995) memuat pasal 40 yang menjadi dasar pembentukan Komite Air Bersama Palestina–Israel (Joint Water Committee).
Komite ini ditetapkan mengambil keputusan secara mufakat, yang pada praktiknya membuat Israel memiliki hak veto terhadap setiap usulan Palestina.
Perjanjian tersebut juga menegaskan bahwa Palestina akan memperoleh tambahan pasokan air dan mengidentifikasi empat cekungan utama: tiga di Tepi Barat dan satu di Jalur Gaza.
Meskipun begitu, volume air tanah dari masing-masing cekungan ditetapkan secara sepihak dan sempat ditolak delegasi Palestina.
Cekungan-cekungan yang diatur dalam perjanjian itu mencakup:
- Cekungan timur Tepi Barat: 172 juta m³
- Cekungan timur laut Tepi Barat: 145 juta m³
- Cekungan barat Tepi Barat: 362 juta m³
- Cekungan Gaza: 55 juta m³
- Total keseluruhan: 734 juta m³ per tahun
Sedangkan pembagian konsumsi air ditetapkan sebagai berikut:
- Tepi Barat: 127,4 juta m³
- Jalur Gaza: 108 juta m³
- Total Palestina: 235,4 juta m³
- Permukiman Israel: 60 juta m³
- Total keseluruhan: 295,4 juta m³
Dari angka-angka tersebut terlihat ketimpangan besar: warga Palestina hanya memanfaatkan sekitar 127 juta m³ air di Tepi Barat, sementara 552 juta m³ sisanya dialirkan ke Israel.
Termasuk sekitar 50 juta m³ untuk kebutuhan permukiman ilegal di wilayah pendudukan.
Di Jalur Gaza, kapasitas air tanah hanya sekitar 55 juta m³, jauh di bawah kebutuhan riil penduduk wilayah yang padat dan terisolasi itu.
Strategi Palestina dalam perundingan Air
Shaddad Attili, mantan koordinator negosiasi air untuk status akhir di Otoritas Air Palestina, merangkum tiga prinsip utama yang menjadi pijakan Palestina dalam setiap perundingan dengan Israel:
- Kedaulatan penuh atas cekungan timur, karena seluruh wilayahnya berada dalam batas politik Tepi Barat dan tidak terhubung dengan sistem air lintas batas. Prinsip yang sama juga berlaku bagi cekungan pesisir Gaza.
- Distribusi adil dan wajar atas sumber air bersama, sesuai dengan prinsip hukum internasional, terutama bagi cekungan timur laut, cekungan barat, dan Sungai Yordan.
- Tanggung jawab Israel atas kerusakan sumber air Palestina sejak 1967, termasuk kewajiban kompensasi atas dampak eksploitasi dan pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas pendudukan.
Sumber air di Tepi Barat dan jalur Gaza
Warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza bergantung pada tiga sumber utama air, yaitu:
- Air Hujan
Curah hujan merupakan sumber utama air, terutama untuk pertanian. Di Tepi Barat, rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 100–600 milimeter, sementara di Jalur Gaza antara 200–900 milimeter.
- Air Tanah
Sekitar 76 persen kebutuhan air di kedua wilayah dipasok dari air tanah. Di Tepi Barat terdapat tiga cekungan utama—timur, barat, dan timur laut.
Sementara di Gaza, lapisan air tanah mencakup hampir seluruh wilayah, meski kedalaman dan kualitasnya bervariasi tajam.
- Pasokan dari Perusahaan Air Israel “Mekorot”
Berdasarkan Perjanjian Oslo 1995, Palestina diwajibkan membeli sekitar 22 persen dari total kebutuhan airnya dari Mekorot, perusahaan air milik pemerintah Israel.
Ketergantungan ini semakin memperdalam kontrol Israel atas kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina, dari ladang hingga dapur rumah tangga.
Perampasan hak air rakyat Palestina
Serangkaian perintah militer yang diterbitkan Israel telah memperkuat cengkeramannya atas sumber daya air Palestina, sekaligus mengebiri hak dasar rakyat Palestina atas air bersih. Akibatnya, kadar garam meningkat di sebagian besar sumur air tanah di wilayah Palestina, yang berimbas langsung pada penurunan hasil pertanian.
Menurut data resmi Palestina, Israel menguras sekitar 86,5 persen dari total sumber daya air permukaan dan air tanah Palestina, sementara warga Palestina hanya dapat memanfaatkan tidak lebih dari 13,5 persen.
Pada Desember 2012, sebuah studi yang dirilis Pusat Al-Tajammu’ untuk Hak-hak Palestina mengungkap bahwa otoritas pendudukan setiap tahun menyita lebih dari 10 juta meter kubik air tawar dari sumber terbaik di Gaza, sehingga mengancam cadangan air wilayah itu.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa Israel mengebor sumur-sumur besar yang menurunkan permukaan air tanah dan mengalihkan alirannya dari Gaza ke wilayah Israel.
Dalam pernyataannya pada 27 November 2022, Perdana Menteri Palestina kala itu, Mohammad Shtayyeh, menegaskan bahwa Israel mencuri lebih dari dua pertiga air tanah Palestina dan menyalurkannya ke kota-kota serta permukiman Yahudi.
Ia menyebut, sekitar 600 juta meter kubik air dari total 800 juta meter kubik air tanah Palestina disedot oleh Israel, sementara sepertiga air di Tepi Barat digunakan di wilayah Israel.
Kebijakan dan praktik penjarahan air
Sejumlah langkah yang ditempuh Israel untuk membatasi akses rakyat Palestina terhadap air antara lain:
- Menetapkan batas maksimal volume air yang boleh dipompa dari sumur milik warga.
- Melarang pengeboran sumur baru untuk keperluan pertanian.
- Mewajibkan izin khusus bagi setiap kegiatan pengeboran baru.
- Menyita sumur-sumur milik petani untuk kepentingan permukiman Yahudi.
- Membatasi kedalaman pengeboran hingga tidak lebih dari 120 meter.
- Menghalangi hak rakyat Palestina atas air Sungai Yordan dan mengubah aliran sungai tersebut.
- Mencuri volume besar air Palestina melalui sumur yang digali di wilayah permukiman.
- Membangun banyak bendungan kecil guna menahan aliran air permukaan agar tidak mengalir ke wilayah Palestina.
- Menyalurkan air berkualitas tinggi ke kota-kota Israel.
- Menjual air kepada warga Palestina dengan harga tinggi.
- Memberlakukan pembatasan ketat terhadap pemerintah lokal Palestina sehingga mereka tidak bisa mengembangkan infrastruktur air.
- Menolak menyalurkan jatah air sebagaimana diatur dalam perjanjian bilateral dengan Palestina.
- Mencemari air tanah Palestina melalui pembuangan limbah cair ke sumur dan sumber air.
Sebaliknya, pemerintah Israel justru memberi izin luas kepada para pemukim Yahudi untuk membangun infrastruktur air yang modern dan menggali sumur-sumur baru.
Langkah ini bertujuan memperkecil volume air tanah yang dapat dimanfaatkan warga Palestina.
Krisis air yang menggigit
Data dari Badan Pusat Statistik Palestina menunjukkan kesenjangan yang mencolok: rata-rata warga Israel mengonsumsi sekitar 300 liter air per hari, sementara warga Palestina hanya 85 liter, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 120 liter per hari.
Banyak wilayah di Tepi Barat dan Jalur Gaza mengalami pemadaman air secara rutin, terutama akibat kebijakan dan kontrol politik Israel.
Tercatat 264 permukiman di Tepi Barat dan 8 di Gaza bahkan tidak memiliki jaringan air publik sama sekali.
Warga di wilayah-wilayah ini terpaksa membeli air dari tangki keliling dengan harga tinggi atau menampung air hujan dalam sumur-sumur buatan, yang sering kali tidak memenuhi standar kebersihan.
Pada Februari 2011, sejumlah lembaga hak asasi manusia Palestina mendesak PBB menyelidiki pencurian air oleh Israel serta dampak ekologis serius yang ditimbulkannya terhadap lingkungan di Palestina.
Penghancuran infrastruktur air
Dalam setiap operasi militer di Tepi Barat maupun perang di Jalur Gaza, Israel secara sistematis menargetkan infrastruktur air: menghancurkan sumur, mengebom tangki penampungan, merusak jaringan irigasi dan pipa distribusi.
Pola ini tampak jelas dalam perang genosida yang dimulai pada 7 Oktober 2023.
Sejak hari pertama agresi ke Gaza, otoritas pendudukan memutus suplai air bagi seluruh penduduk, lalu menghancurkan sumber dan jaringan distribusinya melalui serangan udara dan operasi darat.
Bagian dari strategi yang bertujuan melumpuhkan kehidupan sipil dan memaksa warga meninggalkan wilayahnya.
Lembaga-lembaga Palestina memperingatkan tercemarnya sumber air akibat serangan Israel dan bocornya bahan kimia beracun, yang memperparah krisis kemanusiaan dan kelaparan di wilayah itu.
Pada 21 Mei 2025, Monzer Salem, Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Gaza, mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa Israel telah menghancurkan 85 persen sumber air di Gaza, membuat air minum layak konsumsi tak lagi tersedia bagi lebih dari dua juta penduduk.
Beberapa bulan kemudian, pada 4 Agustus 2025, PBB melaporkan bahwa hampir seluruh penduduk Gaza kehilangan akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi.
Menurut badan dunia itu, 96 persen rumah tangga di Gaza menghadapi ketidakamanan air, sementara 90 persen penduduk tidak lagi mampu memperoleh air minum.