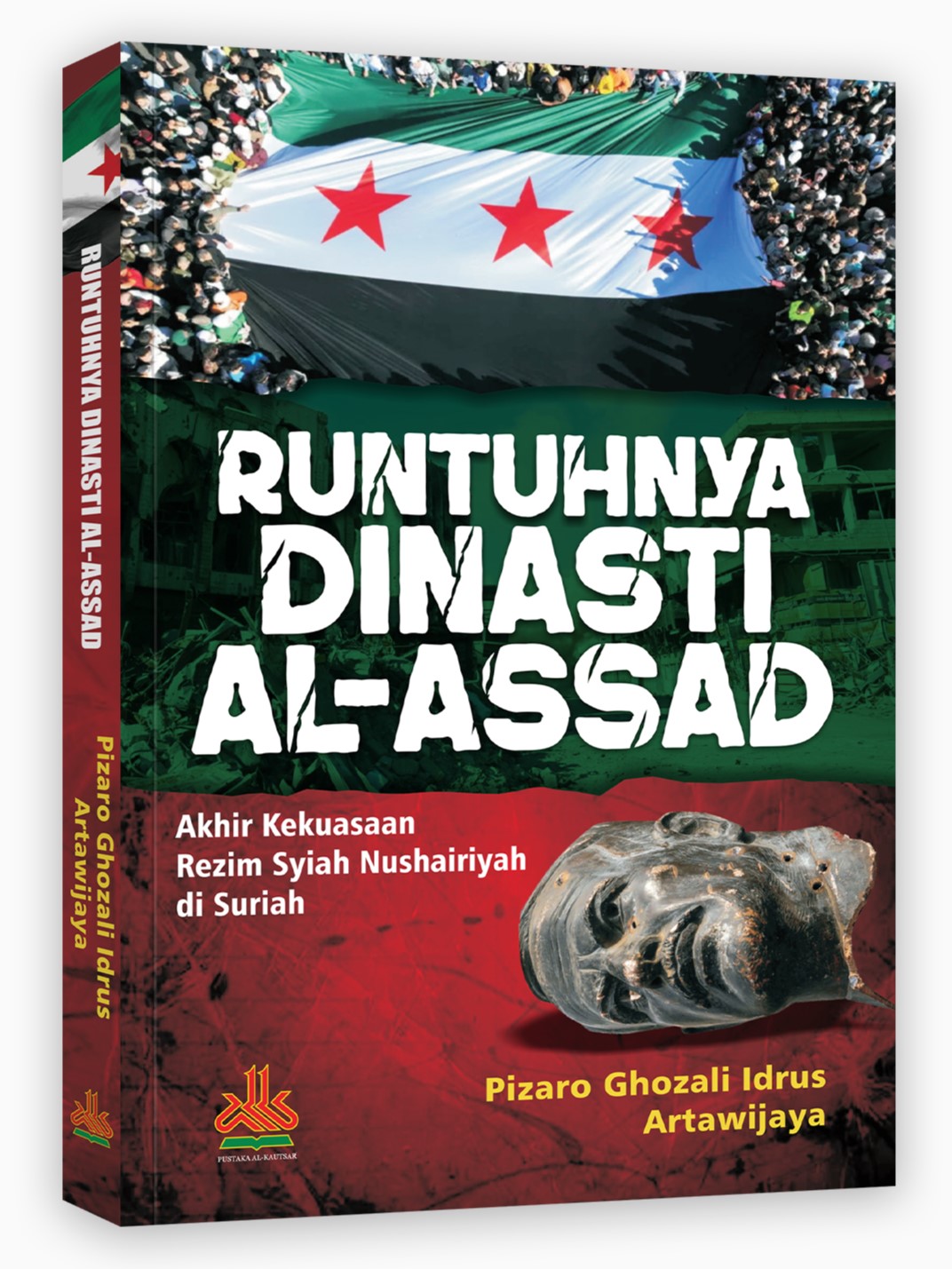Keputusan mengejutkan datang dari Song-Chun Zhu, salah satu ilmuwan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) paling disegani di Amerika Serikat (AS).
Setelah lebih dari separuh hidupnya dijalani di negeri itu—dengan catatan akademik dan karier yang gemilang—Zhu memilih kembali ke tanah kelahirannya, Tiongkok.
Langkah ini memunculkan tanda tanya besar, terutama di lingkungan kampus University of California, Los Angeles (UCLA), tempat Zhu menjabat sebagai profesor ilmu komputer.
Rekan-rekannya mengaku kebingungan. Namun, kepada semua pertanyaan, Zhu hanya menjawab singkat.
“Saya harus melakukannya,” jawabnya.
Di Tiongkok, pintu-pintu prestisius langsung terbuka. Zhu dipercaya menduduki posisi penting di dua universitas papan atas, Universitas Peking dan Universitas Tsinghua, yang kini menjadi pusat pengembangan AI di negeri itu.
Lebih jauh lagi, ia memimpin Beijing Institute for General Artificial Intelligence, sekaligus menjadi salah satu penasihat utama Pemerintah Tiongkok dalam merumuskan kebijakan terkait teknologi AI.
Pertanyaan pun muncul: mengapa ilmuwan pemenang Marr Prize—salah satu penghargaan bergengsi di bidang ilmu komputer—memutuskan meninggalkan AS setelah lebih dari dua dekade, justru untuk kembali ke negara yang dahulu ia tinggalkan?
“Pelarian” menuju menara ilmu
Dalam wawancara dengan The Guardian, Song-Chun Zhu menggambarkan Amerika Serikat—dan universitas-universitasnya—sebagai sebuah menara ilmu, tempat aman bagi para cendekia.
Dari sudut pandangnya, negeri itu adalah ruang di mana seorang anak dari pelosok Tiongkok bisa bermimpi besar, lalu benar-benar menapaki jalan menuju panggung ilmu pengetahuan dunia.
Zhu meninggalkan Tiongkok pada 1992. Cita-citanya sederhana, tetapi penuh ambisi: menekuni ilmu komputer di Harvard University.
Sebelum itu, ia sudah menorehkan prestasi akademik gemilang di sejumlah universitas di Tiongkok. Namun, satu hal menghalanginya—biaya.
Ketika itu, Zhu bahkan tidak mampu membayar ongkos pendaftaran untuk universitas-universitas besar di AS.
Ia hanya mencoba peruntungannya ke beberapa universitas kecil. Hasilnya, nihil. Tak ada satu pun yang melirik berkasnya.
Nasibnya berubah berkat nasihat seorang profesor di kampus asalnya. Sang profesor mendorong Zhu untuk tetap mengirimkan aplikasi ke Harvard.
“Itu universitas tua yang disokong tradisi besar. Mereka tidak peduli soal biaya pendaftaran,” begitu ia meyakinkan.
Dari ribuan aplikasi yang masuk, keberuntungan berpihak pada Zhu. Permohonannya diperhatikan David Mumford, matematikawan tersohor sekaligus penerima Medali Fields—penghargaan paling bergengsi dalam disiplin matematika.
Dalam wawancara terpisah dengan The Guardian, Mumford mengenang momen itu.
“Saya terkejut. Ada seorang mahasiswa dari pedalaman Tiongkok yang sudah berani mengusulkan semacam Theory of Everything untuk kecerdasan buatan, dan menjadikan Marr sebagai sumber inspirasinya. Cara pandangnya benar-benar mengesankan,” katanya.
Mumford pun langsung menghubungi Zhu, membuka jalan baginya untuk mendapatkan beasiswa penuh di Harvard—kampus yang selama ini hanya hidup dalam imajinasinya tentang ilmu pengetahuan di Amerika.
Sejak saat itu, Mumford juga menjadi salah satu pembimbing akademiknya yang paling berpengaruh.
Tersentak oleh “kejutan peradaban”
Tahun 1997, Song-Chun Zhu meninggalkan Harvard. Ia pindah ke Stanford University sebagai dosen muda. Namun, di sanalah ia mengalami apa yang disebutnya sebagai “kejutan peradaban” pertama.
Di kelas yang ia ampu, Zhu menawarkan kuliah-kuliah teoretis tentang dasar-dasar ilmu komputer dan kecerdasan buatan.
Akan tetapi, para mahasiswa justru berbondong-bondong memilih mata kuliah yang lebih praktis: membangun situs web dan mengembangkan aplikasi.
Fenomena itu bukan tanpa sebab. Saat itu, gelombang besar “revolusi dot-com” mulai mengubah lanskap Silicon Valley.
Perusahaan rintisan seperti Yahoo! baru saja melantai di bursa dan mencatat kesuksesan besar, sementara 2 mahasiswa Stanford, Larry Page dan Sergey Brin, tengah merintis mesin pencari yang kelak dikenal dunia dengan nama Google.
Dalam wawancara dengan The Guardian, Zhu mengingat betapa kontrasnya suasana yang ia temui di Stanford dibandingkan dengan Harvard.
“Di Harvard, hidup berkutat pada ilmu dan pemahaman. Lambang mereka menampilkan tiga buku yang berjajar rapi. Tetapi di Stanford, lambangnya seakan berubah menjadi simbol dolar,” ujarnya dengan nada getir.
Stanford tak menjadi rumah yang ia cari. Hanya setahun bertahan, Zhu kemudian pindah ke Ohio State University.
Dari sana, perjalanan akademiknya membawanya ke University of California, Los Angeles (UCLA), yang kelak menjadi pangkalan terakhirnya di AS—sebelum ia mengambil keputusan besar untuk pulang ke Tiongkok.
Pandangan yang menyimpang dari “para bapak AI”
Dalam dunia kecerdasan buatan, sejumlah nama kerap dijuluki “bapak pendiri” atau godfathers of AI: Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio, dan Yann LeCun.
Namun, hubungan Song-Chun Zhu dengan mereka tak pernah berjalan mulus. Perbedaan itu bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan bertolak dari pandangan filosofis dan pendekatan ilmiah yang sangat berbeda mengenai arah masa depan AI, terutama artificial general intelligence (AGI) atau kecerdasan buatan umum.
LeCun dan kubunya percaya bahwa kunci keberhasilan AI terletak pada “3 serangkai”: data dalam jumlah masif, daya komputasi superbesar, serta algoritme yang mampu mengolah keduanya.
Pola pikir ini sejalan dengan arah riset perusahaan raksasa seperti Meta dan OpenAI.
Sebaliknya, Zhu memilih jalur berbeda. Menurutnya, kecerdasan buatan sejati justru harus mampu melakukan tugas-tugas kompleks dengan menggunakan data sekecil mungkin.
Efisiensi, bukan kelimpahan, adalah tanda kecerdasan. Pandangan ini kemudian terbukti relevan di Tiongkok, antara lain melalui perusahaan DeepSeek.
Perusahaan itu meluncurkan sistem AI dengan performa sekelas produk Amerika Serikat, tetapi dilatih dengan data dan sumber daya yang jauh lebih hemat. Jejak pemikiran Zhu jelas tercermin di sana.
Ketegangan akademik antara Zhu dan LeCun mencapai puncaknya pada 2012, saat Zhu menjadi ketua panitia konferensi bergengsi CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition).
LeCun kala itu mengajukan sebuah makalah. Namun, Zhu menolak dengan alasan teori yang mendasarinya belum cukup jelas.
Keputusan itu membuat LeCun berang dan membela karyanya habis-habisan.
Peristiwa itu bukan sekadar perselisihan teknis, tetapi juga menggambarkan jurang perbedaan dalam memandang masa depan AI—antara mereka yang percaya pada kekuatan data raksasa dan mereka yang mengandalkan visi efisiensi ala Zhu.
Mengapa Zhu pulang ke Tiongkok?
Bagi Mark Nitzberg—sahabat lama Song-Chun Zhu selama dua dekade sekaligus rekan kuliahnya di Harvard—kepulangan Zhu ke Tiongkok terasa mengejutkan.
“Itu keputusan yang tak disangka siapa pun,” ujarnya.
Namun, Nitzberg menambahkan, sahabatnya itu melihat di Tiongkok kesempatan untuk mengejar mimpi yang sudah lama ia pendam: mewujudkan kecerdasan buatan umum (artificial general intelligence/AGI) sesuai dengan visinya sendiri.
Alasannya sederhana tetapi signifikan. Pemerintah Tiongkok, menurut Zhu, menyediakan sumber daya dan dukungan riset yang tidak pernah ia temukan di AS.
Dukungan inilah yang diyakininya dapat membuka jalan menuju pencapaian AGI.
Namun, laporan The Guardian menilai keputusan itu tidak hanya lahir dari soal fasilitas. Ada pula dimensi lain yang tak kalah penting.
Zhu kerap berbeda pandangan filosofis dengan para pemimpin arus utama AI, terutama mengenai mekanisme deep learning yang kini menjadi arus besar di dunia.
Selain itu, faktor geopolitik turut berperan. Pada masa pemerintahan Donald Trump, berbagai kebijakan mulai membatasi ruang gerak peneliti asal Tiongkok di Amerika.
Pembatasan itu membuat banyak ilmuwan merasa tertekan. Zhu, yang terbiasa dengan kebebasan berpikir, mengaku kian enggan melanjutkan kiprah akademiknya di sana.
Tidak diragukan lagi, kepulangan Zhu merupakan keuntungan besar bagi Beijing. Kehadirannya bukan sekadar menambah daftar panjang ilmuwan top yang kembali, tetapi juga memperkuat posisi Tiongkok dalam perlombaan global menuju AGI.
Kini, persaingan tersebut tidak lagi sekadar soal teknologi. Ia juga berubah menjadi pertarungan gagasan.
Antara model AS yang mengandalkan data raksasa dan kekuatan komputasi masif, dengan pendekatan Zhu yang menekankan efisiensi—menghasilkan kecerdasan tinggi dengan data sesedikit mungkin.