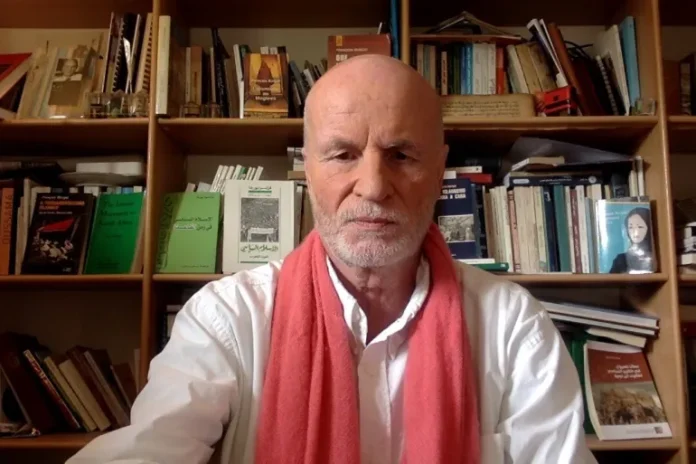Pada April 2025, Francois Burgat—seorang filsuf sekaligus ilmuwan politik dan sosiologi berusia 77 tahun—mendapati dirinya berada di jantung drama hukum di Prancis Selatan.
Pakar studi Islam dan mantan direktur riset di Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), lembaga penelitian pemerintah terbesar di Prancis sekaligus agen riset ilmu dasar terbesar di Eropa, diadili atas tuduhan “pembenaran terhadap terorisme.”
Tuduhan itu bermula dari sebuah unggahan di media sosial pada Januari tahun lalu, di mana ia menyuarakan dukungan terhadap narasi perlawanan Palestina atas pendudukan Israel.
Bagi mereka yang mengenal pemikiran Burgat, proses peradilan ini merupakan puncak dari rangkaian panjang intimidasi yang telah ia alami selama bertahun-tahun.
Petisi solidaritas yang beredar saat itu menyatakan bahwa tuduhan “mengagungkan Hamas” semata-mata berangkat dari cuitan yang merefleksikan analisis yang sebelumnya telah ia tuangkan dalam karya-karya akademiknya.
Sidang tersebut pun dinilai sebagai simbol benturan antara kebebasan akademik dan kampanye keras Pemerintah Prancis terhadap suara-suara pro-Palestina pasca-operasi pembantaian Israel yang terjadi setelah serangan 7 Oktober.
Prancis, negeri yang kerap membanggakan diri sebagai tanah “kebebasan dan pencerahan,” kini telah banyak berubah.
Dalam kondisi normal, Burgat dan para pemikir lain mestinya tampil dalam forum ilmiah untuk menyampaikan gagasannya.
Namun, kali ini, sang intelektual justru dipanggil oleh satuan kepolisian di Aix-en-Provence untuk memberikan penjelasan ihwal pandangan yang dianggap sebagai “pembenaran dan pengagungan terorisme.” Tuduhan ini diajukan oleh sebuah organisasi Yahudi Eropa.
Tuduhan bermula dari tindakan Burgat yang pada 2 Januari 2024 mengunggah ulang pernyataan resmi Hamas.
Dalam pernyataan itu, Hamas membantah tudingan yang dimuat The New York Times mengenai dugaan pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya.
Hamas menyebut tudingan tersebut sebagai bagian dari upaya “iblis Zionis” untuk mencemarkan citra perlawanan Palestina.
Hamas juga mendesak media Amerika itu agar meminta maaf atas kekeliruan profesional tersebut.
Burgat tidak berhenti pada sebatas membagikan ulang pernyataan itu. Ia menambahkan kalimat yang segera memantik kontroversi di ranah publik Prancis.
“Saya memiliki rasa hormat dan penghargaan tak terbatas—saya ulangi, tak terbatas—terhadap para pemimpin Hamas, lebih daripada terhadap para pemimpin Negara Israel,” katanya.
Dalam wawancara dengan harian Libération, Burgat menegaskan bahwa ia tidak mencabut pernyataannya.
Ia mengakui bahwa pendapatnya mungkin terdengar mengejutkan bagi sebagian kalangan, namun ia menolak untuk mengubah sikapnya.
“Mengakui bahwa peristiwa 7 Oktober merupakan tindakan yang memiliki unsur terorisme, tidak berarti saya harus mengkriminalisasi gerakan pembebasan Palestina,” ujarnya.
Di ruang sidang, Burgat membela diri dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah memberi ucapan selamat kepada Hamas atas serangan 7 Oktober.
Ia hanya menyampaikan keraguannya terhadap narasi Israel yang secara luas diterima oleh publik internasional.
Pernyataan-pernyataan Burgat sejalan dengan gagasan dan filsafat yang selama ini ia usung. Ia kerap membela kekerasan yang berasal dari dunia Islam, bukan sebagai ekspresi dari ajaran agama, melainkan sebagai reaksi terhadap sejarah kolonialisme brutal yang menimpa dunia Arab dan Islam.
Baginya, konflik seperti pembentukan negara Israel merupakan bagian dari warisan sejarah kekerasan tersebut.
Perjalanan panjang Burgat menuju titik ini telah berlangsung lintas dekade dan benua. Ia lahir pada 1948 di Chambéry, Prancis Timur, dekat perbatasan Swiss dan Italia.
Lebih dari seperempat hidupnya dihabiskan di dunia Arab. Setelah menyelesaikan studi hukum, ia pindah ke Aljazair pada tahun 1970-an untuk mengajar hukum di negara yang baru merdeka itu (1973–1980), dan menyelesaikan disertasi doktoralnya tentang reformasi agraria sosialis di sana.
Selanjutnya, ia mengajar di Institut Ilmu Politik di Aix, serta menjalani masa riset di Kairo (1989–1993) dan Sana’a (1997–2003).
Ia kemudian mengepalai Institut Prancis untuk Dunia Timur (IFPO) di Damaskus dan kemudian Beirut, serta membuka cabang lembaga itu di Erbil, Irak dan Yerusalem Timur, Palestina.
Namun, kisah Burgat dengan dunia Arab tidak bermula pada 1973 saat ia mengajar di Universitas Constantine, Aljazair.
Hubungan itu telah dimulai jauh sebelumnya—saat ia berusia 16 tahun. Kala itu, ia mengikuti bibinya dalam sebuah perjalanan religius bersama sekelompok peziarah Kristen Prancis ke Yerusalem.
Di sana, ia berjumpa dengan seorang anak Palestina di kota Jericho yang mengatakan kepadanya bahwa tanahnya telah dirampas oleh orang Yahudi.
Bagi remaja Prancis itu, informasi tersebut sangat mengejutkan. Ia tidak tahu bahwa ada bangsa Palestina yang telah kehilangan tanahnya.
Ingatan itulah yang terus hidup dalam benak Burgat dan menjadi referensi berulang dalam analisisnya terhadap dunia Arab dan Islam, termasuk dalam memahami dinamika gerakan-gerakan Islam.
“Islamisasi” yang pincang
Di Prancis, ada seorang imam yang kerap muncul di berbagai program diskusi televisi dan menjadi bahan olok-olok publik.
Namun kata “lucu” di sini bukan ditujukan sebagai celaan pribadi, melainkan deskripsi faktual atas penampilannya yang kontroversial.
Ia adalah Hassan Chalghoumi, sosok yang disebut sebagai salah satu “imam selebriti” oleh media dan institusi resmi di Prancis.
Chalghoumi tidak fasih berbahasa Prancis, dan bahasa Arabnya pun tidak meyakinkan. Ia kesulitan berbicara secara runtut dan logis.
Meski demikian, ia tetap diorbitkan sebagai imam paling populer, seolah menjadi juru bicara umat Islam di Prancis.
Ia berpandangan sangat sekuler, bersahabat akrab dengan Israel, dan telah berkunjung ke sana berkali-kali, bahkan dalam saat-saat ketika negara itu menggempur Gaza tanpa ampun.
Francois Burgat menolak sepenuhnya fenomena yang ia sebut sebagai “chalghoumisasi” umat Islam—yakni berbicara atas nama mereka dalam isu-isu penting.
Konsep ini menurutnya bertentangan dengan kebijakan negara Prancis yang terus berupaya mengendalikan Islam dan memaksakan tafsir sekuler terhadap agama yang memiliki relasi spiritual dan politik berbeda dari sejarah sekularisme Prancis yang dahulu “mengasingkan” gereja dari ruang publik pasca-Revolusi.
Menjadikan sosok seperti Chalghoumi sebagai “model Muslim ideal” berarti menyodorkan gambaran bahwa Muslim sejati adalah mereka yang mengagungkan negara Prancis sama seperti mereka mengagungkan Tuhan.
Mencintai Israel, menolak semua ekspresi Islam yang dianggap ekstrem oleh pemerintah (meski merupakan inti ajaran), dan menjalani kehidupan keagamaan tanpa kesalehan yang mencolok dalam penampilan maupun praktik sehari-hari.
Burgat menunjukkan ketertarikan mendalam dalam memahami fenomena keislaman, baik di Prancis maupun dunia Islam.
Ia melihat bahwa masyarakat Muslim memiliki cara berpikir dan pendekatan atas pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan yang berbeda dari tradisi filsafat Barat.
Dalam kerangka itu, ia membedakan dua proses penting: pertama, menjelaskan mengapa wacana Islam kembali menguat di dunia Arab, dan kedua, menunjukkan betapa beragamnya bentuk-bentuk aksi yang dapat dihasilkan dari wacana tersebut.
Dalam analisanya, Burgat menyajikan ragam contoh yang menegaskan bahwa wacana Islam tidak monolitik.
Ada Islam politik yang demokratis seperti yang diwakili oleh Partai Ennahda di Tunisia, dan ada pula Islam jihadistik yang bahkan ditolak oleh sebagian besar kelompok Islamis sendiri—seperti yang diusung kelompok ekstrem Negara Islam di bawah Abu Bakar al-Baghdadi.
Poin penting yang diangkat Burgat adalah bahwa kekuatan mobilisasi dari wacana Islam kontemporer tidak hanya berasal dari klaim sakralitasnya, tetapi juga dari akar lokalnya.
Ia menyatakan bahwa kebangkitan Islam politik merupakan cara untuk menghidupkan kembali budaya yang telah dirampas secara paksa melalui penjajahan.
Dunia Arab dan Islam, setelah bertahun-tahun mengalami perampasan simbol dan kerangka berpikir, mulai menyadari keterasingannya dari sejarah dan identitas mereka sendiri.
Burgat berseberangan dengan arus utama pemikiran di Barat yang menyederhanakan radikalisme keagamaan sebagai masalah doktrin semata.
Baginya, ekstremisme politik adalah biang utama dari ekstremisme keagamaan. Kekerasan yang dikaitkan dengan Islam, menurutnya, bukan berasal dari Islam itu sendiri, melainkan dari penindasan yang dialami umat Muslim.
Karena itu, berbagai seruan untuk “mereformasi Islam” dinilainya keliru dan tidak efektif.
“Jika kita percaya bahwa jalan menuju stabilitas adalah melalui reformasi pemikiran keagamaan ekstrem, kita justru salah arah. Kita tidak akan menenangkan kawasan dengan memperbaiki wacana keagamaan—kita harus menenangkan kawasan terlebih dahulu, baru kemudian wacana keagamaannya dapat berubah,” tegasnya.
Lebih jauh, akademisi Prancis ini menegaskan bahwa apa yang disebut “Islamisme” dalam tafsir Barat bukanlah penyimpangan, melainkan fase ketiga dalam perjuangan dekolonisasi.
Ia menyebutnya sebagai bentuk renegosiasi antara “Selatan yang tertindas” dan “Utara yang menindas.”
Dalam argumen yang jarang diungkapkan oleh para akademisi Barat, Burgat menekankan bahwa Barat harus mengakui keterlibatannya dalam kekerasan yang dilakukan atas nama Islam.
Bersama dengan elit Muslim yang telah mengadopsi kerangka berpikir Barat dan turut andil dalam membentuk kondisi yang melahirkan terorisme.
Selama satu dekade terakhir, Eropa—khususnya Prancis—mengalami serangkaian serangan berdarah.
Mayoritas elit politik dan intelektual di kawasan itu merespons dengan permusuhan tajam terhadap Islam politik, bahkan terhadap Islam dalam bentuknya yang paling netral.
Diskursus publik pun dipenuhi dengan wacana tentang perlunya “mengakhiri Islam” sebagaimana adanya, menghapus komponen-komponen identitas dan keyakinannya, serta menjadikannya agama tanpa substansi.
Dalam sebuah artikel di Orient XXI, Burgat menyoroti bagaimana analisis keliru telah mendominasi wacana pasca-serangan terorisme.
Ia menilai bahwa banyak analis mengabaikan peran “reaksi” dan identitas politik dalam memahami Islam politik.
Ia mengkritik tajam pemikiran Olivier Roy yang berpendapat bahwa Arab Spring akan menghapus jejak-jejak Islamisme, dan generasi pasca-Islam tidak berperan dalam revolusi.
“Hasil pemilu di Mesir dan Tunisia meruntuhkan asumsi sembrono itu. Tapi di mana titik lemah analisis saat ini? Olivier Roy gagal melihat bahwa generasi Al-Qaeda, dengan seluruh keragaman asal-usul jihadinya, bukan sekadar gelombang warga Prancis yang marah, melainkan ekspresi dari kemarahan umat Muslim terhadap agresi Barat,” katanya.
Dengan gagasan ini, Burgat menawarkan pandangan yang kompleks, yang tidak hanya mengecam kekerasan atas nama agama, tetapi juga menuntut penghentian dominasi dan represi terhadap budaya serta peradaban lain.
Ia mengaitkan serangan-serangan di Prancis dengan dinamika global. Misalnya, ia menganggap tidak masuk akal untuk memisahkan tindakan bersaudara Kouachi (pelaku serangan Charlie Hebdo) dari motivasi politik yang terstruktur.
Hal yang sama berlaku bagi Amedy Coulibaly (pelaku serangan terhadap toko Yahudi), yang tindakannya tak bisa sekadar dilihat sebagai tindakan individu marah tanpa kepedulian terhadap tragedi yang menimpa dunia Arab dan Islam, terutama di Palestina.
Israel yang disakralkan secara resmi
Waktu dan ruang tentu tidak cukup untuk menyebutkan satu per satu tokoh penting —baik dari kalangan seni, sastra, maupun olahraga— yang mengalami serangkaian pelanggaran hak dan tekanan hanya karena mereka mengkritik Israel.
Seiring dengan keputusan Mahkamah Pidana Internasional yang menetapkan Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya sebagai bagian dari rezim kriminal perang, sejumlah analis politik Prancis pun bergegas membela Netanyahu.
Kalaupun mereka mengakuinya sebagai pelaku kejahatan perang, tetap saja ia dipandang “lebih sah” karena memimpin pemerintahan hasil pemilu demokratis — berbeda dengan pimpinan Hamas.
Israel tampaknya telah menjelma menjadi salah satu “hal yang sakral” dalam diskursus resmi Barat, dan hal ini sangat terasa di Prancis.
Kritik terhadap Israel dapat dianggap sebagai tindakan kriminal serius, yang mengundang kecaman tidak hanya dari pengadilan, tetapi juga dari politisi dan media.
Dalam konteks ini, tuduhan anti-Semitisme di Prancis telah mengalami pergeseran makna: dari instrumen untuk mengecam kebencian terhadap Yahudi, menjadi alat untuk membungkam cendekiawan dan akademisi yang mengkritik kebijakan kolonial Israel di Palestina atau strategi geopolitik Barat di dunia Islam.
François Burgat mencatat bahwa “perlawanan terhadap anti-Semitisme” yang semestinya tetap menjadi instrumen penting, justru kerap dimanfaatkan demi kepentingan kelompok tertentu.
Ia mencontohkan peristiwa pembunuhan tragis terhadap Mireille Knoll, seorang perempuan Yahudi lansia yang dibunuh pada 23 Maret 2018 oleh pelaku berdarah keturunan Arab.
Tragedi ini memicu gelombang kegaduhan media dan politis. Robert Badinter, mantan menteri kehakiman, bahkan menyamakannya dengan “Holocaust di sebuah apartemen.”
Namun hasil penyelidikan polisi kemudian menyatakan bahwa motif pembunuhan tidak berkaitan dengan kebencian rasial, melainkan termasuk dalam kategori kriminal umum.
Burgat menanggapi kasus itu dengan sinisme. Ia mengkritik politisi yang tergesa-gesa membangun narasi sektarian, serta media seperti Le Monde yang menyebarluaskan narasi tersebut tanpa verifikasi yang memadai.
Baginya, hal itu justru merupakan bentuk lain dari pelecehan terhadap korban. Tidak mengherankan bila Burgat berkali-kali dituduh sebagai anti-Semit.
Sebelum insiden Knoll, ia juga sudah pernah dituduh demikian pada 2014 karena menyarankan agar dewan perwakilan komunitas Yahudi di Prancis (CRIF) dipisahkan dari pengaruh negara dan agar media Prancis lebih independen dari tekanan politik Israel.
Pandangan-pandangannya itu membuatnya dicap sebagai simpatisan Ikhwanul Muslimin.
Pada 2020, ia menjadi sasaran serangan media arus kanan karena memberikan dukungan moral terhadap akademisi Swiss, Tariq Ramadan, yang dituduh melakukan kekerasan seksual — tuduhan yang hingga kini dibantah keras oleh Ramadan.
Media sayap kanan seperti Marianne bahkan menuding Burgat telah meragukan integritas hukum Prancis karena membela Ramadan, dan mempertegas citra Burgat sebagai pembela kelompok Islamis.
Pasca 7 Oktober 2023, Burgat kembali menempuh jalur berbeda dari arus utama. Ia memang menyebut serangan Hamas sebagai tindakan teror, tetapi ia juga tidak segan mengutuk agresi militer brutal Israel dan menuding Netanyahu sebagai penanggung jawab kejahatan perang.
Ia menulis bahwa ketika para sejarawan di masa depan berusaha memahami keruntuhan Israel sebagai negara, mereka niscaya akan melihat kembali peristiwa Oktober 2023 sebagai titik balik krusial dalam spiral kekerasan ekstrem yang dipelopori oleh Israel sendiri.
Lebih jauh, Burgat menuntut agar tanggung jawab moral tidak hanya dibebankan kepada pihak Palestina atau Hamas.
Melainkan juga kepada para pemimpin dunia Barat — dari Joe Biden hingga Emmanuel Macron — yang, menurutnya, gagal menunjukkan keberanian dan nalar untuk mencegah mitra mereka (Israel) terjerumus ke dalam ekstremisme yang justru menghancurkan impian Zionis itu sendiri.
“Prancis, Amerika Serikat, dan Eropa harus berhenti menggunakan slogan-slogan kemanusiaan sebagai topeng moral untuk membenarkan sikap bungkam terhadap genosida yang sedang berlangsung,” tulisnya di platform X.
Kini, François Burgat masih terus menulis, memberi kuliah, dan menyuarakan pandangan dengan gaya khasnya — mengenakan jaket abu-abu dan senyum tenang yang menyiratkan keyakinan.
Ia menginspirasi generasi baru pemikir dan aktivis yang tidak puas dengan penjelasan permukaan, serta ingin menggali realitas yang lebih dalam di balik peristiwa.
Namun sikap kritis dan keberaniannya dalam menyuarakan opini tak pelak menjadikan dirinya target kebencian kaum ekstrem kanan.
Burgat menilai bahwa fenomena terorisme adalah kegagalan Eropa sendiri. Karena gagasan-gagasan itulah, ia kini akrab dengan ruang-ruang interogasi dan aparat keamanan.
Prancis, yang dahulu dikenal sebagai negeri filsafat dan HAM, kini tampak berubah menjadi negara satu suara: suara yang cenderung condong ke kanan, memuja Israel, dan tidak segan memperlihatkan permusuhan terhadap Islam.
Dan bagi siapa pun yang berani menyuarakan suara lain, hanya ada satu pilihan: meninggalkan “tanah kebebasan” itu.