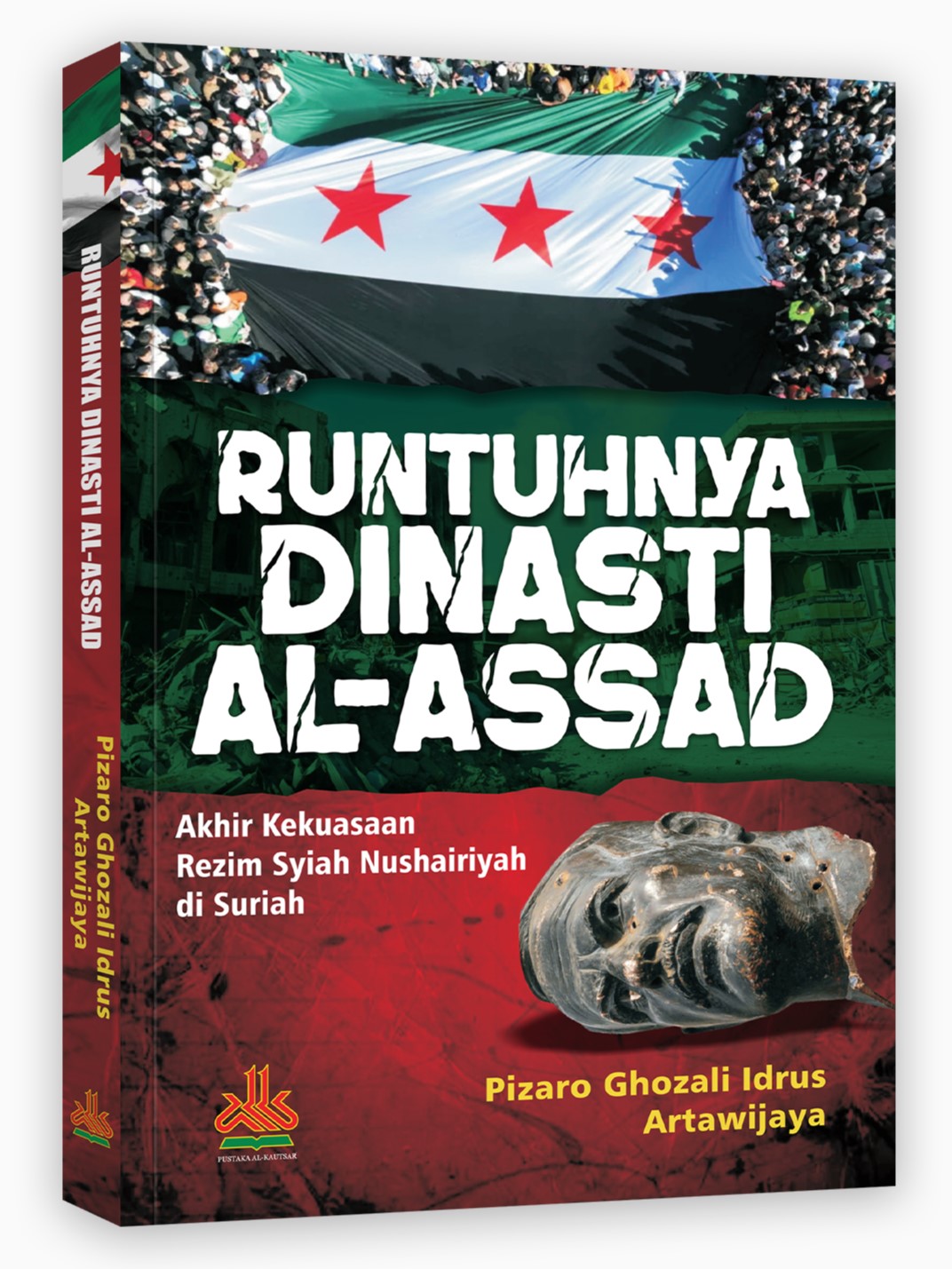Selama lebih dari setengah abad, hambatan terbesar bagi perdamaian di Timur Tengah bukanlah ketiadaan tawaran berani dari pihak Palestina, melainkan tekad Israel yang konsisten untuk menguburnya sebelum sempat tumbuh.
Berkali-kali pihak Palestina telah meletakkan kompromi besar di meja perundingan.
Mulai dari pengakuan bersejarah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1988 terhadap eksistensi Israel dan penolakan jalan perjuangan bersenjata, hingga tawaran para pemimpin Hamas untuk gencatan senjata jangka panjang.
Namun, berkali-kali pula, Israel merespons bukan dengan tangan terbuka, melainkan dengan kepalan, sabotase politik, bahkan pembunuhan.
Pola ini begitu konsisten, begitu disengaja, sehingga ungkapan “Israel tak pernah melewatkan kesempatan untuk melewatkan kesempatan” bukan lagi sekadar tragedi, melainkan doktrin yang dijalankan dengan penuh perhitungan.
Pada 1988, PLO memberikan tawaran paling murah hati dalam sejarah perjuangan Palestina.
Mereka menerima berdirinya negara Israel, merelakan 78 persen wilayah historis Palestina untuk “Negara Yahudi,” mengutuk “terorisme dalam segala bentuknya,” dan hanya meminta balasan berupa negara Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.
Seharusnya inilah skenario yang paling diimpikan Israel: mengakhiri konflik, meredakan Intifada Pertama, mengurangi isolasi internasional, serta menjamin masa depan mereka di kawasan. Tetapi justru sebaliknya, Tel Aviv panik.
Perdana Menteri Yitzhak Shamir segera menolak mentah-mentah tawaran PLO itu, menyebutnya “gila dan berbahaya” seraya bersumpah Israel “tidak akan pernah mengizinkan terbentuknya negara Palestina merdeka di wilayah pendudukan.”
Menteri Pertahanannya kala itu, Yitzhak Rabin, berjanji menggunakan “tangan besi” untuk menghancurkan peluang perdamaian ini.
Kementerian Luar Negeri Israel bahkan segera mengaktifkan tim khusus untuk merusak citra tawaran PLO.
Seorang jurnalis Israel, David Grossman, yang memberanikan diri melaporkan keputusan PLO, langsung dipecat dari radio tempatnya bekerja, dan diserang habis-habisan di Knesset maupun media nasional.
Pemerintah Israel bersama kelompok pro-Israel di Amerika Serikat (AS) juga mengecam kalangan Yahudi Amerika yang berusaha membangun komunikasi dengan Yasser Arafat.
Bahkan Washington menolak memberikan visa kepada Arafat untuk menyampaikan langsung tawarannya di Sidang Umum PBB.
Kini, sejarah kembali berulang. Di tengah citra Israel yang hancur akibat genosida di Gaza, sejumlah negara Eropa mencoba menawarkan jalan keluar diplomatik.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, dalam pidatonya di Singapura Mei lalu, menyebut pengakuan terhadap Palestina sebagai “tugas moral dan kebutuhan politik.”
Namun, pernyataan itu kehilangan bobot karena disertai syarat: Hamas harus meletakkan senjata, meninggalkan Gaza, dan tak lagi berperan dalam pemerintahan Palestina.
Pemerintah Israel kembali panik. Macron dituduh sedang “memimpin perang salib melawan negara Yahudi.”
Sikap serupa juga ditunjukkan terhadap setiap negara yang berencana mengakui Palestina.
Mereka dituding “memberi hadiah” bagi Hamas, mengacaukan negosiasi gencatan senjata, dan mendorong Israel ke arah “bunuh diri nasional.”
Kemarahan Israel ini sesungguhnya membuka tabir. Mereka paham betul, pengakuan Palestina oleh sejumlah negara Eropa tak lebih dari upaya menghidupkan kembali ilusi “proses perdamaian” yang sudah lama mati, sekaligus menghindari kewajiban moral untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan perang.
Pengakuan itu, dalam kenyataan, tidak akan membawa dampak nyata terhadap kemerdekaan Palestina, apalagi membendung laju aneksasi Israel di Tepi Barat. Namun, bahkan sekadar gestur simbolis seperti ini pun membuat Tel Aviv gelisah.
Alasannya jelas: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha meyakinkan sekutu Barat bahwa satu-satunya “solusi” atas persoalan Palestina adalah pengosongan Gaza dari penduduknya.
Para pemimpin Barat sering kali menyalahkan pemerintahan sayap kanan Netanyahu atas sikap keras kepala ini.
Tetapi fakta di lapangan menunjukkan, hampir seluruh partai politik Zionis di Israel—bahkan yang dianggap kiri sekalipun, seperti Meretz dan Partai Buruh—secara terbuka menolak solusi dua negara.
Dengan demikian, penolakan Israel terhadap gagasan perdamaian bukanlah fenomena baru, apalagi akibat tragedi 7 Oktober.
Ia adalah watak yang sudah mengakar dalam kebijakan negara itu sejak awal pendudukan pada 1967.
Menggagalkan “serangan perdamaian” Palestina
Pada 1976, PLO bersama negara-negara Arab mendorong sebuah resolusi di Dewan Keamanan PBB yang menyerukan solusi dua negara.
Resolusi ini mendapat dukungan dari semua anggota DK PBB, namun Israel menolaknya, sehingga AS turun tangan menggunakan hak veto.
Lima tahun kemudian, pada 1981, PLO secara resmi menyetujui proposal Uni Soviet yang menawarkan pendirian negara Palestina di wilayah 1967, sekaligus menjamin “keamanan dan kedaulatan” Israel.
Beberapa bulan berselang, Raja Fahd dari Arab Saudi mengajukan usulan paling dermawan yang mungkin.
Israel akan diterima sebagai bagian dari kawasan dan dijamin perdamaian dari seluruh negara Arab jika bersedia menerima solusi dua negara.
Usulan tersebut kembali ditegaskan dalam Arab Peace Initiative tahun 2002 dan disepakati oleh 57 negara Muslim. Israel, sekali lagi, memilih mengabaikannya.
Tel Aviv justru melihat momentum ini sebagai ancaman. Mereka menyebutnya sebagai “serangan perdamaian”—Palestina dianggap terlalu moderat, sehingga Israel mulai kehabisan alasan untuk mempertahankan pendudukannya.
Jawaban Israel bukan dialog, melainkan perang terhadap PLO di Lebanon. Tujuannya jelas: memberikan “tekanan militer paling keras” untuk melemahkan faksi moderat Palestina, agar PLO kembali terlihat keras dan kehilangan legitimasi politik di mata dunia.
Oslo dan ilusi proses perdamaian
Pada 1993, Israel terpaksa menerima Perjanjian Oslo. Alasannya bukan karena niat tulus berdamai, melainkan karena gagal meredam Intifada Pertama dengan kekerasan.
Selain itu, juga karena tekanan internasional yang menimbulkan kerugian ekonomi, diplomatik, serta politik akibat strategi “mematahkan tulang” terhadap warga sipil dan anak-anak Palestina.
Dunia menyambut Oslo sebagai babak baru perdamaian. Namun, Israel dengan cermat memasukkan cukup banyak celah agar pendudukan tetap berlanjut.
Perdana Menteri Yitzhak Rabin, yang diganjar Nobel Perdamaian karena Oslo, bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa kesepakatan itu “bukan untuk mendirikan negara Palestina merdeka, melainkan sekadar pemisahan.”
“Apartheid berarti keterpisahan, dan itulah yang kemudian terjadi di lapangan,” katanya.
Alih-alih menuju kemerdekaan, pemukiman Israel justru berkembang pesat. Jumlah pemukim yang masuk ke wilayah pendudukan selama periode “proses perdamaian” jauh lebih banyak daripada sebelumnya.
Sementara itu, rakyat Palestina dipaksa mengawasi sendiri pendudukan Israel dan mencegah perlawanan bersenjata, membuat sistem apartheid berjalan tanpa biaya bagi Tel Aviv.
Pada 2000, Israel menunjukkan kartu sebenarnya dalam perundingan di Camp David.
Tawaran maksimal yang diajukan bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan 3 kantong terpisah (Bantustan) yang dipisahkan pos-pos militer dan permukiman Israel, tanpa hak kembali bagi para pengungsi Palestina.
Israel tetap ingin mengendalikan wilayah udara Palestina, frekuensi radio, jaringan seluler, serta perbatasan dengan Yordania.
Mereka juga berniat mempertahankan pangkalan militer di 13,3 persen wilayah Tepi Barat, menganeksasi 9 persen, dan tetap menempatkan tiga blok permukiman di Gaza yang memecah kantong kecil itu menjadi beberapa bagian.
Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Shlomo Ben Ami, yang juga menjadi negosiator, bahkan mengakui.
“Seandainya saya orang Palestina, saya juga akan menolak syarat-syarat gila di Camp David.” akunya.
Tetapi Israel terus mengklaim bahwa pertemuan tahun 2000 itu adalah “tawaran paling dermawan” mereka, lalu mengulang narasi bahwa “tidak ada mitra perdamaian di Palestina.” Narasi inilah yang dijadikan legitimasi untuk mengabadikan sistem apartheid.
Pada 2005, Israel secara terang-terangan menyatakan bahwa penarikan pasukan dari Gaza dan pemindahan simbolis 9.000 pemukim ke Tepi Barat tak lain adalah strategi untuk “membekukan proses perdamaian” dan mencegah lahirnya negara Palestina.
Setahun kemudian, ketika Ehud Olmert naik sebagai Perdana Menteri, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berusaha mendekatinya untuk membuka kembali perundingan.
Menurut seorang pejabat senior Israel, Abbas menghabiskan 16 bulan untuk meminta Olmert duduk bernegosiasi, tetapi yang terjadi hanyalah penundaan demi penundaan.
Barulah ketika Olmert tersandung kasus hukum, ia mencoba menorehkan “warisan politik” dengan mengajukan proposal serupa Camp David—sambil melancarkan operasi militer paling berdarah di Gaza saat itu, Operation Cast Lead.
Setelah 36 kali pertemuan, di mana pihak Palestina terus-menerus melonggarkan sikap demi mencapai kesepakatan, Olmert akhirnya harus mengundurkan diri. Benjamin Netanyahu kemudian naik menggantikannya.
Hamas dan tawaran yang berulang-ulang
Salah satu dalih utama Israel dalam mempertahankan sistem apartheid adalah narasi yang terus diulang.
“Kami sudah meninggalkan Gaza dan yang kami terima hanyalah roket Hamas,” ujarnya.
Klaim ini sejak lama dipatahkan oleh fakta sejarah. Israel juga gemar menyalahkan runtuhnya proses perdamaian akibat serangan Hamas di tahun 1990-an.
Padahal serangan besar pertama Hamas—pada 1994 di terminal bus Hadera yang menewaskan 5 orang—baru terjadi setelah tragedi Masjid Ibrahimi, ketika seorang pemukim Israel, Baruch Goldstein, membantai 29 warga Palestina saat mereka sedang salat.
Seperti halnya PLO, Hamas sebenarnya juga beberapa kali mengajukan tawaran perdamaian, meski dengan sikap yang lebih hati-hati.
Para pemimpinnya belajar dari pengalaman: bahwa pengakuan PLO terhadap Israel, penghentian perlawanan bersenjata, dan kerja sama dengan aparat keamanan Israel justru tidak membuahkan apa pun. PLO kehilangan alat tawar dan tak mendapat konsesi berarti.
Karena itu, titik awal Hamas adalah menawarkan gencatan senjata jangka panjang, 10 hingga 30 tahun, berupa penghentian penuh permusuhan secara timbal balik tanpa kewajiban melucuti senjata.
Pada 1997, ketika Hamas mengajukan tawaran ini, Israel langsung merespons dengan percobaan pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas, Khaled Meshal, di Yordania.
Pada 2004, pendiri Hamas, Syekh Ahmad Yassin, kembali menegaskan tawaran tersebut—dan dua bulan kemudian ia dibunuh oleh Israel.
Belakangan, sejumlah pejabat Israel sendiri mengakui bahwa mereka sebetulnya bisa mencapai perdamaian dengan Yassin.
Situasi serupa terulang. Pada 2012, ketika Ahmad Jabari—komandan militer Hamas—mendorong tercapainya gencatan senjata permanen, Israel kembali merespons dengan membunuhnya.
Padahal, Haaretz menyebut Jabari sebagai “subkontraktor Israel di Gaza” karena ia selama ini berupaya keras menjaga ketenangan dalam masa gencatan senjata dan menahan kelompok-kelompok lain agar tidak melanggar kesepakatan.
Pada 2006, begitu Hamas membentuk pemerintahan, Perdana Menteri Ismail Haniyeh mengirim surat kepada pemerintahan George W. Bush menawarkan kompromi berdasarkan solusi dua negara.
Penasihat Haniyeh, Ahmad Yousef, bahkan membuat proposal yang dinilai terlalu lunak—hingga Partai Fatah menyebutnya “lebih buruk dari Deklarasi Balfour.”
Isinya: pembentukan negara Palestina dengan perbatasan sementara hanya di sepertiga Tepi Barat (Area A dan B) serta Gaza, yang kemudian diperluas perlahan lewat negosiasi.
Respons Israel yaitu engepung Gaza dengan blokade ketat, menekan Swiss dan Inggris agar melarang kunjungan Yousef maupun pejabat Hamas lain, menahan dana Otoritas Palestina untuk melumpuhkan pemerintahan Hamas, lalu bersekongkol dengan AS menyusun rencana kudeta.
Pada 2008, Hamas bahkan menjalin komunikasi dengan seorang pemukim Israel, Rabbi Menachem Froman, untuk merumuskan gencatan senjata yang mencakup pencabutan blokade Gaza dengan imbalan penghentian penuh permusuhan.
Hamas menyetujui proposal akhir tersebut, Israel menolaknya mentah-mentah, dan tak lama setelah itu melancarkan Operation Cast Lead.
Serangan paling berdarah ke Gaza kala itu, yang menurut PBB bertujuan “menghukum, mempermalukan, dan meneror” penduduk sipil.
Laporan US Institute of Peace pada 2009 mencatat, Hamas “berulang kali mengirim sinyal bahwa mereka siap memulai proses hidup berdampingan dengan Israel.”
Bahkan di tengah genosida Israel di Gaza hari ini, Hamas tetap menyatakan kesediaan untuk berproses secara politik, menawarkan pembubaran sayap militer jika pendudukan diakhiri, atau setidaknya gencatan senjata jangka panjang. Semua ditolak Israel.
Seorang sumber yang dekat dengan perundingan gencatan senjata di Gaza mengungkap kepada The New Arab, bahwa pada 2024 Ismail Haniyeh sempat berdialog dengan AS mengenai kemungkinan menjadikan Hamas sekadar partai politik sipil.
Lawan bicaranya disebut adalah Direktur CIA, Bill Burns. Namun, tak lama setelah proses ini dimulai, Israel membunuh Haniyeh di Teheran.
Catatan sejarah tentang penolakan Israel tidak akan ditulis oleh para propagandis di Tel Aviv atau para penulis pidato di Washington.
Ia akan terukir dalam lembaran panjang, berdarah, tentang kesempatan-kesempatan yang disia-siakan, janji-janji yang dikhianati, dan kebijakan yang secara sengaja menutup jalan perdamaian.
Setiap negosiator yang dibunuh, setiap kesepakatan yang digagalkan, setiap kepanikan Israel bahkan terhadap gestur simbolis pengakuan Palestina.
Semua itu menyingkap kebenaran mendasar: para pemimpin Israel lebih takut pada perdamaian daripada pada perang.
Sebab perdamaian berarti kesetaraan, pertanggungjawaban, dan berakhirnya apartheid.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah bangsa Palestina akan meraih kebebasan atau bersedia hidup berdampingan.
Pertanyaannya adalah: berapa banyak lagi “kesempatan yang dilewatkan” yang akan dipaksakan Israel kepada dunia, sebelum hari itu akhirnya tiba?