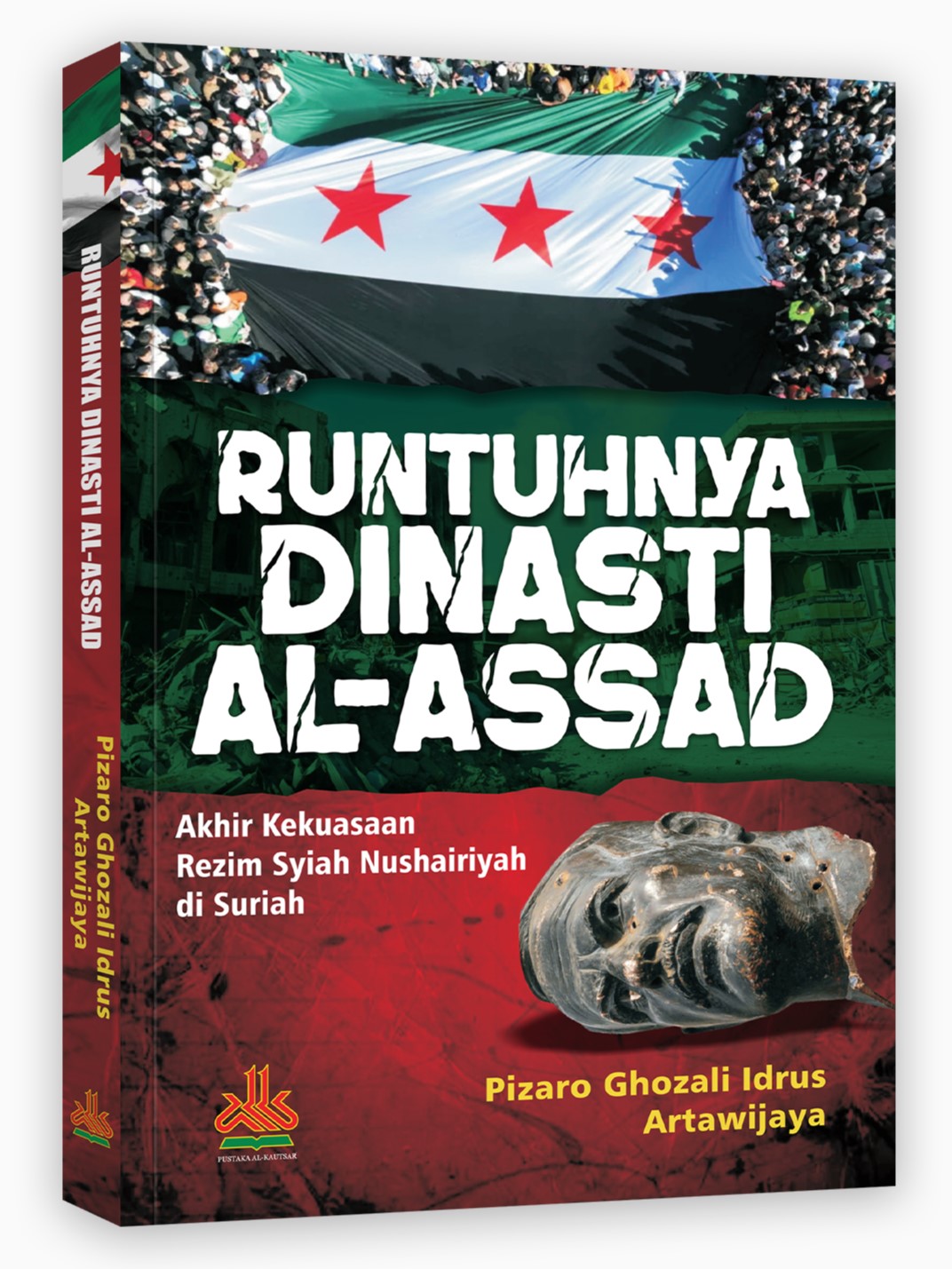Oleh: Saifuddin Mawed*
Respons Hamas terhadap usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memperlihatkan tingkat kesadaran politik yang tajam terhadap jebakan yang coba dipasang Washington dan Tel Aviv di bawah nama “penghentian perang”.
Secara lahiriah, proposal itu tampak sebagai langkah untuk memuaskan ego politik Trump, dengan menonjolkan kesiapan Hamas membahas poin utama usulan itu—yakni pembebasan seluruh tawanan dan jenazah warga Israel sekaligus.
Namun, Hamas dengan tegas mengaitkan langkah itu dengan penghentian agresi dan penarikan penuh pasukan pendudukan dari Jalur Gaza, tanpa terjerumus ke dalam skema “hari setelah perang” yang tengah dirancang Washington dan Tel Aviv.
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan bahwa masa depan Gaza dan hak-hak sah rakyat Palestina bukan urusan satu kelompok semata.
Persoalan itu, menurut mereka, hanya bisa dibahas dalam kerangka nasional Palestina yang menyeluruh—bukan melalui formula yang dipaksakan dari luar.
Dengan demikian, Hamas menarik garis batas yang jelas antara kepatuhan pada tuntutan kemanusiaan dan penolakan terhadap skenario politik yang berpotensi menghapus hak-hak dasar rakyat Palestina di balik slogan “penghentian perang”, “rekonstruksi”, dan “perdamaian”.
Namun, dinamika yang muncul setelah pernyataan Hamas justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Respons cepat AS yang menyebut sikap Hamas sebagai “langkah ke arah yang benar”, tampak lebih sebagai upaya eksploitasi politik ketimbang sambutan tulus.
Trump sendiri tak menyembunyikan ambisinya untuk mencatat namanya dalam sejarah sebagai presiden yang berhasil menengahi kesepakatan pembebasan tawanan Israel.
Namun, inti dari rencana yang ia usung justru tidak mengakhiri pendudukan, melainkan menghidupkannya kembali dengan mekanisme baru.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan segera menyatakan bahwa koordinasi penuh dengan Washington untuk menerapkan bagian pertama dari rencana itu.
Ia juga menegaskan bahwa implementasi akan berlangsung “sesuai dengan prinsip yang ditetapkan Israel.”
Kalimat itu jelas menyiratkan bahwa Tel Aviv akan tetap menjadi pihak yang memegang kendali penuh dalam menafsirkan konsep “keamanan”, “penarikan pasukan”, dan “ancaman”.
Kecepatan dan keserasian antara pernyataan Amerika dan Israel menyingkap munculnya “tahapan baru” yang berpihak sepenuhnya pada Israel.
Dalam skema itu, poin-poin yang menguntungkan Tel Aviv segera dijalankan, sementara isu-isu besar—seperti penghentian perang, penarikan pasukan, pengelolaan Gaza, dan hak menentukan nasib sendiri—ditunda ke dalam proses tawar-menawar panjang, penuh jebakan detail yang siap dimanfaatkan.
Bagi rakyat Palestina, sejarah menghadirkan ingatan pahit yang tak lekang. Mereka pernah menyaksikan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dipaksa keluar dari Beirut dengan jaminan internasional berat.
Namun jaminan itu tak mampu mencegah terjadinya pembantaian setelah pasukan internasional meninggalkan kota dan kamp pengungsinya.
Mereka juga pernah dijanjikan negara lewat Perjanjian Oslo—buah dari pengakuan terhadap Israel dan lima tahun masa “otonomi terbatas”—namun 3 dekade berlalu tanpa kedaulatan yang nyata.
Sebaliknya, pendudukan justru meluas, permukiman bertambah, Yerusalem dianeksasi, dan otoritas Palestina kehilangan kendali di tanahnya sendiri.
Bahkan kemudian, AS secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mengesahkan pencaplokan Dataran Tinggi Golan, dan melegitimasi aneksasi bertahap di Tepi Barat.
Belakangan, rudal-rudal Israel dan Amerika juga berjatuhan di berbagai ibu kota kawasan, bahkan ketika perundingan masih berjalan.
Tak jarang, para negosiator sendiri menjadi target serangan. Israel juga telah berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan Lebanon dengan alasan “menyelesaikan tujuan militer yang belum tuntas”.
Rangkaian peristiwa itu menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana jaminan Amerika bisa dipercaya?
Pengalaman menunjukkan, jaminan Washington kerap berubah menjadi payung taktis yang bisa dibatalkan kapan pun kepentingannya berubah.
Kecurigaan itu tak lahir dari pesimisme, tetapi dari pembacaan tekstual terhadap apa yang disebut sebagai “Rencana Trump untuk Menghentikan Perang”.
Siapa pun yang menelaah isi rencana itu akan menyadari: dokumen tersebut tidak dirancang untuk mengakhiri agresi, melainkan untuk mengelolanya dengan cara baru.
Rencana yang dikemas sebagai dokumen kemanusiaan demi perdamaian itu sesungguhnya digerakkan oleh logika kolonial. Ia ingin mengubah nama pendudukan tanpa mengubah hakikatnya.
Dalam rancangan tersebut, penghentian tembakan dimulai dengan kesepakatan pertukaran tawanan.
Namun, penghentian itu akan ditutup dengan syarat pelucutan senjata dan pembentukan pemerintahan “transisi” yang ditetapkan dari luar Gaza, bukan oleh rakyatnya sendiri.
Lebih jauh, Israel akan mempertahankan “zona keamanan” di dalam dan di luar wilayah Gaza, dengan rincian yang diserahkan pada “pertimbangan lapangan” mereka sendiri.
Di antara baris-baris teks itu tersembunyi konsep yang berbahaya: negara Palestina hanya disebut sebagai “aspirasi tertunda”.
Sementara penarikan pasukan dikaitkan dengan kemajuan dalam “penghapusan ancaman”—istilah yang definisinya diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang memiliki kekuatan militer.
Netanyahu bahkan secara terbuka mengonfirmasi bahwa penarikan Israel akan bergantung pada pelucutan senjata Hamas, dan menegaskan niatnya mempertahankan pasukan “di sebagian besar wilayah Gaza”, sekaligus memastikan pemisahan permanen antara Gaza dan Tepi Barat.
Ia juga dengan bangga menyebut keberhasilan mengisolasi Hamas di tingkat regional maupun internasional.
Pada saat yang sama, muncul rencana pembentukan “dewan supra-nasional” yang akan mengelola Gaza pascaperang.
Figur-figur yang disiapkan untuk memimpin lembaga itu bukanlah sosok baru; mereka berasal dari lingkaran yang berpengalaman dalam kolonialisme dan strategi memecah belah negara.
Sementara itu, sejumlah ibu kota Arab dan Muslim ditempatkan sekadar sebagai penyandang dana dan pelaksana lapangan.
Dengan demikian, terbentuklah kerancuan yang disengaja: satu rencana dengan banyak wajah.
Satu versi yang menonjolkan aspek kemanusiaan, satu versi yang menegaskan keamanan bagi Israel, dan versi lain yang mengatur peran negara-negara di kawasan agar tetap berada dalam orbit tekanan dan ketergantungan.
Membaca tanggapan Israel terhadap pernyataan Hamas yang bersedia membebaskan seluruh tawanan sekaligus.
Lalu mengaitkannya dengan prinsip yang diumumkan Netanyahu di Gedung Putih, tampak jelas bahwa orientasi negosiasi Amerika-Israel hanya berjalan searah.
Segala bentuk konsesi harus dilakukan pihak Palestina terlebih dahulu, sementara hak-hak mereka sendiri digantung tanpa batas waktu.
Inilah inti dari “komitmen bertahap”—sebuah pola yang mengharuskan pihak lemah membayar harga kontan, sementara pihak kuat menunda kewajibannya ke masa depan tanpa tanggal.
Dari celah inilah tipu daya diplomasi menyusup: gencatan senjata digunakan bukan untuk melindungi warga sipil.
Melainkan sebagai jembatan menuju rekayasa politik baru yang bertujuan menyingkirkan kekuatan perlawanan dan menggantinya dengan bentuk pengawasan yang lebih halus maupun keras.
Untuk memahami fungsi sebenarnya dari rencana Amerika-Israel ini, konteksnya harus diperjelas.
Dua tahun setelah perang pemusnahan di Gaza, Israel gagal mencapai seluruh tujuannya: para tawanan belum dikembalikan, perlawanan belum dilenyapkan, dan semangat warga Gaza belum dipatahkan meski korban begitu besar.
Upaya memaksakan eksodus massal pun tidak berhasil.
Di sisi lain, Amerika—yang mendukung agresi Israel secara politik dan militer—mendapati legitimasi moralnya terkikis hebat, baik di jalan-jalan dunia, di lembaga-lembaga internasional, maupun di antara sekutu yang mulai merasa gerah.
Rencana Trump dengan demikian tampil sebagai jembatan penyelamat: alat untuk mengeluarkan Netanyahu dari isolasi, mengembalikan dominasi Amerika dalam bentuk “pengawasan kemanusiaan”.
Seain itu juga mengubah kegagalan militer menjadi kemenangan diplomatik yang dikemas sebagai “perdamaian”.
Dalam bahasa propaganda, ini hanyalah “penamaan ulang dari hal yang sama”.
Lebih berbahaya lagi, rencana ini menyerang jantung masyarakat Palestina dari dalam.
Ia menstigma perlawanan sebagai kejahatan, membenarkan pendudukan atas nama perang melawan “terorisme”, dan bahkan menjanjikan “amnesti” bagi para pejuang jika mereka bersedia hidup damai di bawah kekuasaan pendudukan.
Ironinya begitu mencolok: para pelaku kejahatan perang justru menawarkan pengampunan kepada korban yang mempertahankan haknya.
Ini merupakan upaya sistematis untuk mengebiri legitimasi moral dan historis dari perjuangan kemerdekaan Palestina, dengan menggantinya melalui wacana “reformasi” dan “dialog deradikalisasi” sebagaimana termaktub dalam rencana itu.
Sebuah strategi untuk menanamkan narasi baru dalam sistem pendidikan bahwa pendudukan adalah “kakak besar” yang harus ditaati, sebagaimana dalam novel klasik 1984 karya George Orwell.
Rencana ini, pada akhirnya, berupaya menulis ulang identitas Palestina agar rakyatnya berhenti memimpikan tanah air yang dirampas.
Ia ingin menggantikan gagasan kembali dan merdeka dengan mentalitas tunduk dan menerima.
Dalam kerangka itu, hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri terancam dicabut. Bahkan kedua sumber otoritas nasional—baik pemerintah maupun perlawanan—akan dilucuti kewenangannya.
Anehnya, Otoritas Palestina yang justru dikeluarkan secara eksplisit dari rencana ini malah menyambutnya dengan gembira, seolah menyetujui vonis pembubarannya sendiri. Entah karena keluguan politik, entah karena tekanan—dua-duanya berbahaya.
Rencana itu bukan sekadar permainan istilah, melainkan upaya mengubah bingkai perjuangan Palestina dari proyek pembebasan nasional menjadi urusan penanggulangan ekstremisme.
Bahasa hukum internasional dipinjam untuk menutupi tindakan yang justru melanggarnya.
Tidak ada jaminan hukum PBB, tidak ada mekanisme sanksi bagi pelanggaran, dan tidak ada partisipasi sejati dari korban yang dijadikan objek semata.
Karena itu, Gaza harus membaca setiap kata dalam teks itu dengan ukuran yang diajarkan oleh pengalamannya sendiri.
Setiap skema yang memisahkan Gaza dari Tepi Barat atau membentuk pemerintahan tanpa horizon politik, sejatinya adalah resep untuk perpecahan dan likuidasi.
Setiap pengaturan keamanan yang memberi Israel hak untuk mendefinisikan “ancaman”, berarti memperpanjang pendudukan dan pembunuhan.
Dan setiap peta politik yang tidak disertai jaminan penarikan pasukan secara penuh, dengan tenggat waktu pasti di bawah pengawasan hukum internasional, hanyalah bentuk penipuan politik.
Rakyat Gaza tentu menginginkan penghentian pembantaian secepatnya, dan itu pula yang diharapkan oleh siapa pun yang masih memiliki nurani.
Namun pertanyaan etis dan politis yang tak bisa dihindari adalah: dengan harga apa? Di bawah kontrak macam apa? Dengan jaminan siapa?
Siapa yang bisa memastikan bahwa kelonggaran Hamas terhadap beberapa poin rencana itu akan benar-benar menghentikan genosida, sementara inti rencana justru mengarah pada pelucutan kekuatan mereka dan memperpanjang pendudukan?
Rencana itu bahkan tidak menjamin penghentian perang secara permanen; satu-satunya jaminan hanyalah penangguhan sementara operasi militer sampai tawanan Israel dibebaskan.
Setelah itu, Israel tetap memegang hak untuk kembali menyerang kapan pun atas nama “keamanan”.
Trump bahkan telah menyerukan penghentian tembakan sebelum membahas secara rinci tanggapan Hamas,
Karena ia tahu bahwa kekuatan sesungguhnya ada di tangan pihak yang masih berhak memutuskan kapan perang dimulai kembali.
Kekuatan internasional yang dijanjikan untuk “memelihara perdamaian” pun akan dipimpin Amerika, bukan untuk melindungi rakyat Gaza, melainkan untuk memburu para pejuang dan membongkar infrastruktur perlawanan atas nama stabilitas.
Maka, wajar jika rencana ini hanya menghasilkan “gencatan rapuh”—sebuah jeda, bukan akhir dari tragedi.
Dalam situasi ini, perlawanan Palestina berada di persimpangan sulit. Menerima perangkap berarti menyerahkan senjata dan hak masa depan; menolak berarti menanggung beban moral dari kelanjutan pembantaian di hadapan dunia.
Dilema ini merupakan hasil dari ketimpangan kekuatan dan keberpihakan internasional terhadap Israel.
Namun juga buah dari kesalahan perhitungan sejumlah ibu kota Arab dan Muslim yang mengira tekanan dan jaminan simbolik cukup untuk mengelola dampak perang.
Seolah-olah sumber masalahnya adalah perlawanan, bukan pendudukan dan dukungan militer Amerika terhadapnya.
Padahal, penerapan Rencana Trump akan membawa dampak regional yang tak kalah berbahaya dari perang itu sendiri.
Ia membuka jalan bagi penerapan model “pengawasan” di seluruh dunia Arab atas nama “penghapusan ancaman”, sebagaimana sedang diuji coba di Gaza hari ini.
Apa yang diterapkan di Gaza bisa direplikasi di Tepi Barat, Lebanon, Suriah, atau bahkan di ibu kota Arab dan Muslim lainnya.
Sebab proyek Zionis pada hakikatnya merupakan perpanjangan dari fungsi imperium kolonial untuk mempertahankan dominasi atas jantung dunia lama.
Semakin lemah kemampuan Amerika memaksakan hegemoni secara langsung, semakin besar kebutuhan untuk menjadikan Israel pusat gravitasi politik, militer, dan ekonomi di Kawasan.
Sebuah pusat yang menarik negara-negara sekitarnya ke dalam orbit ketergantungannya.
Kritik terhadap rencana itu, tentu, belum cukup. Jika Gaza hari ini menjadi simpul penentu antara dunia Arab-Muslim yang ingin memulihkan peran historisnya dan wilayah yang terancam terjerumus lebih dalam ke dalam penjajahan modern, maka dibutuhkan visi yang jelas dan peta jalan yang berlandaskan keadilan.
Tak ada makna pembicaraan tentang “keamanan regional” tanpa fondasi moral dan hukum yang menghentikan pembunuhan massal, membongkar sistem kolonisasi, dan mengakhiri pendudukan.
Maka, berhadapan dengan Rencana Trump bukanlah urusan internal Palestina semata, tetapi ujian moral bagi seluruh dunia Arab dan Islam.
Taruhan terbesar kini terletak pada kemampuan rakyat Palestina—bersama seluruh kekuatan nasionalnya—dengan dukungan kuat dari negara-negara Arab dan Muslim, untuk menyusun posisi politik yang utuh.
Yaitu, posisi yang menolak jebakan, memulihkan prioritas perjuangan di atas prinsip pembebasan dan keadilan, bukan di atas dasar tekanan dan kompromi.
Rincian implementasi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada Washington dan Tel Aviv.
Hanya dengan keterlibatan serius kekuatan Arab dan Islam yang mampu menggunakan instrumen tekanan politik dan ekonomi terhadap Amerika, penghentian perang sejati dapat tercapai.
Pendekatan itu menuntut dua payung besar. Pertama, payung kemanusiaan segera untuk menghentikan pembantaian dan membuka jalur bantuan tanpa syarat politik.
Kedua, payung politik yang berlandaskan prinsip tetap. Penarikan penuh pasukan pendudukan dalam batas waktu pasti, pengakuan hukum internasional yang mengikat, penyatuan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah pemerintahan Palestina yang dipilih rakyat secara demokratis, serta keadilan bagi korban melalui rekonstruksi dan kompensasi.
Kita tengah menghadapi ujian besar kesadaran dan keberanian moral umat. Negosiasi apa pun tidak boleh mengorbankan prinsip dasar rakyat Palestina.
Selain itu juga pengelolaan “hari setelah perang” tidak boleh merampas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Yang dibutuhkan bukanlah solusi yang “mematikan dengan dalih penyelamatan”, melainkan penghentian perang yang sungguh-sungguh melindungi warga sipil, tanpa menyerahkan kunci masa depan Palestina kepada pendudukan.
*Saifuddin Mawed merupakan seorang penulis dan jurnalis Palestina. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengaan judul “Kaifa Tanjaḥu Ḥillah Ḥamās wa Tanjau Min al-Fakhi?”.