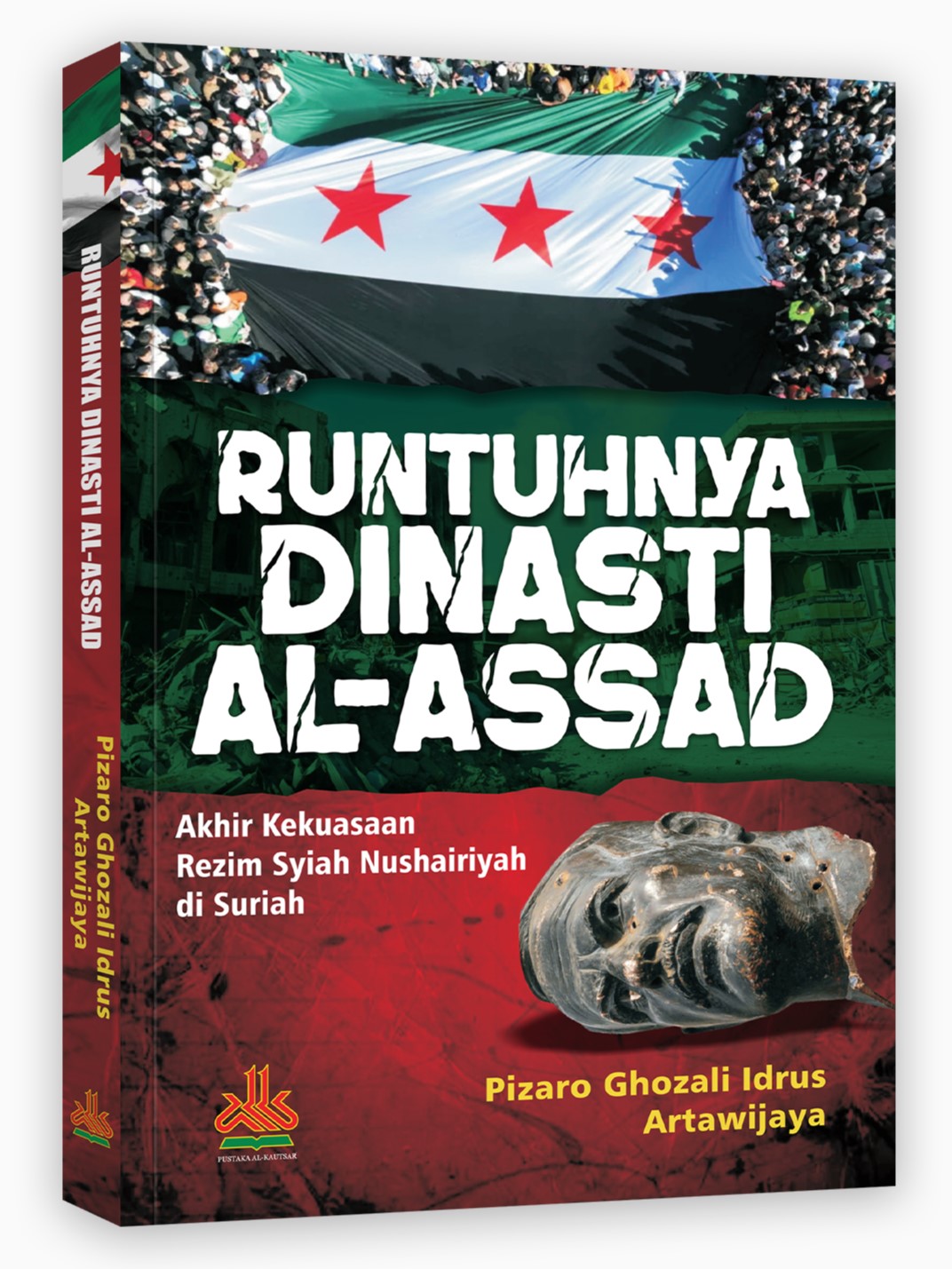Oleh: Mahmud Sultan
Sebelum “Thaufan Al-Aqsha” pada 7 Oktober 2023, para pembuat kebijakan di pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang berturut-turut—terutama sejak era Obama dan penerusnya—telah beranggapan bahwa konflik Israel-Palestina tidak lagi memerlukan investasi politik yang signifikan di Timur Tengah.
Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa kawasan Arab yang sebelumnya kokoh telah menjadi semakin lemah dalam menghadapi skenario normalisasi hubungan yang besar dan berani.
Wilayah-wilayah ini telah bergeser menjadi pusat pengaruh politik dan peradaban yang memiliki “suara yang didengar” dan wibawa regional yang tidak dapat diabaikan jika ada konsensus internasional dan regional mengenai masa depan kawasan tersebut.
Selain itu, pemerintahan AS percaya bahwa perlawanan Palestina—sebelum 7 Oktober—terlalu lemah untuk menciptakan kekacauan besar.
Mereka yakin bahwa “kekerasan yang mungkin terjadi” dapat dikendalikan dengan metode dan pengalaman yang telah diwariskan dari waktu ke waktu.
Berdasarkan pendekatan ini, AS pun menyusun kembali prioritasnya, menempatkan “poros Asia” sebagai fokus utama, serta mengurangi investasi politik dan militer di Timur Tengah.
Langkah ini bertujuan untuk lebih berkonsentrasi pada tantangan yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dalam menghadapi kebangkitan China, yang secara resmi sering digambarkan oleh Washington sebagai “agresif”.
Namun, perang di Gaza membalikkan strategi ini secara drastis dan memaksa AS untuk terlibat lebih dalam dalam permasalahan di kawasan ini dibandingkan sebelumnya.
Washington tidak hanya berusaha “menyelesaikan” krisis ini seperti yang ingin mereka tampilkan di mata dunia, tetapi juga menjadi mitra utama dalam perang pemusnahan yang dilakukan Israel.
AS tidak hanya memberikan perlindungan politik dan diplomatik terhadap kebrutalan Israel serta mencegahnya dari tuntutan hukum internasional. Tetapi juga menyediakan dukungan logistik, intelijen, serta mengisi kembali persediaan senjata Israel dengan jumlah yang bahkan melebihi yang digunakan oleh AS sendiri dalam perang-perangnya di luar negeri.
Selain itu, AS juga menggunakan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghalangi resolusi yang menuntut penghentian kekerasan. Meskipun jumlah korban jiwa terus meningkat dan bukti ketidakpedulian Israel terhadap korban Palestina semakin nyata.
Peran AS ini semakin memperburuk citranya di kawasan yang sebelumnya pun sudah tidak terlalu dihormati. Akibatnya, muncul kekosongan yang secara alami diharapkan akan diisi oleh dua kekuatan global yang sedang naik daun: Rusia dan China.
Jika tidak untuk tujuan lain, setidaknya mereka dapat memanfaatkan situasi ini untuk “mengganggu balik” AS guna mengurangi tekanan terhadap mereka di Ukraina dan Taiwan.
Secara historis, China sejak era Mao Zedong (1893-1976) telah mendukung perjuangan Palestina.
Sikap ini didasarkan pada prinsip bahwa China harus menentang semua yang didukung oleh AS. Terutama karena Beijing menempatkan dirinya sebagai pendukung utama negara-negara berkembang di dunia. Termasuk banyak negara Arab yang memiliki hubungan baik dengannya.
Selain itu, kawasan Arab adalah pemasok utama kebutuhan energi China, yang sangat bergantung pada minyak dari negara-negara Teluk.
Dukungan terhadap Palestina juga menjadi cara bagi China untuk menyeimbangkan kecaman dunia Muslim dan Arab atas perlakuannya terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.
Di sisi lain, China juga memiliki kepentingan ekonomi di kawasan ini, terutama melalui proyek ambisiusnya, Belt and Road Initiative (BRI), yang bertujuan menghubungkan pasar global dan memperluas pengaruhnya.
Sementara itu, Rusia, baik di era Uni Soviet maupun setelahnya, secara konsisten memberikan dukungan kepada perjuangan Palestina.
Perjuangan kemerdekaan Palestina selalu mendapat tempat dalam pemikiran politik Rusia, yang sejak lama memiliki hubungan dengan gerakan-gerakan anti-kolonialisme.
Dukungan ini terus berlanjut meskipun terjadi perubahan global pasca-Perang Dingin. Rusia tetap menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan di kawasan yang sering kali bertentangan satu sama lain. T
ermasuk Israel, Palestina, Hamas, Hizbullah, Iran, dan kekuatan-kekuatan Arab besar lainnya.
Namun, hubungan ini tetap bersifat “di batas” atau “di tepian”, tidak cukup dalam dan tidak cukup dipercaya untuk menjadikan Rusia sebagai mitra global yang dapat diandalkan dalam konflik ini.
Di awal perang Gaza, Moskow dan Beijing memang melakukan upaya untuk meningkatkan kredibilitas diplomatik mereka dan menunjukkan kemampuan mereka dalam memimpin, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.
Tidak lama setelah serangan balasan Israel terhadap Gaza pada Oktober 2023, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengecam tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional. Presiden Vladimir Putin bahkan membandingkan pengepungan Israel atas Gaza dengan pengepungan Leningrad oleh Nazi Jerman.
Banyak politisi dan anggota parlemen Rusia pun menggemakan pandangan ini, tanpa mengecam serangan Hamas seperti yang dilakukan oleh negara-negara sekutu AS di Eropa.
Langkah Rusia ini berseberangan dengan sikap negara-negara Barat yang secara terbuka mendukung Israel.
Hanya tiga minggu setelah serangan Hamas ke Israel selatan, Moskow juga menerima delegasi tingkat tinggi dari Hamas yang dipimpin oleh salah satu pendirinya, Mousa Abu Marzouk.
Meskipun Rusia sebelumnya sudah dua kali menerima delegasi Hamas pada tahun 2023, pertemuan ini dipandang sebagai tantangan nyata terhadap arus utama Barat yang berpihak kepada Israel.
Secara resmi, Rusia beralasan bahwa dialog dengan semua pihak diperlukan untuk mencapai kesepakatan guna menghentikan “kekerasan” di wilayah pendudukan.
Meski perundingan ini menghasilkan pembebasan beberapa sandera berkewarganegaraan Rusia, hasil tersebut dinilai minim dan tidak berhasil memperkuat posisi diplomatik Rusia dalam menyelesaikan krisis Gaza.
Di sisi lain, sementara Rusia secara tegas menunjukkan kedekatannya dengan Hamas, China justru mengambil sikap yang lebih samar dan tidak menunjukkan ambisi untuk menggantikan peran AS di kawasan ini.
Sikap diplomatik China dalam konflik ini bisa digambarkan sebagai “tidak berpihak secara eksplisit”, mirip dengan mesin-mesin berat buatan China yang bekerja lambat tetapi stabil.
Terlepas dari upaya mereka untuk menarik simpati dunia Arab dan membangun citra internasional di atas kelemahan AS.
Baik Moskow maupun Beijing belum membuktikan bahwa mereka dapat memainkan peran diplomatik yang signifikan dalam menciptakan solusi politik bagi konflik Israel-Palestina.
Sebaliknya, Washington—terlepas dari kebenciannya di dunia Arab—tetap menjadi pihak yang paling aktif berinteraksi dengan pemerintah regional untuk mengatur gencatan senjata kemanusiaan dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.
Pada akhirnya, meskipun banyak pihak di kawasan ini kecewa dengan AS. Mereka masih melihat Washington sebagai satu-satunya kekuatan yang memiliki kapasitas untuk mendorong proses perdamaian yang dapat diterapkan—jika AS benar-benar menginginkannya.
*Mahmud Sultan adalah seorang penulis dan jurnalis Mesir. Ia juga peneliti sosiologi politik dan agama serta anggota Majelis Umum Sindikat Jurnalis Mesir. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Ghazah Fī Laḥdzah Fāriqah, Hal Tatakharak Rūsiyya wa al-Shīn?”.