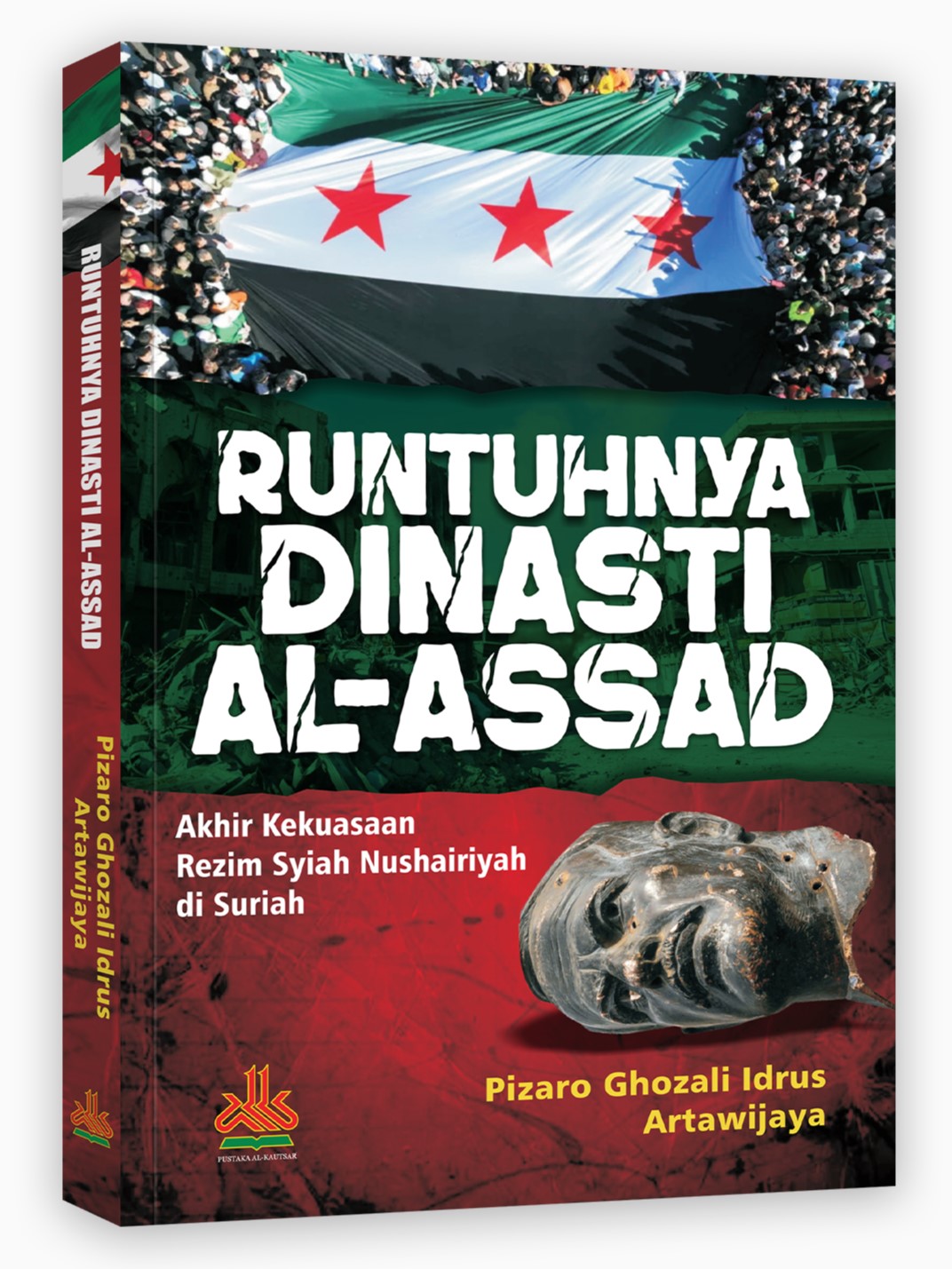Oleh: Saifuddin Mawed*
Apa sebenarnya yang berubah di kawasan ini sejak Perjanjian Camp David hingga hari ini? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawaban atasnya justru membuka inti dari persoalan kita.
Proyek Zionis, sejatinya, tidak pernah meninggalkan bahasa pertamanya. Semua wacana tentang “proses perdamaian”, “solusi dua negara”, atau “keterlibatan konstruktif”, pada kenyataannya, hanyalah selubung diplomasi.
Dalam versi yang paling ramah sekalipun, ia tak lebih dari manuver politik yang menunda waktu, sembari tetap berpijak pada kaidah strategis yang menganggap kekuatan senjata sebagai satu-satunya bahasa yang berlaku di kawasan.
Para pemimpin Arab menyadari hal itu. Mereka tahu, Tel Aviv tidak pernah bersandar pada prinsip “tanah sebagai imbalan bagi perdamaian”.
Mereka juga paham bahwa slogan “solusi dua negara” sejak awal diperlakukan sekadar sebagai alat hubungan masyarakat, yang menunda kewajiban sambil menumpuk fakta di lapangan.
Namun, sebagian besar rezim Arab tetap saja menggantungkan harapan pada jaminan lisan, pada mediasi Amerika Serikat (AS), dan pada “garis merah” yang sejatinya tidak pernah eksis.
Dengan cara itu, proses pun bergerak perlahan—dari perdamaian yang disyaratkan dengan penarikan pasukan, ke perdamaian tanpa syarat, dan pada akhirnya ke bentuk perdamaian yang diam-diam dipahami sebagai kepatuhan terhadap logika kekuatan.
Dari sudut pandang inilah, rangkaian peristiwa dari Gaza hingga Doha tidak bisa dipandang sekadar sebagai potongan-potongan yang terpisah.
Ia adalah cermin dari cara kita membaca kenyataan. Dalam imajinasi strategis Israel, peta kawasan selalu bisa diperluas, negara-negara di sekitarnya diperlakukan sebagai “ruang hidup” yang dapat direkayasa ulang setiap kali kesempatan muncul.
Siapa pun yang gagal memahami pergeseran ini, tidak akan pernah mengerti Israel hari ini. Aturan dasarnya sederhana: hak ditentukan sejauh mana pesawat tempur dan roket mereka bisa menjangkau.
Barang siapa mampu membendungnya, silakan. Jika tidak, maka yang tersisa hanyalah penyesuaian diri.
Sebagian kalangan masih menilai bahasa politik semacam itu hanya gejala sementara dari pemerintahan sayap kanan yang ekstrem, dan bisa berubah seiring bergantinya rezim.
Namun, bila kita kembali ke teks para pendiri dan fondasi ideologis Zionisme, akan jelas bahwa persoalannya jauh lebih mendasar.
Sejak awal, Zionisme memosisikan diri sebagai pengecualian: di atas hukum, di luar kompromi politik.
Dari Ze’ev Jabotinsky dengan teori “tembok besi” yang menekankan kekuatan militer untuk memutus harapan bangsa Arab, hingga David Ben-Gurion yang menganggap penerimaan atas pembagian wilayah hanya sebagai taktik menuju penguasaan penuh.
Dari Rabbi Tzvi Kook yang merumuskan Zionisme religius sebagai doktrin utuh—menyucikan tanah Israel imajiner, menjadikan permukiman dan seragam militer sebagai panggilan suci—hingga generasi Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, dan Itamar Ben-Gvir yang tumbuh dengan keyakinan bahwa tanah Alkitab, dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat, adalah hak sejarah yang harus diwujudkan dalam negara Yahudi.
Gagasan ekspansionis itu kini bukan lagi sekadar isi buku atau khotbah sinagog. Ia sudah menjelma menjadi kebijakan negara.
Didukung keunggulan militer, teknologi, dan diplomasi, Israel dengan sadar mengeksploitasi keretakan internal kawasan. Netanyahu bahkan berani mengumumkan secara terbuka komitmennya pada gagasan “Israel Raya”.
Ia berbicara tentang memperluas “kedalaman strategis” hingga meliputi kawasan luas di Timur Tengah dan Afrika Utara, dengan dalih “pencegahan ancaman” yang tak pernah berhenti.
Bahasa itu mengingatkan pada konsep “ruang hidup” Nazi, pada gagasan fragmentasi negara-negara menjadi unit-unit kecil sebagaimana dirancang Oded Yinon, bahkan pada wacana lama tentang “Yordania sebagai tanah alternatif” bagi Palestina.
Skenario itu selalu disertai gagasan penjinakan Mesir, pelemahan militernya, dan subordinasi kawasan dalam narasi “Timur Tengah Baru” yang diyakini sebagai prasyarat bagi keamanan Israel.
Untuk memahami konsistensi perilaku Zionisme, kita harus menilik akar intelektual yang menopangnya.
Proyek ini sejak awal membentuk kembali identitas Yahudi modern di atas tiga pilar: tanah sebagai hak historis yang tidak dapat dipisahkan, Israel sebagai entitas di atas hukum, dan komunitas Yahudi sebagai bangsa yang suci sekaligus selalu terancam sehingga memerlukan perlindungan preventif.
Di dalam negeri, kitab suci dihadirkan sebagai alat mobilisasi dan legitimasi. Di luar negeri, narasi politik dibungkus dengan bahasa sekuler yang luwes.
Di balik keduanya, bekerja mesin pengetahuan dan media yang konsisten menanamkan gagasan Zionisme sejak sekolah hingga universitas, dari layar film hingga pemberitaan, dari mimbar politik hingga khotbah keagamaan.
Di tingkat pelaksanaan, Israel menerapkan strategi bertahap untuk menggerogoti apa yang semula dianggap tabu dan garis-garis merah.
Ia mengukur batas terlebih dahulu; jika tidak ada respons setimpal, pelanggaran tersebut cepat berubah menjadi norma baru.
Apa yang terjadi hari ini di Gaza—pembantaian yang berlangsung secara bertahap—adalah contoh nyata dari logika itu.
Pembunuhan menjadi prosedur administratif, pemindahan paksa menjadi opsi logistik, dan pengepungan serta kelaparan dijadikan alat tekanan yang terstruktur.
Di Tepi Barat proses penggerogotan, aneksasi, dan yahudisasi berlangsung dengan langkah-langkah yang perlahan namun konsisten.
Di sana pun, warisan pemikiran ekstrem seperti yang diwakili oleh rabbi Meir Kahane—yang merumuskan resep mengerikan untuk meledakkan kompleks Al-Aqsha dan menyingkirkan seluruh warga Palestina sebagai “kendala” bagi kemurnian negara Yahudi—kembali menyuburkan narasi-narasi eksklusif yang berbahaya.
Di Suriah dan Lebanon, front konflik dikelola melalui kebijakan pemerasan: serangan berulang yang dibalut legitimasi semu dan berlandaskan apa yang bisa disebut “deterrence berjalan”.
Dengan pola serupa, bab-bab konfrontasi terhadap Iran dan Yaman diurus; bahkan tak tertutup kemungkinan serangan menyeberang menuju Tunisia dan Qatar.
Langkah demi langkah, batasan-batasan dilanggar—tanpa konsekuensi berarti—hingga setiap pelanggaran menjadi kebiasaan dan “melampaui tanpa biaya” berubah menjadi strategi permanen.
Selain itu, kawasan ini diperlakukan sebagai ruang yang bisa dibelah berdasarkan garis-garis sektarian dan etnis bila itu menguntungkan arsitektur dominasi. Di titik ini, proyek Zionis bertemu dan berfungsi sesuai kepentingan proyek hegemoni AS.
Ideologi ekspansionis Zionis sulit mewujud tanpa sandaran-sandaran lokal dan eksternal; dari faktor-faktor itu, AS menempati posisi sentral.
Kita tidak dihadapkan pada tindakan-kehendak-murni oleh sebuah entitas semata: apa yang terjadi hari ini juga merupakan pelaksanaan strategi Amerika yang lebih luas untuk mengamankan dominasi atas Timur Tengah—yang kini lebih tepat disebut Asia Barat—tanpa harus terseret dalam konfrontasi langsung dengan kekuatan-kekuatan lain seperti Tiongkok atau Rusia.
Tujuannya jelas: menguasai cadangan sumber daya—minyak dan gas—serta memperkokoh kontrol atas jalur-jalur pelayaran strategis.
Dalam kerangka itu, Israel bukan sekadar sekutu; ia adalah “carrier” statis di darat, alat tekan yang bisa diaktifkan untuk memengaruhi kebijakan rezim di sini, atau menekan keputusan di sana—melalui kombinasi legitimasi selektif, sanksi, bantuan militer bersyarat, veto berkala, dan jaringan ketergantungan ekonomi-keamanan.
Hasilnya adalah integrasi yang timpang: klaim-klaim “bersejarah” dipakai untuk menutupi akar persoalan.
Sementara “kekacauan kreatif” (creative chaos) telah melahirkan peta-peta kehancuran di Irak, Suriah, Libya, Sudan, dan Yaman—dan mengkriminalkan setiap bentuk perlawanan atau upaya kemandirian.
Namun struktur ini tak dapat berfungsi sendiri; ia memerlukan lingkungan Arab yang mudah ditembus. Kejadian 7 Oktober dan gelombang yang mengikutinya menjadi cermin keras.
Betapa tubuh politik Arab dan Islam tampak lemah daya tahanya, sedangkan Israel tampak sebagai organisme yang tahu bagaimana bertahan, menyerap energi, dan mendaur ulang krisis untuk keuntungan agenda sendiri.
Meski simpati global terhadap hak-hak Palestina melonjak, dorongan itu belum menerjemah menjadi strategi Arab atau Islam yang efektif.
Diskursus kemanusiaan sering berdiri sendiri, terlepas dari instrumen kekuatan; bahkan ada saat-saat ketika korban dilayangkan kritikan dan aspek-aspek perlawanan dimarginalkan secara media, sementara sebagian pihak secara langsung atau tidak langsung memberi napas ekonomi — dan kadang-kadang dukungan militer — kepada penjajah.
Seolah sejarah baru dimulai pada 7 Oktober, menghapus tujuh dekade pendudukan, pemindahan, dan “pembersihan”.
Akibatnya, momentum yang semestinya bisa diubah menjadi keputusan kolektif untuk menaikkan biaya agresi dan mengkonversi solidaritas internasional menjadi keuntungan politik konkret terlewatkan.
Gaza hari ini menjadi batu sandungan terhadap proyek desintegrasi itu. Meski dengan harga yang amat mahal, Gaza membuktikan bahwa proyek Zionis bukanlah takdir yang tak bisa dilawan.
Namun, bila Israel berhasil menundukkan Gaza, pesan yang dikirim tak hanya kepada penduduk Palestina: ia adalah peringatan bagi seluruh kawasan—terima dominasi mutlak atau siap-siap menghadapi kehancuran total.
Bahayanya nyata: keberhasilan menundukkan Gaza dapat membuka pintu bagi operasi “penyelesaian” ke Tepi Barat, Yerusalem, dan warga Palestina di dalam garis tahun 1948; itu juga bisa mendorong ekspansi territorial ke utara dan timur, mengobarkan konflik internal, bahkan memicu upaya pemecahan negara-negara besar seperti Irak, Suriah, dan Mesir. Ancaman serupa tidaklah jauh dari Turki atau Iran.
Simpulan sederhana namun menggigit: serangkaian kebijakan yang tampak episodik sejatinya membentuk pola strategis.
Melawan pola itu membutuhkan bukan sekadar empati atau kecaman moral, melainkan strategi yang menaikkan harga bagi agresor—langkah-langkah diplomatik, politik, dan praktis yang konkret dan terpadu dari blok Arab dan komunitas internasional—agar pelanggaran tidak lagi menjadi norma yang bisa dinormalisasi.
Boleh jadi ada yang berpendapat: mari bertaruh pada waktu — proyek Zionis rapuh dan dapat runtuh cepat oleh faktor-faktor internal, jadi mengapa terburu-buru? Itu salah kaprah.
Kenyataan menunjukkan kekuatan Israel bersifat multi-dimensi: keunggulan teknologi dan militer yang nyata, kelenturan politik luar negeri berpadu dengan kekakuan ideologis di dalam negeri, jaringan kepentingan yang saling melayani dengan Barat—terutama AS—serta kemampuan tinggi untuk mengelola waktu panjang.
Namun realitas itu bukanlah takdir yang tidak bisa dilawan. Titik lemah Israel ada pada kontradiksi strukturalnya.
Proyek ekspansi kolonial yang dipaksakan di luar konteks historisnya; berakar pada doktrin religius yang sulit ditawar; sebuah negara yang ingin sekaligus “normal” dan “istimewa”.
Oleh karenanya garis pertahanan pertama bukanlah semata-mata berteriak pada hukum internasional, melainkan membangun kekuatan tandingan yang mampu mendefinisikan kembali biaya setiap agresi—bahkan merebut inisiatif untuk menghadang ancaman Zionis.
Untuk menata kekuatan itu, harus ada pengakuan jujur bahwa lingkungan Arab mengalami kelainan struktural yang berat.
Negara-negara Arab modern mewarisi birokrasi besar warisan kolonial yang mengerdilkan ruang publik dan menyingkirkan warga dari politik dan pengambilan keputusan.
Sistem pendidikan gagal mencetak pola pikir kritis, tersandera oleh pengajaran yang mendikotomi dan meredam pemikiran analitik.
Di ranah religius, otoritas fiqh meredup, berubah menjadi ritual tanpa etika pembangunan; sedangkan kesadaran sejarah masyarakat sering absen, terperangkap dalam narasi kalah yang dikapitalisasi sebagai nasib tak terelakkan.
Beban itu diperparah oleh sekte-sektarianisme dan etnisitas, naluri politik pragmatis yang merusak solidaritas, krisis media dan wacana politik-religius, serta warisan “Musim Semi Arab” yang menyisakan puing hubungan intra-Arab dan friksi baru.
Dampaknya: isu sentral — Palestina — dipinggirkan menjadi isu sekunder, sementara pembangunan terhenti dan negara-bangsa terkuras, represi menjadi perangkat kebijakan, dan oposisi gagal dewasa sehingga tak mampu menawarkan alternatif nyata.
Dalam skala lebih luas, krisis kepercayaan Arab makin mengakar. Dari luka Irak ke trauma Suriah, dari kecurigaan terhadap Iran dan Turki hingga sengketa perbatasan antarnegara, semua mendorong logika “tak satu pun berani mempertaruhkan punggungnya”. Logika itu berubah menjadi doktrin kemandekan.
Tambahkan pula fakta: beberapa rezim Arab membangun legitimasi dengan memusuhi gagasan “kesatuan” atau “nasional” yang lebih luas; gagasan tentang umat Arab atau Islam—yang menghimpun mayoritas penduduk Muslim dunia, banyak di antaranya miskin—dipersepsikan sebagai ancaman bagi kepentingan dan pengaruh rezim-rezim tersebut.
Maka lahirlah slogan memerangi “politik Islam” sebagai kambing hitam untuk menegaskan konsep “negara kesatuan” versus proyek ummah.
Sikap ini mempermudah permainan pembelahan dan melemahkan tenaga kolektif yang bisa menantang dominasi eksternal.
Semua itu memuluskan tugas Israel mengendalikan panggung regional: ia tinggal memanen perpecahan hingga rencananya matang, tanpa perlu kejeniusan luar biasa untuk menembus dari Maghrib ke Mashriq.
Jika mesti dirumuskan kembali cara berpikir politik kita—sebelum mengusulkan resepnya—maka itu dimulai dari tiga pengakuan dasar.
Pertama: kontradiksi utama kawasan ini bukanlah “politik Islam”, bukan pula perbedaan madzhab, ataupun surplus ideologi; melainkan proyek Zionis pengganti dan ekspansionis yang merancang dirinya atas dasar kekuatan dan pembentukan peta baru.
Kedua: AS bukan pihak netral, bukan mediator yang jujur, bukan penjamin; ia adalah pelindung organik proyek itu—selimut politik, keamanan, dan ekonomi bagi perluasan fungsinya—maka berharap pada payung Amerika agar tidak runtuh adalah ilusi strategis.
Ketiga: bersandar pada kesepakatan “Abrahamik” yang dipasarkan sebagai jalan pintas menuju perdamaian hanyalah rekayasa penyerahan yang timpang; ia menangguhkan substansi konflik tanpa menyelesaikannya.
Keluar dari pusaran ketidakberdayaan ini tidak dapat dilakukan hanya dengan kecaman moral atau rujukan pada hukum internasional yang sudah terkikis oleh pengecualian-pengecualian berulang.
Diperlukan respons sebanding dengan tantangan: terkoordinasi, politis, dan praktis. Di sinilah relevansi teori “tantangan dan respons” Arnold Toynbee—bangsa yang menghadapi ancaman besar dan mengalami ketidakseimbangan kekuatan akan kembali pada warisan peradabannya untuk menyalakan kapasitasnya menghadapi tantangan—menjadi rujukan.
Upaya kebangkitan itu harus membentuk matriks tandingan terhadap apa yang disimpulkan pemikir syahid Fathi Shiqaqi: segitiga tantangan yang harus dilawan adalah fragmentasi, ketergantungan, dan Israel.
Fragmentasi membuat tiap negara terisolasi menghadapi proyek Zionis; ketergantungan memenggal kapasitas pengambilan keputusan; sementara Israel memanen kedua kelemahan itu untuk melegitimasi fakta-fakta di lapangan.
Menghadapi tiga elemen ini butuh strategi yang nyata—rekonsiliasi politik-institusional, pembebasan kebijakan dari dominasi eksternal, dan pembangunan kapasitas kolektif yang membuat agresi menjadi mahal bagi pelakunya.
Respon strategis terhadap tantangan Zionisme hanya mungkin jika dibangun di atas segitiga kebalikan: persatuan fungsional, kemerdekaan politik, dan mobilisasi energi kolektif.
Persatuan di sini berarti menyingkirkan kontradiksi sekunder, sekaligus menggali kembali simpul-simpul historis dan peradaban bersama bangsa Arab dan Islam dalam menghadapi ancaman eksistensial.
Kemerdekaan berarti membebaskan keputusan politik dari ketergantungan eksternal, mengarahkan sumber daya untuk pembangunan manusia dan peradaban, serta menata ulang keseimbangan kekuatan.
Sedangkan mobilisasi berarti menyatukan potensi dalam sebuah proyek nyata yang berangkat dari inisiatif, bukan sekadar reaksi, terhadap proyek Zionis.
Dari sini muncul kesimpulan praktis: mustahil ada proyek kebangkitan tanpa pengakuan bahwa Zionisme adalah ancaman menyeluruh, bukan hanya bagi Palestina. Bahaya itu menyasar kawasan sebagai satu kesatuan historis, kultural, dan politik.
Israel bukan sekadar “tentara kuat”, melainkan proyek lintas-batas yang merekayasa ulang lanskap regional, memanfaatkan perpecahan internal, dan mendefinisikan ulang batas serta makna kawasan setiap kali tersedia celah.
Seperti halnya sebuah negara tidak bisa membangun kewarganegaraan tanpa narasi pemersatu, kawasan pun tidak mungkin membangun proyek regional tanpa menerima adanya “umat Arab” dalam makna kultural-historis yang luas—yang di dalamnya juga terhubung Turki dan Iran melalui geografi, agama, sejarah, dan budaya.
Tanpa pengakuan terhadap benang merah bersama ini, negara-negara hanya akan menjadi pulau-pulau terpisah yang dikonsumsi oleh kontradiksi lokal, sementara orang lainlah yang menggambar peta masa depan.
Agar proyek kebangkitan tidak berhenti sebagai retorika, dibutuhkan revolusi kesadaran di dalam setiap negara: dalam pendidikan, riset, media, wacana agama dan politik.
Semua itu mesti berangkat dari pengakuan terhadap ancaman eksistensial Zionisme. Masyarakat dan negara perlu mengonsentrasikan sumber daya untuk menantangnya: memberdayakan generasi muda, memperbarui kontrak sosial, dan menghubungkan legitimasi dengan kapasitas untuk membela kepentingan rakyat.
Rezim yang gagal menghadapi ancaman eksistensial—dan tidak mencerminkan aspirasi rakyatnya—akan kehilangan legitimasi dan rapuh di hadapan ujian apa pun.
Tidak mungkin rezim yang menindas rakyat di dalam negeri berharap menang melawan musuh di luar. Otoritarianisme dan korupsi justru sekutu paling efektif bagi proyek yang dihadapi kawasan.
Begitu pula dengan sektarianisme, kesukuan, dan primordialisme: ia adalah bom waktu bila minoritas tidak dijamin hak-haknya.
Negara adil yang menjadikan keberagaman sebagai sumber kekuatan hanya bisa dibangun dengan membuka ruang politik, menghubungkan legitimasi dengan kotak suara, serta mengukur kinerja pelayanan publik.
Di level regional, tidak cukup meratapi tumpulnya Liga Arab atau Organisasi Kerja Sama Islam. Keduanya perlu direstrukturisasi total agar bertransformasi dari forum simbolik menjadi wadah pengambilan keputusan yang mengikat.
Perjanjian Pertahanan Arab Bersama harus dihidupkan kembali, bahkan diperluas untuk melibatkan Turki, Iran, dan Pakistan.
Keraguan dalam hal militer juga harus diakhiri. Siapa yang ingin menghindari perang, harus bersiap untuknya; siapa yang mendambakan perdamaian, harus membangun kapasitas penangkal.
Yang dibutuhkan adalah doktrin pertahanan regional yang rasional, menempatkan keamanan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan urusan nasional sempit.
Doktrin itu harus menetapkan aturan keterlibatan yang jelas, memperluas sumber persenjataan agar tidak tergantung pada satu pusat eksternal, mengembangkan industri pertahanan lokal dengan tata kelola sipil yang transparan, dan mengaitkan belanja militer dengan target yang terukur.
Dalam horizon geopolitik global, kawasan tidak bisa selamanya menjadi panggung perebutan blok-blok besar dunia.
Pilihan bukan tunduk ke Barat atau ke Timur, melainkan menjadi blok historis, politik, ekonomi, dan militer yang berdiri sendiri.
Arab, Turki, dan Iran memiliki energi, jalur laut, pasar luas, dan populasi muda yang dinamis—semua bahan baku bagi kekuatan mandiri.
Itu menuntut lompatan dalam pendidikan, riset, dan lembaga pemikir yang menyusun kebijakan.
Dibutuhkan pembangunan koridor bea bersama, pasar energi regional, dana kedaulatan untuk pembangunan lintas batas, dan dewan teknologi yang menumbuhkan kemandirian pengetahuan.
Sejarah menunjukkan transformasi itu bukan mustahil. Uni Eropa lahir dari reruntuhan Perang Dunia Kedua, bangkit dengan semangat mengatasi trauma Nazi. Cina keluar dari “abad penghinaan” dan menjelma pemain global tak terelakkan.
Kawasan ini bukan salinan dari keduanya, tetapi juga bukan pengecualian dari hukum sejarah.
Seperti dikatakan Malik Bennabi, kebangkitan membutuhkan manusia, tanah, waktu—dan sebuah ide yang menggerakkan.
Ide itu hanya bisa berubah menjadi peradaban bila dipikul oleh umat yang percaya bahwa kebangkitan bukan pilihan yang bisa ditunda, melainkan satu-satunya jalan untuk bertahan hidup.
Namun semua itu tidak akan berjalan bila sebagian negara Arab dan Islam tetap ngotot mempertahankan hubungan diplomatik, komersial, ekonomi, keamanan, atau militer dengan rezim Israel—atau dengan korporasi yang mendukungnya.
Matriks tantangan-dan-respons tidak akan lengkap tanpa mengembalikan pengakuan atas perlawanan sebagai gerakan pembebasan nasional yang dijamin haknya menurut hukum alam, hukum internasional, dan kemanusiaan; hak untuk menentang dan menghadapi pendudukan.
Pengakuan itu mesti disertai dukungan terang-terangan, tanpa ragu atau malu, karena perlawanan adalah garis pertahanan pertama bagi kedalaman Arab-Islam dan bagian dari persamaan penangkalan yang lebih luas—bukan sekadar fenomena lokal yang patut didemonisasi.
Semua pengakuan ini perlu dipadukan dengan piagam aturan-aturan bertempur yang tegas untuk melindungi warga sipil secara mutlak.
Di samping itu, saat merumuskan proyek ini, kita tidak boleh alpa menyasar opini publik global. Kesadaran dunia yang tumbuh tentang Palestina adalah peluang yang harus diraih dengan kecerdikan.
Kemarahan rakyat di ibu kota-ibu kota Barat, meningkatnya suara-suara Yahudi yang mengkritik Zionisme, dan retak-nya citra “keunggulan moral” dalam media arus utama—semua itu memberi ruang bagi terciptanya koalisi internasional yang lebih luas.
Bukan berarti kita menggantungkan nasib pada pihak lain; maksudnya adalah menghadirkan kasus kita ke panggung dunia dengan argumen hukum dan etika yang gamblang, dengan narasi politik yang rasional—yang tak mengorbankan hak-hak mendasar dan tak membenarkan yang tak dapat dibenarkan.
Kita harus mengembalikan wajah dan nama korban ke dokumen, cerita, dan ruang publik; mengasah cara berbicara pada pergerakan mahasiswa Barat, pada Yahudi-Yahudi kritis terhadap Zionisme, dan bahkan pada “evangelical Zionists” di AS—dengan argumentasi yang menunjukkan biaya dukungan itu terhadap kepentingan Amerika sendiri.
Harus ada jembatan-jembatan cerdas dengan kelompok-kelompok sosial dan ekonomi yang tidak meyakini doktrin keagamaan politik itu, tetapi telah terhisap narasi media yang mendukungnya.
Ada yang berpendapat: ini semua adalah idealisme besar di hadapan kenyataan keras. Benar—namun alternatifnya adalah keheningan yang melegalkan kehancuran. Kita berada di saat penentuan: memperbaiki akal politik dan menyembuhkan retakan di dalam negeri, atau membiarkan proyek Zionis menyelesaikan arsitektur pemecahan.
Kita pernah mencoba sikap netral, bertaruh pada pihak luar, dan berinvestasi pada perpecahan—semua itu membawa kita ke titik ini.
Peluang belum musnah, tetapi waktu semakin sempit. Pengalaman Gaza membuktikan bahwa tunduk bukanlah nasib; meskipun ada jurang dalam neraca kekuatan, perlawanan mampu mengejutkan Israel dan membuka celah-celah struktural dalam masyarakat, militer, dan mesin keamanannya.
Sayangnya, ketiadaan dukungan regional yang efektif mengubah kemenangan parsial menjadi pengurasan lama, memberi Israel waktu tambahan untuk menyelesaikan tujuannya.
Israel memang menikmati momen superioritas historis, tetapi juga menghadapi momen keterbukaan moral yang belum pernah ada sejak pendiriannya. Struktur kekuatan yang dimilikinya tidak akan melindungi dari erosi lambat jika dihadapkan pada lingkungan Arab yang utuh secara internal, kooperatif secara regional, dan cerdik dalam kelola hubungan globalnya.
Pelajaran yang kita peroleh sudah cukup untuk memulai perpindahan dari mengelola kekalahan ke mengelola transformasi. Jika tidak, kita justru memberi proyek Zionis waktu yang dibutuhkannya—dan mempertaruhkan pewarisan kekalahan kepada generasi yang akan datang.
Tidak ada yang lebih pahit bagi sejarah daripada sebuah bangsa yang mengetahuinya namun tidak bertindak. Saat ujian datang, bangsa yang menukar pengetahuan menjadi keputusan, kehendak, dan langkah-langkah terukur akan menegaskan: akhirnya, kita mulai mengetuk dinding tangki.
*Saifuddin Mawed adalah seorang penulis dan jurnalis Palestina. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Al-Quwwah al-Waḥīdah al-Qādirah ‘Alā Muwājaḥah Isrāīl”.