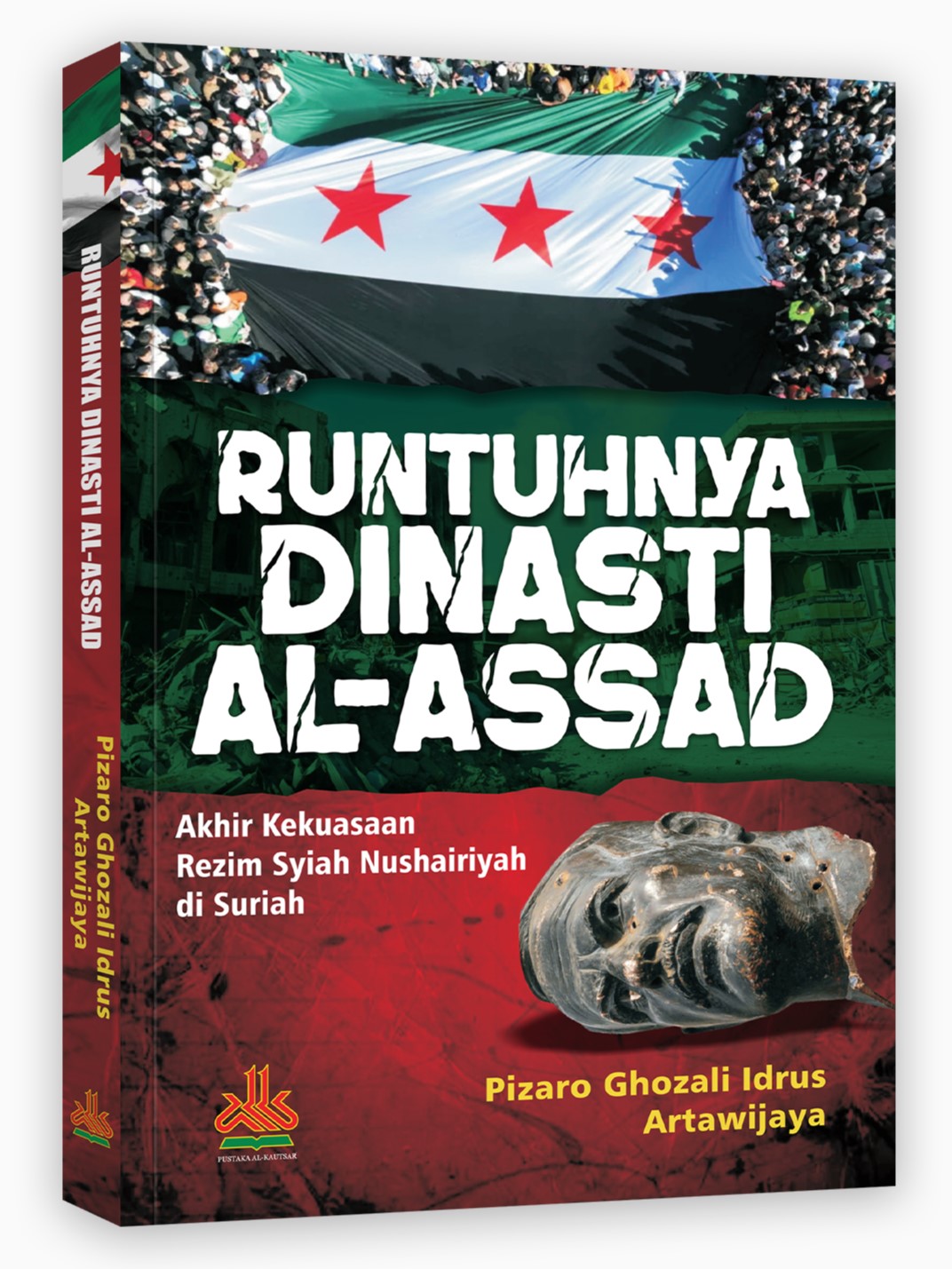Oleh: Dr. Mohammed Ghaly*
Dalam lintasan sejarah Islam, kerap kali muncul kisah tentang individu-individu yang berdiri tegak menantang kekuasaan demi prinsip moral dan keyakinan mereka.
Salah satunya adalah peristiwa antara Ibrahim bin Maimun, yang dikenal sebagai Tukang Emas dari Merv, dan Abu Muslim al-Khurasani, tokoh penting di balik lahirnya Dinasti Abbasiyah.
Kisah ini, meskipun terjadi lebih dari 13 abad lalu, tampaknya memiliki gema yang tak jauh berbeda dengan yang dialami seorang insinyur muda asal Maroko, Ibtihal Abu Saad, dalam menghadapi salah satu raksasa teknologi dunia, Microsoft.
Keteguhan hati tukang emas dari Merv
Ibrahim bin Maimun dikenal sebagai pribadi saleh dan taat beragama. Diceritakan bahwa setiap kali mendengar azan, ia akan langsung meletakkan alat kerjanya dan segera melaksanakan salat.
Pada awalnya, ia termasuk di antara para pendukung Abu Muslim al-Khurasani, tokoh revolusioner yang memainkan peran besar dalam menggulingkan kekuasaan Umayyah.
Abu Muslim berjanji akan menegakkan keadilan. Namun, begitu kekuasaan berada di tangannya, janji tinggal janji. Ia justru dikenal dengan kebijakan represif dan kekerasan berdarah yang menewaskan banyak orang.
Ibrahim, yang kecewa atas pengingkaran janji itu, berulang kali mengingatkannya. Namun ia justru diabaikan, hingga akhirnya ia memilih jalan konfrontasi terbuka.
Dalam satu pertemuan publik, Ibrahim datang dengan kafan dan wewangian jenazah, tanda bahwa ia siap mati.
Ia menegur Abu Muslim secara langsung dan keras. Hasilnya tragis: ia dihukum mati di tempat. Tapi namanya tetap dikenang sebagai simbol keberanian moral.
Ibtihal Abu Saad: Suara nurani dari dunia teknologi
Lompatan ke abad ke-21, kita menyaksikan cerita yang tak kalah menggugah datang dari dunia yang sangat berbeda—dunia teknologi dan kecerdasan buatan.
Ibtihal Abu Saad, insinyur dan programmer muda asal Maroko, bergabung dengan Microsoft pada tahun 2022, setelah menyelesaikan studinya di Universitas Harvard dengan beasiswa penuh.
Sejak muda, Ibtihal dikenal memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai sosial. Ia aktif dalam proyek literasi digital, membantu komunitas termarjinalkan, dan bahkan ikut mengembangkan platform untuk pencatatan medis digital bagi para pengungsi.
Di awal kariernya di Microsoft, ia melihat perusahaan ini sebagai sarana untuk mewujudkan idealismenya: menggunakan teknologi demi kebaikan (technology for social good). Namun, seiring waktu, harapan itu memudar.
Microsoft diketahui terlibat dalam proyek-proyek militer, termasuk kolaborasi dengan Departemen Pertahanan AS dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk keperluan tempur.
Momen konfrontasi yang menggema
Puncak ketidakpuasan Ibtihal terjadi dalam perayaan 50 tahun Microsoft. Dalam acara yang dihadiri para tokoh besar Perusahaan.
Termasuk Bill Gates dan Mustafa Suleyman (kepala divisi AI Microsoft), Ibtihal mendadak naik ke atas panggung dan berseru lantang.
“Mustafa, sungguh memalukan!” serunya.
Ia menuding Microsoft sebagai bagian dari sistem yang mendukung kekerasan terhadap warga sipil di Gaza.
“Lima puluh ribu orang telah tewas, dan Microsoft menyuplai teknologi pembunuh ini!” katanya.
Ia melemparkan syal Palestina ke atas panggung—simbol solidaritas yang kuat.
Aksi itu terekam dan viral di media sosial. Banyak yang memuji keberaniannya. Tak sedikit pula yang menyebutnya sebagai “suara hati nurani” di tengah dunia teknologi yang kerap diselimuti kabut kepentingan.
Sejarah yang berulang: Prinsip vs kekuasaan
Dua cerita yang terpisah ribuan tahun dan dunia yang berbeda ini menunjukkan benang merah yang serupa: bagaimana individu yang berpegang teguh pada nilai moral kerap kali berhadapan langsung dengan struktur kekuasaan yang besar.
Baik Ibrahim bin Maimun maupun Ibtihal Abu Saad, keduanya tidak hanya menyuarakan protes, tapi juga menanggung risiko nyata atas keberanian mereka.
Seperti kata Imam Syafi’i, “Siapa yang membaca sejarah, akan bertambah akalnya.”
Dalam menapaki zaman yang semakin kompleks, barangkali kita memang perlu lebih sering menoleh ke belakang—untuk mengambil hikmah, dan melangkah ke depan dengan lebih bijak.
Di bawah permukaan gunung es: Tantangan etika di era kecerdasan buatan
Aksi Ibtihal Abu Saad di perayaan 50 tahun Microsoft tak bisa dianggap sebagai insiden spontan atau sekadar reaksi emosional sesaat.
Ia juga bukan sekadar bentuk solidaritas terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza—meskipun kekerasan yang disiarkan langsung dari sana telah melampaui batas daya tahan banyak orang untuk menonton, apalagi untuk diam.
Yang diperlihatkan Ibtihal adalah cerminan dari kegelisahan moral yang lebih dalam. Sebuah kegelisahan yang juga dirasakan oleh sejumlah tokoh dan pakar dalam bidang teknologi, yang menyoroti dominasi kekuasaan baru dalam dunia modern. Kekuasaan raksasa teknologi dan pengaruh mereka yang kian meluas melalui kecerdasan buatan (AI).
Kini, AI tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam keseharian, tapi juga memengaruhi kebijakan negara, keputusan bisnis, bahkan urusan perang dan perdamaian.
Suara-suara yang memilih mundur demi prinsip
Ibtihal bukan satu-satunya sosok yang memilih bersuara, bahkan ketika itu berarti menghadapi konsekuensi serius dalam karier.
Di daftar yang sama, nama Geoffrey Hinton menjadi sorotan. Ilmuwan komputer asal Inggris yang dijuluki “Bapak AI” ini memilih mengundurkan diri dari Google pada tahun 2023 agar bisa bicara lebih bebas tentang bahaya kecerdasan buatan.
Ia kemudian menjadi kritikus terbuka terhadap tokoh-tokoh industri seperti Sam Altman (CEO OpenAI) dan Elon Musk.
Hinton bahkan dianugerahi Nobel pada tahun 2024, tidak semata karena pencapaiannya dalam pengembangan teknologi, tapi juga karena keberaniannya mengingatkan dunia akan risiko besar yang mengintai.
Kisah serupa datang dari Timnit Gebru, salah satu ahli etika AI terkemuka yang juga hengkang dari Google pada tahun 2020.
Gebru sempat memimpin tim etika AI di perusahaan tersebut, sebelum akhirnya diberhentikan setelah menulis makalah ilmiah yang mengkritisi potensi bahaya dari large language models (LLMs)—teknologi dasar di balik chatbot seperti ChatGPT.
Dalam narasi resmi, Google menyebut Gebru telah “mengundurkan diri.” Namun Gebru menegaskan bahwa ia hanya menyatakan niat untuk mundur jika tuntutannya tidak dipenuhi—dan belum benar-benar melayangkan pengunduran diri secara resmi.
Etika perang dan teknologi: Pertanyaan yang belum terjawab
Salah satu aspek paling kontroversial dalam penggunaan AI adalah keterlibatannya dalam industri militer. Bukan hanya karena potensi penyalahgunaan, tetapi karena pertanyaan mendasar: haruskah AI digunakan dalam konteks membunuh?
Jawaban dari ribuan pegawai Google pada 2018 adalah tegas: tidak. Lebih dari 3.100 karyawan, termasuk para insinyur senior, menandatangani petisi internal menolak partisipasi perusahaan dalam “Project Maven” milik Pentagon, proyek yang mengandalkan AI untuk menganalisis citra udara dan meningkatkan akurasi serangan drone.
“Kami percaya Google tidak seharusnya terlibat dalam bisnis peperangan,” tulis mereka dalam surat kepada CEO.
Mereka juga menuntut perusahaan mengadopsi kebijakan eksplisit untuk tidak mengembangkan teknologi militer di masa depan. Surat ini mengingatkan pada moto etis lama perusahaan itu: Don’t be evil.
Akibat tekanan publik dan internal yang kian menguat, Google akhirnya mengumumkan tidak akan memperpanjang kontraknya dalam proyek tersebut.
Refleksi: Keberanian di tengah sistem
Apa yang dilakukan Ibtihal, Hinton, Gebru, dan ribuan lainnya bukanlah tindakan mudah. Mereka menantang arus besar industri yang digerakkan oleh keuntungan, efisiensi, dan kekuasaan.
Namun, di tengah gelombang tersebut, suara-suara yang menyerukan etika, transparansi, dan tanggung jawab tetap muncul—kadang sunyi, tapi menggema jauh.
Kita hidup di zaman ketika keputusan teknologi dapat menentukan hidup dan mati, damai atau perang. Di tengah semua itu, pertanyaan etis bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak.
Dan mungkin, seperti yang ditunjukkan oleh kisah-kisah ini, masih ada ruang bagi nurani dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh kode dan algoritma.
Ketika Abu Muslim bernama Microsoft
Sulit memahami pengaruh besar yang dimiliki Abu Muslim al-Khurasani tanpa menempatkannya dalam konteks perubahan besar yang mengguncang dunia Islam pada abad ke-8: dari keruntuhan Bani Umayyah menuju kebangkitan Bani Abbasiyah.
Abu Muslim bukan hanya seorang jenderal—ia adalah arsitek kekuasaan, pengatur arah sejarah, hingga pengaruhnya diyakini melampaui kekuasaan khalifah itu sendiri.
Dalam salah satu suratnya, Abu Ja’far Al-Mansur, sang adik dan kelak menjadi khalifah, memperingatkan saudaranya tentang dominasi Abu Muslim.
Tapi sang khalifah saat itu menolak mengambil tindakan, karena menyadari bahwa negara yang baru berdiri masih sangat membutuhkan kekuatan militer dan pengaruh politik sang jenderal.
Kini, kita berada dalam babak sejarah yang lain, tapi dengan pola yang mirip. Dunia tengah bergeser dari kekuasaan negara ke dominasi korporasi teknologi.
Pemerintah, bahkan negara, seolah tak bisa hidup tanpa Microsoft dan para sekutunya, baik di masa damai maupun konflik.
Sejumlah pemikir dan politisi mulai menyuarakan keprihatinan mereka akan fenomena ini. Salah satunya adalah Elizabeth Warren, senator AS yang dalam kampanyenya untuk pemilu presiden 2019 secara terang-terangan menyerukan pembongkaran struktur kekuasaan raksasa teknologi. Dalam iklan kampanyenya, terpampang jelas slogan: “Break up Big Tech”.
Pelajaran dari seorang tukang emas
Sejarah juga mencatat nasib tragis seorang tukang emas dari kota Merv yang berani menegur Abu Muslim atas kekejamannya.
Ia dibunuh, tetapi keberaniannya tetap dikenang. Kuburannya menjadi tempat ziarah, dan kisahnya menjadi simbol moral keberanian menegakkan kebenaran.
Menariknya, setelah Abu Ja’far Al-Mansur naik takhta, ia sendiri yang akhirnya menyingkirkan Abu Muslim—sebuah babak simbolik dari negara yang merebut kembali kekuasaannya dari tangan sosok non-negara.
Kisah ini kembali terasa relevan dalam konteks masa kini. Ibtihal Abu Saad, insinyur Microsoft yang baru-baru ini mencuri perhatian publik karena sikap moralnya, tidak mengalami nasib tragis seperti tukang emas dari Merv—ia masih hidup dan menyuarakan pendapatnya melalui media sosial.
Namun, ia kehilangan pekerjaannya. Hanya beberapa hari setelah insiden yang ia lakukan, Microsoft memecatnya dengan alasan pelanggaran serius, pembangkangan, dan kelalaian tugas.
Jangan biarkan mereka berdiri sendiri
Pelajaran moral dari kisah ini adalah pentingnya solidaritas. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton yang bertepuk tangan dari jauh kepada para pahlawan moral seperti Ibtihal, lalu melupakannya dalam hitungan minggu.
Dalam satu riwayat, tukang emas dari Merv sempat berdiskusi dengan Imam Abu Hanifah tentang kewajiban amar makruf nahi mungkar.
Imam besar itu memperingatkannya bahwa menegur kekuasaan bukanlah tugas individual, melainkan tugas kolektif. Jika dilakukan sendiri, itu sama saja menantang kematian.
Begitu pula hari ini. Kita tidak bisa membiarkan Ibtihal dan rekan-rekannya menjadi korban dalam pertarungan yang semestinya menjadi urusan kita bersama.
Sudah semestinya para ilmuwan, etikus, dan insinyur bersatu menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan etika terhadap perusahaan-perusahaan yang menguasai teknologi global.
Negara-negara Arab dan Muslim, yang menggelontorkan miliaran dolar untuk membeli perangkat dan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan teknologi ini, juga tidak bisa terus diam.
Mereka seharusnya berdiri bersama para insinyur dan karyawan yang berdiri membela prinsip.
Teknologi dan kecerdasan buatan tentu bukan sesuatu yang jahat pada dasarnya. Tapi tanpa pengawasan nilai, kekuatan itu bisa berubah menjadi ancaman.
Dan satu-satunya cara untuk memastikan bahwa teknologi bekerja untuk manusia—bukan sebaliknya—adalah dengan memastikan adanya kontrol, partisipasi, dan keberanian moral dari banyak pihak.
Akankah Abu Muslim tunduk?
Pertanyaan besarnya kini adalah: akankah “tukang emas” zaman ini—seperti Ibtihal dan koleganya—berhasil menjinakkan Abu Muslim yang kini bernama Microsoft, Google, atau Amazon?
Ataukah nasib mereka akan seperti leluhurnya di Merv, ditumbalkan demi stabilitas sesaat? Dan apakah dunia akan membiarkan perusahaan-perusahaan teknologi terus mengambil alih peran negara, sampai kekuasaan tak lagi berada di tangan rakyat, tapi di balik layar server dan algoritma?
Atau, mungkinkah sejarah berulang? Bahwa seperti Abu Ja’far yang akhirnya mengambil kembali kendali dari Abu Muslim, politisi seperti Elizabeth Warren dan para pemimpin masa depan akan berhasil melakukan koreksi besar terhadap arah dominasi teknologi?
Allah Swt. telah menegaskan dalam kitab-Nya:
“Katakanlah, ya Allah, Pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Ali Imran: 26)
*Dr. Mohammed Ghaly adalah Profesor Islam dan Etika Biomedis di Pusat Penelitian Legislasi & Etika Islam (CILE) di CIS. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Ibn Maimūn wa Ibtihāl Abū al-Sa’ad: Ḥikāyatān Fī Muwājahah Saltah Wāḥidah”.