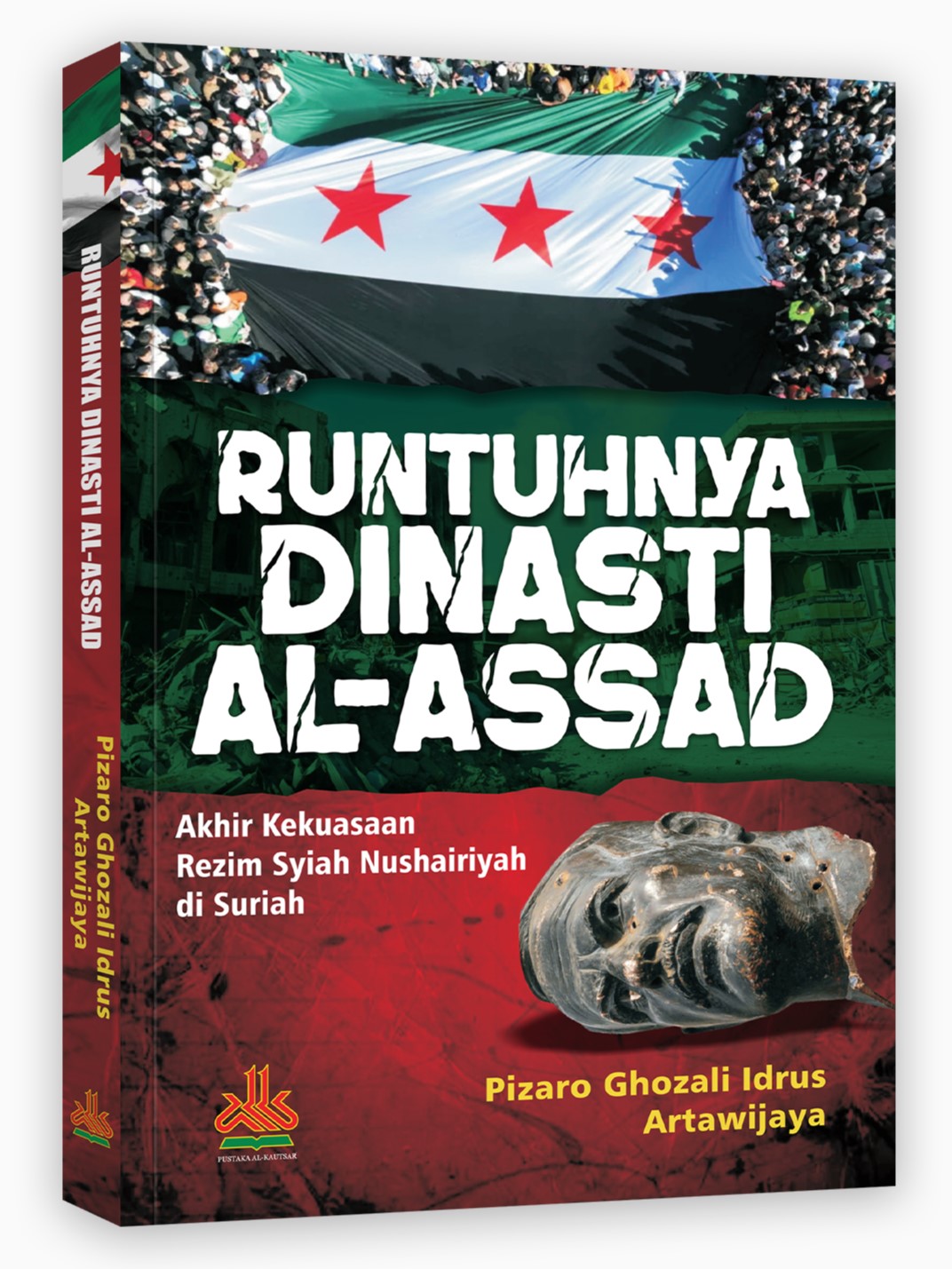Telah berulang kali publik Israel mendengar istilah “peristiwa keamanan sulit di Gaza”. Namun, apa sebenarnya yang tersembunyi di balik ungkapan itu?
Media Israel melaporkan tewasnya sejumlah tentaranya, dengan 11 lainnya luka parah, serta hilangnya empat prajurit yang dikhawatirkan jatuh sebagai tawanan di tangan kelompok perlawanan Palestina.
Peristiwa ini digambarkan sebagai insiden paling besar sejak serangan “Thaufan Al-Aqsha” pada 7 Oktober 2023.
Serangkaian operasi perlawanan terjadi di dua kawasan padat penduduk, yakni Hayy az-Zaytun dan Hayy as-Sabra, Kota Gaza.
Media Israel menyebut, sebuah serangan mendadak berupa penyergapan mematikan telah menewaskan sejumlah tentara Israel.
Situasi kian rumit karena militer Israel terpaksa mengaktifkan apa yang disebut Protokol Hannibal, yakni prosedur kontroversial yang memungkinkan tentaranya sendiri ditembak untuk mencegah mereka ditawan.
Helikopter yang ditugaskan mengevakuasi korban juga dikabarkan mendapat tembakan gencar dari pasukan perlawanan.
Menurut laporan, korban sebagian besar berasal dari Divisi 162 dan Brigade 401, yang terjebak dalam penyergapan di kawasan timur Gaza.
Menyusul insiden itu, tentara Israel ditarik mundur dari Hayy az-Zaytun dan dikembalikan ke pangkalan. Sementara itu, lembaga sensor militer Israel memberlakukan larangan publikasi mengenai nasib empat tentara yang hilang.
Pernyataan resmi dari militer hanya menyebutkan adanya “pencarian intensif” terhadap para prajurit tersebut.
Namun, media Israel mengaitkan insiden ini dengan peringatan Abu Ubaida, juru bicara sayap militer Hamas, yang sebelumnya menegaskan bahwa Israel akan membayar harga mahal jika berusaha menyerbu Kota Gaza.
Pola operasi perlawanan
Dalam beberapa pekan terakhir, operasi kelompok perlawanan Palestina memang meningkat tajam, dengan kerugian besar di pihak militer Israel. Ungkapan “peristiwa keamanan sulit di Gaza” pun semakin sering terdengar.
Kunci strategi perlawanan tampaknya bertumpu pada penggunaan penyergapan (ambush) yang dirancang secara kompleks.
Dalam literatur militer, penyergapan dipahami sebagai operasi ofensif terencana, dilakukan oleh kelompok kecil bersenjata, terhadap sasaran yang bergerak atau berada dalam posisi rentan.
Meski kerap tampak spontan, kenyataannya setiap operasi perlawanan di Gaza dirancang dengan perhitungan matang.
Dibutuhkan intelijen lapangan yang kuat untuk melacak pola pergerakan musuh, mengenali titik lemahnya, serta memanfaatkan kondisi geografis yang sudah akrab bagi warga setempat.
Keunggulan “mengenali medan” menjadi aset penting. Jalur sempit, reruntuhan bangunan, hingga lorong-lorong kota dimanfaatkan untuk menjerumuskan pasukan Israel ke area “zona maut” yang sudah dipersiapkan.
Prosesnya berlapis. Dari intelijen lapangan, komandan unit perlawanan memperoleh data detail tentang jumlah prajurit lawan, peralatan yang mereka bawa, jalur patroli, hingga pola rotasi mereka.
Jalur pergerakan tentara kemudian dibagi menjadi sejumlah titik yang menjadi lokasi potensial penyergapan.
Di titik itu, pejuang Palestina menyiapkan jebakan: mulai dari bahan peledak untuk menghentikan laju kendaraan, senapan serbu untuk serangan jarak dekat, hingga roket antitank “Yasin” untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja.
Serangan pun tidak dilakukan dari satu arah saja, melainkan dari beberapa sudut serangan yang mematikan.
Yang tak kalah penting, para pejuang juga merancang jalur evakuasi. Setelah serangan dilancarkan, mereka segera menghilang ke jaringan lorong bawah tanah atau bangunan terlindung, menyelamatkan diri sekaligus mengamankan senjata yang digunakan.
Beberapa analis militer menilai, intensifikasi operasi bersenjata ini tak lepas dari kalkulasi politik.
Kelompok perlawanan Palestina ingin meningkatkan tekanan terhadap Israel, khususnya di saat berlangsungnya negosiasi soal gencatan senjata.
Israel berharap gempuran udara harian, penghancuran infrastruktur, serta krisis kemanusiaan di Gaza—kelaparan massal, ketiadaan layanan kesehatan, dan runtuhnya jaringan air serta listrik—akan membuat kelompok perlawanan luluh dan menerima kompromi besar.
Namun, rangkaian penyergapan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya: kelompok perlawanan justru memanfaatkan momentum itu untuk menegaskan daya tawar.
Senjata murah, tetapi efektif
Bagi pengamat yang mengikuti dinamika perang di Gaza, penting dipahami bahwa tidaklah tepat membandingkan senjata secara sederhana: satu lawan satu, atau satu angkatan melawan angkatan lainnya.
Senjata selalu harus ditempatkan dalam konteks fungsinya di medan operasi, sekaligus dalam lanskap politik yang lebih luas.
Dalam buku klasiknya, Pengantar Strategi, Jenderal André Beaufre—perwira tinggi militer Prancis yang pensiun pada 1961—menyebut bahwa seni strategi pada hakikatnya adalah memilih sarana terbaik yang tersedia.
Selain itu, juga mengombinasikannya untuk menghasilkan tekanan psikologis yang cukup dalam mencapai dampak yang diinginkan.
Kalimat itu menemukan relevansinya di Gaza hari ini. Di sana, pihak yang lemah dalam hal persenjataan konvensional justru mampu menggunakan senjata sederhana—murah, bahkan kerap rakitan—untuk menimbulkan kerugian besar pada lawan yang jauh lebih unggul secara teknologi.
Dalam berbagai penyergapan, sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin al-Qassam, kerap mengandalkan alat peledak improvisasi (improvised explosive devices atau IED).
Bahan peledak ini biasanya dirakit secara lokal, menggunakan campuran bahan sederhana—mulai dari amunisi bekas, mortir, hingga pupuk pertanian yang dipadukan dengan TNT.
Fleksibilitasnya menjadikan IED efektif dipasang di tepi jalan untuk menghadang konvoi militer, disembunyikan di pintu masuk bangunan untuk menyerang regu tentara, bahkan ditempelkan langsung ke kendaraan lapis baja. Dengan kreativitas tinggi, bom rakitan itu juga bisa dijatuhkan dari drone.
Sistem pemicunya pun bervariasi. Ada yang sederhana, menggunakan tombol tekan layaknya ranjau darat. Ada pula yang canggih, diaktifkan dari jauh melalui sinyal radio.
Bahkan dalam sejumlah kasus, pejuang Palestina menempelkan bahan peledak langsung ke dinding tank atau kendaraan musuh.
Dalam perkembangan terbaru, Hamas memperkenalkan versi lebih canggih: explosively formed penetrator (EFP), yang mereka sebut “Shuwaz”.
Berbentuk logam cekung dari baja atau tembaga, EFP mampu memfokuskan energi ledakan sehingga menciptakan semburan logam cair berkecepatan ribuan meter per detik—mampu menembus lapisan baja terkuat sekalipun.
Senjata serupa pernah membuat kendaraan tempur Amerika, termasuk tank Abrams, kewalahan dalam invasi ke Irak.
Selain bom rakitan, perlawanan di Gaza juga memproduksi roket antitank lokal, yang dikenal sebagai “Yasin” berkaliber 105 mm.
Senjata ini memiliki hulu ledak ganda (tandem warhead). Ledakan pertama dirancang untuk memicu “armor reaktif”—lapisan pelindung yang meledak ke luar demi meredam serangan.
Setelah itu, hulu ledak kedua masuk dan melubangi lapisan baja utama, menimbulkan kerusakan fatal di dalam kendaraan tempur.
Keunggulan Yasin terletak pada tiga hal: murah, mudah digunakan, dan diproduksi secara lokal sehingga bisa dipasok dalam jumlah banyak. Satu prajurit cukup berlatih singkat untuk bisa mengoperasikannya di medan tempur.
Tiga titik lemah tank Israel
Namun, senjata hanyalah separuh cerita. Yang menentukan adalah bagaimana ia dipakai. Video-video yang dirilis Hamas memperlihatkan pola serangan terhadap tank Israel, terutama Merkava, di tiga titik lemah:
- Mesin di bagian depan: serangan di titik ini melumpuhkan tank sekaligus berpotensi menewaskan komandan tank yang duduk di dekat mesin.
- Bagian buritan: pintu keluar kru dan ruang penyimpanan amunisi, yang jika terkena serangan, menonaktifkan kekuatan tank.
- Sambungan antara menara dan badan tank: area vital yang relatif rentan meski tank dilengkapi perlindungan berlapis.
Foto-foto tank Merkava yang hancur, tersebar di media sosial, menunjukkan pola kerusakan pada tiga titik ini.
Padahal, Merkava bukan kendaraan tempur sembarangan. Tank itu didukung pengintaian drone, analisis berbasis kecerdasan buatan, hingga formasi tempur berlapis yang dirancang untuk menutup segala sisi.
Fakta bahwa tank ini bisa dihantam berkali-kali justru menunjukkan adanya koordinasi perlawanan yang semakin matang.
Dari intelijen lapangan, perencanaan taktis, distribusi target, hingga eksekusi oleh unit tempur kecil, semua berjalan dalam sinkronisasi yang rapi.
Inilah alasan mengapa senjata yang relatif murah, ketika dipadukan dengan strategi jitu dan keberanian tempur, bisa mengimbangi bahkan melumpuhkan teknologi perang tercanggih di dunia.
Perang non-konvensional
Pertanyaan penting yang kerap muncul adalah: bagaimana mungkin Brigade al-Qassam, yang jumlah pasukannya tidak lebih dari 5 persen kekuatan militer Israel, tanpa tank dan pesawat tempur, serta dengan persenjataan yang jauh lebih sedikit, mampu bertahan begitu lama menghadapi kampanye militer besar-besaran?
Salah satu jawabannya terletak pada apa yang disebut “strategi tidak langsung”.
Dua peneliti dari Universitas Pertahanan Nasional Swedia, Gunilla Eriksson dan Ulrika Pettersson, dalam bukunya Operasi Khusus dari Perspektif Kekuatan Kecil, menjelaskan bahwa strategi tidak langsung dirancang untuk memberi ruang gerak maksimal bagi pihak yang lebih kecil.
Dan juga, sambil membatasi kebebasan pihak yang lebih besar. Pembatasan itu bisa berupa kekuatan material, moral, hingga faktor waktu.
Salah satu metode efektif dalam kerangka ini adalah “strategi pengikisan”. Tujuannya bukan meraih kemenangan militer yang mutlak, melainkan membuat konflik menjadi amat mahal bagi pihak lawan—secara militer, ekonomi, sekaligus politik.
Dalam kerangka itu, perang tak bisa hanya mengandalkan sikap bertahan. Ia mesti memadukan pertahanan (untuk menahan laju musuh) dengan serangan terbatas (untuk menciptakan efek psikologis dan supremasi moral).
Caranya adalah lewat mobilitas tinggi, serangan mendadak, dan penguasaan momentum.
Inilah yang secara luas dikenal sebagai “perang non-konvensional” (irregular warfare).
Berbeda dengan perang konvensional yang mengandalkan pasukan besar, tank, dan jet tempur, perang non-konvensional bertumpu pada unit-unit kecil, fleksibel, yang menyerang dengan taktik gerilya.
Tujuannya bukan menaklukkan lawan di medan terbuka, melainkan melemahkan perlahan, memecah konsentrasi, dan menimbulkan kerugian mendadak.
Penyergapan (ambush) adalah salah satu instrumen kunci. Serangan dilakukan secara tiba-tiba terhadap konvoi atau patroli militer, lalu pasukan perlawanan segera mundur dengan cepat.
Efektivitasnya diperkuat oleh kondisi alam: gang-gang kota, reruntuhan bangunan, hingga jaringan terowongan.
Selain itu, perlawanan juga menggunakan operasi psikologis—serangan yang muncul tak terduga di lokasi yang dianggap aman, menciptakan ketakutan mendalam di kalangan tentara lawan.
Dalam banyak kasus, kekuatan kecil berkembang dalam posisi defensif. Mereka cenderung menjadi pihak yang diserang, bukan penyerang.
Oleh karena itu, perlawanan di Gaza menekankan pelatihan pasukan dalam perang perkotaan (urban warfare).
Faktor kota memberi keuntungan besar: bangunan bisa menjadi titik tembak atau perlindungan yang siap pakai, persediaan bisa disembunyikan, dan senjata bisa disamarkan. Sebaliknya, bagi pihak penyerang, kota adalah medan yang membatasi penglihatan, manuver, dan intelijen.
Drone, misalnya, tak mampu menembus dinding beton untuk mengintai apa yang tersembunyi.
Tentara penyerang harus masuk ke gang-gang sempit, di mana mereka terlihat jelas oleh pihak bertahan. Bahkan sekadar menyeberang jalan bisa menjadi ancaman mematikan bagi infanteri.
Sejarah mencatat bagaimana pertempuran di kota hampir selalu menguntungkan pihak bertahan: dari Stalingrad di era Perang Dunia II, hingga Grozny, Mogadishu, dan Fallujah. Kini, hal itu pula yang memberi napas bagi perlawanan di Gaza.
Kota memberikan ruang manuver, menyulitkan tank, dan pada titik tertentu memaksa pasukan Israel turun ke medan tempur terbuka: pertempuran klasik, manusia melawan manusia.
Perlawanan yang masih bertahan
Pada titik ini, pertanyaan yang layak diajukan adalah: bagaimana Brigade al-Qassam masih mampu mengatur serangan-serangan besar setelah berbulan-bulan perang, meski menghadapi disintegrasi kepemimpinan dan tercerainya unit-unit tempur di lapangan?
Jawabannya tidak tunggal. Para peneliti berbeda pandangan soal bagaimana Hamas mengelola operasi militernya.
Dalam sebuah tulisan di Journal of Palestine Studies edisi Juli 2024, peneliti Tariq Hamoud berargumen bahwa Hamas, baik politik maupun militernya, lebih tepat dipahami sebagai entitas jaringan desentralistis ketimbang organisasi hierarkis.
Menurutnya, tekanan Israel yang selalu menargetkan tokoh kunci mendorong pergeseran menuju model kepemimpinan yang tersebar, dengan otoritas terbagi ke banyak tangan.
Pandangan ini senada dengan analisis Bilal Saab, peneliti di lembaga riset Chatham House, London.
Kepada Financial Times, ia menilai Hamas mengadopsi pendekatan yang “sangat terdesentralisasi”.
Di mana setiap unit kecil bekerja mandiri dalam kerangka struktur militer menyerupai sel-sel kecil.
Tujuannya jelas: menimbulkan kerugian sebanyak mungkin pada Israel, dengan menggabungkan kekuatan non-konvensional dan konvensional.
Hal yang disepakati para analis adalah bahwa, apa pun yang menimpa unit-unit perlawanan di garis depan, struktur besar al-Qassam tetap bertahan.
Dengan demikian, perlawanan tidak pernah benar-benar berhenti, meskipun koordinasi pusat mungkin berkurang.
Perbandingan menarik muncul di sini: jika manusia bergantung pada otak sebagai pusat kendali tunggal, beberapa makhluk laut justru bisa terus hidup meski sebagian tubuhnya rusak.
Bahkan tumbuh kembali menjadi organisme baru. Begitu pula al-Qassam: kehilangan satu bagian tidak serta-merta mematikan keseluruhan.
Dalam sebuah kajian yang terbit Agustus 2023, Peter Kounsach—perwira Angkatan Darat AS sekaligus peneliti di Lieber Institute—menyatakan bahwa melemahkan Hamas tak cukup hanya dengan menguras pasukan tempur garis depan.
Lebih jauh dari itu, perlu menghancurkan seluruh jaringan penghubung antarunit, hingga ke kelompok-kelompok kecil yang nyaris sepenuhnya otonom.
Dengan kerangka itu, al-Qassam tampil sebagai kekuatan hibrid. Di satu sisi, mereka mirip faksi gerilya non-konvensional.
Di sisi lain, mereka juga punya atribut ala militer reguler—bahkan mendekati fungsi pemerintahan.
Kombinasi ini menjelaskan mengapa mereka masih memiliki struktur kokoh meski dihantam berkali-kali, sekaligus memberi keleluasaan bagi unit-unit kecil untuk mengambil keputusan mandiri di medan tempur.
Pendekatan “semi-sentralistis” ini menutup kelemahan utama model desentralisasi: fragmentasi strategi.
Dengan kata lain, meskipun unit-unit kecil diberi ruang inisiatif, arah besar perlawanan tetap konsisten.
Bila komunikasi terputus, pasukan kecil itu tetap terlatih membuat rencana, mengambil keputusan, dan melaksanakan operasi secara independent. Tujuan utama mereka jelas: menimbulkan kerugian sebesar mungkin di pihak Israel.
Perang non-konvensional, sejatinya, menuntut kecepatan adaptasi. Yang lemah secara teknologi harus mampu menentukan kapan dan di mana pertempuran dimulai dan diakhiri.
Inilah intinya: menghindari pertempuran frontal dengan tank dan jet tempur yang jelas lebih unggul, sambil memanfaatkan celah untuk menimbulkan dampak maksimal.
Contohnya terlihat dalam taktik serang-lari (hit and run). Meski kini lebih rumit, dengan variasi senjata dan pola serangan dari berbagai arah, esensinya tetap sama.
Yaitu, sekelompok kecil pejuang membuat rencana cepat untuk menyerang unit lawan di titik tertentu, lalu segera menghilang.
Kekuatan utama ada pada fleksibilitas. Unit-unit kecil itu mampu menciptakan taktik sesuai kondisi spesifik, mengeksploitasi kelemahan musuh yang mungkin baru muncul dalam satu momen singkat. Dengan demikian, serangan mereka bukan hanya efektif, tetapi juga sulit diprediksi.