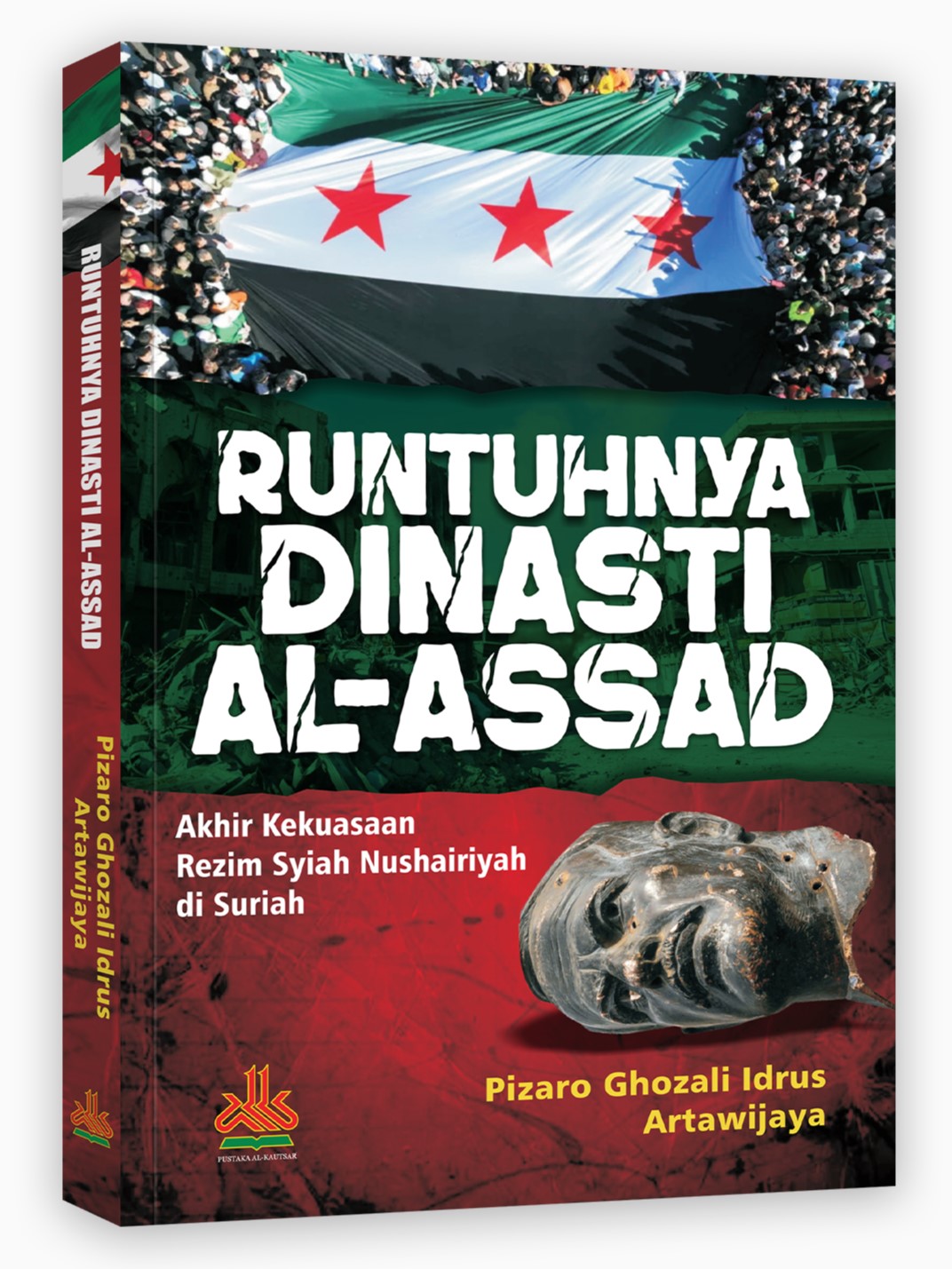Oleh: Dr. Mohamed El-Senousi*
Gedung Putih baru-baru ini merilis sebuah dokumen berisi 20 butir yang disebut sebagai “rencana perdamaian”, ditandatangani Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Rencana ini dipromosikan sebagai “awal era baru” bagi Gaza, dengan janji menghentikan perang serta membuka jalan bagi rekonstruksi besar-besaran.
Namun, pembacaan lebih saksama—dengan latar seratus tahun pengalaman pahit rakyat Palestina, dari Deklarasi Balfour (1917), keputusan pembagian wilayah (1947), Perjanjian Oslo (1993), hingga yang kini disebut “Proyek Trump”—menunjukkan bahwa yang dipasarkan sebagai solusi, sesungguhnya hanya mengulang siklus lama.
Yaitu, siklus kompromi dan pengingkaran hak-hak dasar Palestina. Pertanyaan penting pun muncul: apa sebenarnya isi dari rencana ini?
Janji di permukaan, jebakan di dalam
Rencana Trump–Netanyahu sekilas menyodorkan janji-janji manis: penghentian perang, jalan menuju perdamaian, hingga rekonstruksi Gaza.
Tetapi di balik kemasan yang berbalut wajah kemanusiaan, tersembunyi butir-butir berisiko tinggi secara politik. Antara iming-iming dan pelepasan hak, batasnya amat tipis.
Pertama, gencatan senjata seketika digambarkan sebagai pintu masuk untuk menghentikan pertumpahan darah.
Namun, hal itu diperlakukan bukan sebagai perjanjian mengikat, melainkan sebatas “ujian kepatuhan” pihak Palestina terhadap syarat-syarat baru.
Kedua, pelucutan total senjata Hamas di bawah pengawasan internasional menjadi jantung rencana ini.
Sementara senjata perlawanan dianggap “hambatan yang mesti dihapus”, Israel tetap berhak mempertahankan kekuatan militernya. Perdamaian dalam versi ini bukanlah keseimbangan, melainkan penyerahan.
Ketiga, pertukaran tawanan dan sandera ditempatkan dalam bingkai “langkah kemanusiaan”.
Namun, di sini dilegalkan kesetaraan palsu: ribuan tahanan Palestina—banyak ditangkap tanpa proses adil—diposisikan sebanding dengan sejumlah sandera Israel.
Keempat, penarikan pasukan Israel disebut sebagai imbalan bersyarat, bukan hak yang melekat pada rakyat yang diduduki.
Setiap pelanggaran kecil dari pihak Palestina memberi celah bagi Israel untuk tetap bercokol, sehingga penarikan berubah menjadi kartu tekanan abadi.
Kelima, pembentukan dewan transisi internasional—atau disebut “Dewan Perdamaian”—menjadi pasal paling genting.
Gaza akan ditempatkan di bawah semacam perwalian langsung yang dipimpin AS, dengan figur-figur seperti Tony Blair disebut masuk dalam jajaran pengawas.
Sejarah mencatat, transisi semacam ini kerap berubah permanen, membuka peluang pemisahan Gaza dari Tepi Barat, sekaligus mengosongkan inti dari proyek nasional Palestina.
Keenam, rekonstruksi besar-besaran ditawarkan sebagai hadiah. Tetapi, seperti biasa, bantuan dikelola pihak luar dan dijadikan instrumen tekanan politik: menerima syarat berarti mendapatkan dana, menolak berarti kembali ke jurang kehancuran.
Akhirnya, syarat paling berbahaya datang dari ultimatum Trump sendiri: rencana ini bukanlah tawaran damai sejati, melainkan ancaman terbuka.
Bila Palestina patuh, pintu bantuan dibuka. Bila menolak, Israel diberi restu penuh untuk melanjutkan perang.
Dengan demikian, rencana ini lebih dari sekadar proyek rekonstruksi atau penghentian konflik.
Ia adalah permainan politik yang rapi, berselimut jargon kemanusiaan, tetapi sejatinya memuat perangkat baru untuk memperpanjang perwalian asing sekaligus meruntuhkan proyek nasional Palestina.
Bila dicermati, ini bukan sekadar “kesepakatan kemanusiaan” yang lahir dari kebutuhan sesaat. Ia adalah langkah strategis untuk menata ulang peta kekuasaan di Gaza dan Tepi Barat.
Mekanismenya jelas: menempatkan Gaza di bawah administrasi internasional, mengaitkan bantuan rekonstruksi dengan syarat politik dan keamanan, serta membentuk kerangka baru yang mengutamakan kepentingan luar atas kedaulatan rakyat Palestina.
Dimensi yang berlapis ini menuntut pembacaan kritis. Satu per satu butir perlu ditelisik untuk membongkar jebakan yang terselip di balik wacana perdamaian.
Sebab, di balik janji “akhir perang” dan “awal pembangunan”, tersimpan peta jalan baru yang sesungguhnya hanya memuluskan kontrol asing—sekali lagi dengan mengorbankan kehendak nasional Palestina.
Memecah ranjau
Sebelum kita menyelami makna rinci rencana ini, penting disadari bahwa apa yang disodorkan hari ini bukan sekadar usulan rekonstruksi atau kesepakatan politik sementara.
Ini merupakan perpanjangan terencana dari pola-pola politik historis yang berulang selama beberapa dekade—memiliki tujuan mendasar yang sama namun disajikan dengan cara baru yang lebih meyakinkan dan mudah menggalang dukungan.
Rencana ini bukan kebetulan ataupun kumpulan pasal acak; melainkan jalinan ranjau dan jebakan strategis yang dirancang secara presisi.
Tujuannya bukan semata mengelola krisis darurat, melainkan mereproduksi pengalaman panjang peminggiran hak-hak Palestina—mengubah proyek nasional menjadi soal teknis dan agenda sementara yang pada akhirnya dibawa menuju penguburan permanen.
Setiap pasal bukan peristiwa sekejap, melainkan batu penjuru dalam sistem terpadu yang hendak merekonstruksi realitas politik di bawah selubung baru.
Yaitu, slogan-slogan kemanusiaan dan keamanan yang menyamarkan mekanisme perwalian berkepanjangan dan pemisahan politik baru.
Ranjau ini hanyalah alat dalam skema lebih besar yang bertujuan menegaskan status quo penindasan dan memperpanjang masa pendudukan—melalui serangkaian syarat, penundaan, dan keputusan yang disajikan sebagai solusi kemanusiaan.
Oleh karena itu, menghadapi realitas ini tidak cukup dengan membaca permukaan naskah. Diperlukan pembacaan mendalam dan pembongkaran ranjau satu per satu untuk memahami peta strategis risiko yang disamarkan dan mengungkap niat sesungguhnya di balik penyusunannya.
Dari titik inilah analisis berlanjut ke tahap berikut: memecah ranjau yang terselip dalam teks rencana, di mana pasal-pasal tampak sebagai instrumen strategis halus yang berupaya merekonstruksi realitas Palestina secara sistematis.
Selain itu juga menyembunyikan ancaman langsung terhadap proyek nasional dan kedaulatan Palestina di balik sampul kemanusiaan dan keamanan.
Proses ini tidak sebatas merancang ulang peta kontrol; ia menyinggung inti persoalan Palestina secara politik dan kemanusiaan.
Terang jelas bahwa rencana ini bukan entitas sementara, melainkan bagian dari proses berkepanjangan yang menata kembali masa depan rakyat Palestina dengan sekumpulan batasan yang mengekang hak menentukan nasib sendiri.
Ranjau “bersifat sementara” — dari janji temporer ke realitas abadi
Sejarah memberi pelajaran: ungkapan-ungkapan yang diposisikan sebagai bersifat sementara kerap bertransformasi menjadi norma yang menetap.
Dari Deklarasi Balfour hingga Perjanjian Oslo, pengalaman Palestina menunjukkan bagaimana janji administratif kemudian bercokol menjadi kenyataan politik yang membatasi tuntutan nasional.
Kini, rencana ini mengusulkan suatu dewan transisi internasional yang tampak sementara—namun menyandang kewenangan operasional dan administratif yang menjamin keberlangsungan.
Ancaman yang nyata adalah kemungkinan terciptanya pemisahan administratif dan politik antara Gaza dan Tepi Barat, sehingga apa yang disebut “fase transisi” berubah menjadi kenyataan menetap yang mengerdilkan kesatuan proyek nasional.
Ranjau “mengubah hak menjadi urusan teknis dan keamanan”
Sejarah Palestina sarat dengan upaya mereduksi hak-hak politik menjadi isu keamanan atau teknis belaka, sehingga substansinya dikosongkan dari makna politik.
Kini, tuntutan pelucutan senjata Hamas dijadikan prasyarat utama bagi rekonstruksi Gaza.
Namun, tak ada ruang diskusi mengenai senjata pendudukan atau mekanisme kontrol yang dipelihara Israel.
Hasil akhirnya adalah marginalisasi dimensi politik perlawanan, dengan hak-hak dasar yang diciutkan menjadi urusan manajemen keamanan yang tetap berada di tangan pihak terkuat.
Ranjau “iming-iming ekonomi dengan harga pelepasan politik”
Inilah ranjau paling berbahaya, sebab ia menghidupkan kembali pola tawar-menawar lama: janji kemakmuran sebagai imbalan atas penyerahan hak.
Dari Deklarasi Balfour, lewat proyek-proyek pembangunan yang syaratnya menggugurkan hak-hak fundamental, hingga Perjanjian Oslo yang membuat otoritas Palestina bergantung pada pendanaan internasional dengan konsekuensi membekukan isu-isu inti—sejarah penuh dengan pola serupa.
Kini, rencana Trump–Netanyahu melanjutkan praktik itu dengan balutan janji “revitalisasi ala Riviera” dan rekonstruksi menyeluruh, dengan syarat pelucutan senjata Gaza dan penyerahan administrasinya kepada lembaga internasional.
Dengan kata lain, hak-hak paling elementer rakyat Palestina dijadikan instrumen pemerasan politik.
Hasilnya mudah ditebak: ekonomi rapuh, ketergantungan absolut, dan isu kemerdekaan maupun kedaulatan terdorong ke pinggiran.
Ranjau “penundaan isu-isu pokok”
Menunda persoalan inti ke “tahap selanjutnya” telah lama menjadi taktik memperpanjang pendudukan dan membentuk ulang realitas di lapangan.
Perjanjian Oslo sudah mewujudkan strategi ini, dan kini rencana baru mengulanginya dengan kemasan lebih menggoda.
Masalah-masalah mendasar tetap digantung tanpa batas waktu dan tanpa jaminan penyelesaian.
Konsekuensinya adalah rekonstruksi tanpa kedaulatan, gencatan senjata tanpa solusi konflik, serta masa transisi yang dijadikan tujuan itu sendiri—yang pada akhirnya mengikis substansi proyek nasional.
Ranjau “perwalian internasional dan sterilisasi politik”
Usulan pembentukan dewan internasional untuk mengelola Gaza tidak lain adalah bentuk perwalian baru dalam kemasan modern.
Atas nama netralitas dan teknokrasi, mekanisme ini justru melegitimasi penghapusan aktor-aktor politik Palestina, sekaligus menyerahkan kendali kepada kekuatan eksternal.
Dampaknya, Gaza berisiko berubah menjadi entitas administratif yang tunduk, terputus dari kehendak nasional, serta terjerumus dalam fragmentasi yang mengancam kesatuan proyek kebangsaan Palestina.
Ranjau “ancaman kekerasan sebagai instrumen negosiasi”
Sejarah Palestina menunjukkan pola berulang: kekerasan digunakan untuk memaksa penerimaan syarat politik. Hari ini, pola itu tampil lebih gamblang.
Rencana yang ditawarkan disertai peringatan keras: setiap penolakan akan dihadapi dengan dukungan militer penuh bagi Israel.
Dengan demikian, tertanam logika tunduk melalui kekuatan, sekaligus meneguhkan pandangan bahwa perdamaian hanya mungkin dicapai lewat kepatuhan, bukan berdasarkan hak yang adil.
Ranjau “pemisahan administratif dan keroposnya nasionalisme”
Setiap skema serupa pada hakikatnya ditujukan untuk merusak proyek nasional melalui fragmentasi wilayah dan bangsa.
Sejak gagasan “ikatan desa” hingga konsep otonomi terbatas, tujuan utamanya adalah mengubah rakyat Palestina menjadi komunitas-komunitas lokal tanpa kedaulatan.
Rencana baru ini mengulang pola sama: membentuk administrasi terpisah bagi Gaza, yang hanya melayani kepentingan pendudukan dan memperdalam perpecahan internal.
Dampaknya jelas: melemahnya prospek persatuan nasional sejati.
Inti Gagasan: Memperbarui Alat, Mempertahankan Masalah
Gagasan pokok yang menonjol dari rencana ini adalah bahwa ia bukan sekadar upaya menyelesaikan sengketa tertentu, melainkan pembaruan canggih atas perangkat lama dalam mengelola persoalan Palestina.
Bukan untuk mengakhirinya, melainkan untuk mempertahankannya dalam bentuk yang lebih “modern”.
Teknik baru yang dihadirkan tampak mengilap: dewan internasional untuk mengelola Gaza, janji rekonstruksi besar-besaran, strategi komunikasi publik yang rapi, hingga nama-nama tokoh dunia yang memberi legitimasi simbolik.
Namun, substansi politik tetap sama: mengelola persoalan, bukan menutupnya; menunda keputusan nasib, bukan menegaskannya; serta mengubah hak-hak dasar menjadi klausul keamanan semata.
Dengan kata lain, alat baru hanyalah etalase dari sebuah pola panjang, di mana pendudukan diperpanjang dan Nakba dipelihara sebagai tragedi berkelanjutan.
Bagian dari strategi regional
Rencana ini sejatinya merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk menata ulang Timur Tengah. Ada beberapa poros utama yang saling terhubung.
Pertama, normalisasi regional. Pemisahan administratif Gaza dari Tepi Barat melemahkan proyek politik Palestina sebagai satu kesatuan.
Perpecahan ini memudahkan Israel dan sebagian negara Arab menjual normalisasi sebagai “langkah kemanusiaan” atau “damai ekonomi”. Tanpa kekuatan Palestina yang bersatu, jalur ini akan sulit ditantang.
Maka, yang disebut “kesepakatan damai” lebih tepat dibaca sebagai pintu masuk menuju normalisasi bertahap dalam bayang-bayang perwalian internasional.
Kedua, keamanan energi dan sumber ekonomi. Rekonstruksi Gaza dan proyek-proyek pembangunan besar dapat dijadikan sarana integrasi ekonomi regional yang menguntungkan Israel dan para pendukungnya.
Termasuk di dalamnya: keterlibatan perusahaan multinasional, negara kaya, hingga kemungkinan menjadikan Gaza simpul energi, pelabuhan, dan jalur perdagangan.
Mekanisme ini memberi kekuatan eksternal kendali atas ekonomi Gaza, sekaligus mengubah ketergantungan ekonomi menjadi alat tekanan politik jangka panjang.
Ketiga, poros pengaruh regional. Pembentukan dewan internasional untuk mengelola Gaza secara langsung meredefinisi kedaulatan Palestina dalam bingkai perwalian global.
Ini bukan sekadar urusan lokal, melainkan bagian dari proyek geostrategis: mendistribusikan ulang pengaruh di Timur Tengah dengan Washington dan kekuatan Barat di pusat panggung, sementara normalisasi ekonomi-politik dijadikan instrumen pengendalian.
Konsekuensi yang mengintai
Dari peta besar itu, setidaknya lima konsekuensi utama dapat dicatat:
- Perwalian panjang: pengelolaan sementara oleh pihak luar yang mudah menjelma permanen, menciptakan dekade-dekade keterasingan rakyat Palestina dari kendali atas nasib mereka sendiri.
- Fragmentasi proyek nasional: pemisahan Gaza dari Tepi Barat meruntuhkan kapasitas tawar kolektif, sekaligus menghantam peluang membangun negara Palestina yang utuh.
- Ketergantungan ekonomi dan politik: rekonstruksi dijalankan dengan syarat investor dan negara luar, sehingga melemahkan pondasi ekonomi berdaulat.
- Erosi hak-hak fundamental: hak kembali, hak atas tanah, serta kedaulatan diturunkan menjadi “isu yang ditunda” atau diganti dengan kompensasi ekonomi, sementara pendudukan terus berlangsung.
- Pelemahan resistensi politik dan sosial: pengosongan peran aktor lokal, baik politik maupun militer, bertujuan meruntuhkan jaringan perlawanan masyarakat yang selama ini menjadi faktor penekan nyata terhadap pendudukan.
Dengan demikian, rencana Trump–Netanyahu tidak bisa dipandang sekadar sebagai dokumen atau perjanjian. Ia adalah bagian dari strategi komprehensif untuk mengatur ulang keseimbangan kekuatan di kawasan.
Persoalan Palestina ditempatkan dalam lingkaran pengelolaan tanpa akhir, diubah menjadi dossier kemanusiaan dan administratif—alih-alih sebagai isu politik dengan hak-hak nasional yang jelas.
Dalam konteks ini, menerima atau menolak rencana bukan hanya soal sikap politik. Ia adalah ujian bagi daya tahan setiap proyek nasional Palestina untuk menghadapi jaringan tekanan yang terjalin rapi—politik, ekonomi, dan internasional—yang semuanya diarahkan untuk mempertahankan masalah, bukan menyelesaikannya.
Respons cerdas Palestina atas rencana Trump-Netanyahu
Respons yang cerdas dari pihak Palestina terhadap rencana Trump-Netanyahu tidak cukup berhenti pada sikap penolakan simbolik.
Ia harus dibangun di atas pemahaman yang mendalam tentang hakikat tantangan yang dihadirkan, sekaligus ditopang oleh kapasitas strategis untuk menyatukan barisan dan mengubah penolakan menjadi agenda kerja yang nyata.
Penolakan itu perlu ditegaskan melalui garis merah yang jelas: tidak ada rekonstruksi yang dapat diterima tanpa jadwal konkret penarikan pasukan, serta tanpa pemulihan penuh kendali Palestina atas seluruh pintu masuk dan keluar wilayah.
Prinsipnya, pemulihan kedaulatan di atas tanah harus menjadi prasyarat, bukan sekadar proyek ekonomi atau program kemanusiaan yang tanpa jaminan politik.
Di titik ini, tantangan utama adalah memastikan adanya representasi Palestina yang menyeluruh dan sah.
Setiap upaya membentuk tata kelola dari luar tanpa keterlibatan penuh institusi Palestina—baik faksi perlawanan, Dewan Nasional, lembaga peradilan, maupun organisasi masyarakat sipil—harus ditolak.
Persatuan bukan sekadar tuntutan seremonial, melainkan senjata strategis yang dapat menggagalkan upaya memecah-belah bangsa Palestina dengan dalih pembentukan administrasi baru.
Keterkaitan antara rekonstruksi dan kedaulatan perlu dijadikan prinsip dasar. Kontrak pembiayaan serta proyek pembangunan harus disusun dengan mekanisme yang menjamin peralihan kepemilikan dan kendali operasional secara bertahap kepada lembaga-lembaga Palestina.
Dengan begitu, rekonstruksi tidak berubah menjadi instrumen tekanan atau bentuk pengawasan, melainkan langkah menuju pemulihan kedaulatan nasional.
Di ranah hukum dan politik, gerakan Palestina juga perlu bergerak ke jalur internasional untuk menantang rencana ini.
Langkah menuju Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional, serta lembaga-lembaga hak asasi dunia perlu ditempuh guna menegaskan bahwa hak-hak nasional Palestina bukanlah komoditas yang bisa ditawar.
Sejalan dengan itu, diperlukan pula kampanye media dan diplomasi publik yang kuat. Upaya ini harus menyingkap praktik-praktik tekanan politik dan ekonomi di balik rencana tersebut, serta menelusuri sejarah berbagai formula serupa yang pernah menjerat Palestina.
Tujuannya, membangun kesadaran bahwa rencana ini bukanlah peta jalan perdamaian, melainkan proyek jangka panjang untuk menempatkan Palestina di bawah pengelolaan eksternal.
Kampanye itu idealnya berangkat dari narasi sejarah yang teruji, bukti-bukti hukum yang kuat, dan strategi komunikasi yang cermat.
Hanya dengan cara itu, tabir propaganda dapat disibakkan, dan rencana ini diposisikan sebagai isu penolakan bersama—baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dengan strategi terpadu semacam ini, penolakan tidak lagi sekadar menjadi simbol perlawanan.
Ia dapat bermetamorfosis menjadi kekuatan politik, hukum, dan moral yang mampu menggagalkan proyek rekayasa regional, sekaligus mengembalikan isu Palestina ke jantung percaturan global—bukan sebagai “file” yang dikelola dari luar, melainkan sebagai perjuangan bangsa yang sah.
*Dr. Mohamed El-Senousi merupakan seorang Profesor Studi Foresight dan Hubungan Internasional di Universitas Mohammed V di Maroko. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Al-Fakhu al-Akbar Fī Khuṭṭah Trāmb”.