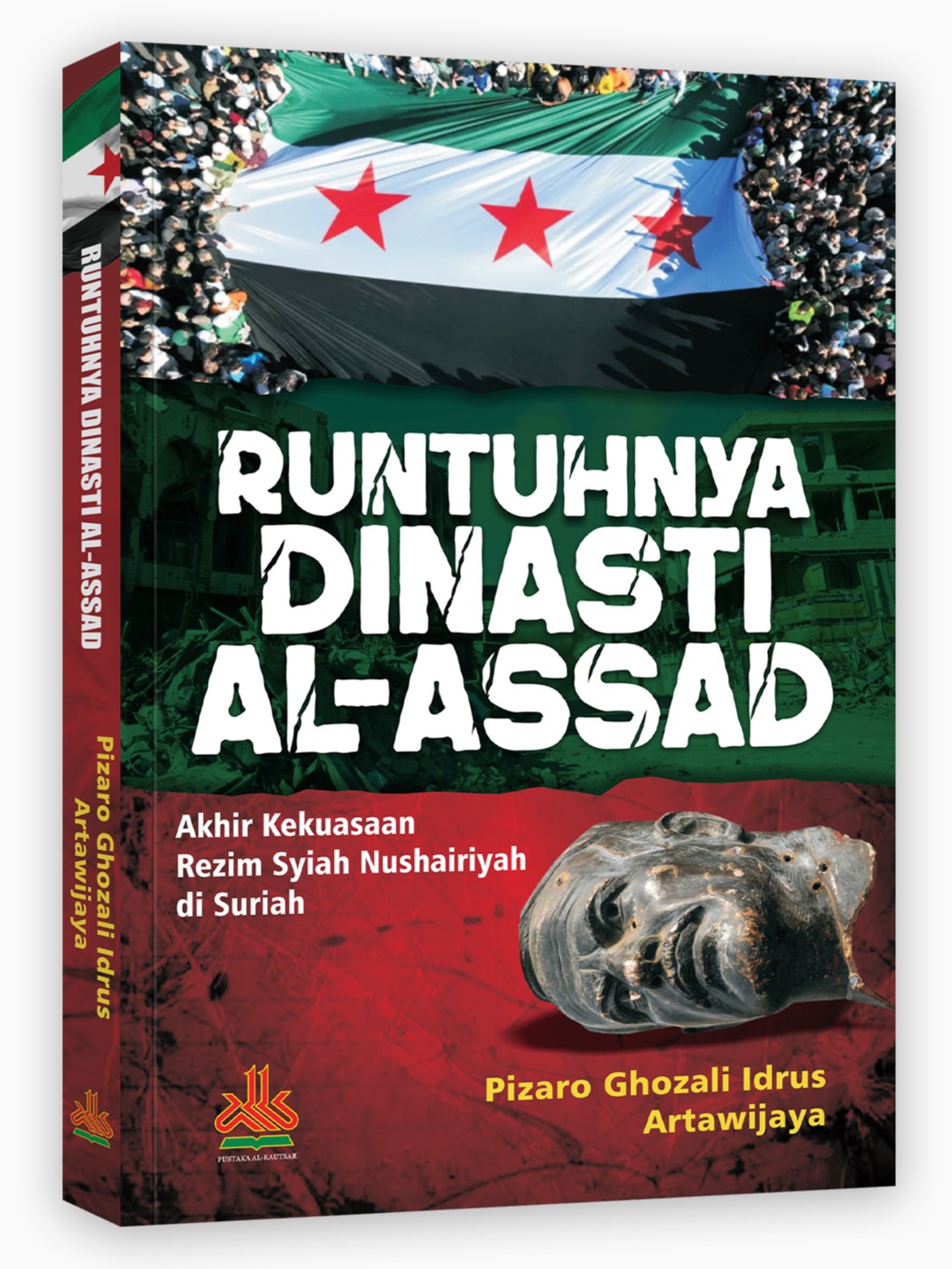Oleh: Robert Inlakesh
Isyarat renggangnya hubungan antara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian mencuat ke permukaan.
Laporan dari berbagai media, termasuk media Israel dan Amerika Serikat, menyebutkan bahwa jalur komunikasi langsung antara kedua pemimpin tersebut kini telah ditutup.
Di tengah tekanan yang meningkat atas Israel terkait agresinya di Gaza, serta penghentian mendadak operasi militer AS terhadap Ansarallah di Yaman, muncul pertanyaan besar: apakah ini sekadar manuver atau AS benar-benar mulai memberi tekanan serius kepada Israel?
Ketegangan ini mulai mencuat pada 1 Mei, ketika Presiden Trump secara mendadak memberhentikan penasihat keamanan nasionalnya, Mike Waltz.
Menurut laporan The Washington Post, salah satu alasan utama pemecatan itu adalah upaya Waltz untuk berkoordinasi secara intensif dengan Netanyahu—terkait rencana serangan terhadap Iran—tanpa sepengetahuan Presiden, menjelang kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih.
Beberapa analis melihat pemecatan Waltz sebagai kemenangan kubu pendukung diplomasi dalam pemerintahan Trump, yang selama ini kalah suara dari kelompok yang mendesak konfrontasi militer.
Langkah ini juga terjadi di tengah kebuntuan dalam perundingan Iran-AS, yang banyak pihak anggap dipengaruhi oleh tekanan dari lobi pro-Israel. Termasuk think tank terkemuka AS dan tokoh Israel seperti Ron Dermer.
Lima hari kemudian, pada 6 Mei, Presiden Trump secara mengejutkan mengumumkan penghentian kampanye militer terhadap kelompok Ansarallah yang berkuasa di Sana’a, Yaman.
Keputusan ini mengejutkan Tel Aviv, yang selama ini mengandalkan dukungan militer AS dalam menghadapi kelompok tersebut. Kini, Israel harus menghadapi Ansarallah seorang diri.
Tak lama berselang, laporan dari media berbahasa Ibrani di Israel mulai mengungkap bahwa pemerintahan Trump menuntut Israel menyepakati perjanjian penghentian tembak-menembak dan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Bahkan, sumber-sumber itu menyebut bahwa Presiden Trump sangat kecewa terhadap Netanyahu hingga memutuskan komunikasi langsung dengannya.
Pemerintah kedua negara sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keretakan hubungan tersebut.
Namun, Netanyahu baru-baru ini mengunggah video di media sosial yang menegaskan bahwa dirinya akan “bertindak sendiri demi membela Israel”.
Di saat yang sama, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dikabarkan membatalkan kunjungannya ke Tel Aviv.
AS ambil sikap terhadap Israel?
Untuk memahami dinamika ini, sejumlah konteks mendasar perlu diperhatikan. Pertama, seluruh jajaran pemerintahan Trump secara historis dikenal sangat pro-Israel dan banyak didukung oleh lobi Israel.
Mike Waltz, misalnya, diketahui telah lama mendapat dukungan dari kelompok-kelompok pro-Israel.
Dalam rekaman audio dari konferensi AIPAC yang dibocorkan oleh The Grayzone, Waltz disebut telah “dipersiapkan” oleh lobi Israel untuk posisi penting di pemerintahan.
Terlepas dari pemecatannya sebagai penasihat keamanan nasional, Waltz tidak sepenuhnya disingkirkan dari lingkaran kekuasaan.
Ia justru dipilih untuk menduduki posisi sebagai duta besar AS untuk PBB, menggantikan Elise Stefanik, anggota Kongres yang dikenal vokal mendukung Israel dan menggagas pembatasan terhadap gerakan pro-Palestina di kampus-kampus AS.
Penarikan pencalonan Stefanik sendiri dilakukan demi mempertahankan mayoritas Partai Republik di Kongres.
Maka muncul pertanyaan krusial: jika Trump memang berniat menjauh dari pengaruh lobi pro-Israel, mengapa ia justru mengumumkan paket sanksi baru terhadap Iran hanya seminggu kemudian?
Pada Jumat lalu, Trump menyatakan bahwa sebuah perusahaan penyulingan independen ketiga asal Tiongkok akan dikenai sanksi sekunder karena menerima pasokan minyak dari Iran.
Kebijakan ini, ditambah dengan sikap tim negosiasi AS yang terus menambahkan syarat-syarat baru dalam perundingan dengan Iran.
Syarat yang oleh Teheran dianggap sebagai titik buntu, menunjukkan bahwa agenda yang selama ini diperjuangkan think tank pro-Israel seperti WINEP dan FDD masih mendominasi arah kebijakan luar negeri AS.
Namun demikian, muncul indikasi bahwa perpecahan mulai terjadi dalam tubuh lobi pro-Israel itu sendiri, dan kini mulai menjalar ke dalam pemerintahan Trump.
Meski begitu, tidak bisa diabaikan bahwa kampanye Trump selama ini didanai oleh miliarder Zionis dan tokoh teknologi ternama.
Termasuk Miriam Adelson, orang terkaya di Israel dan pemilik surat kabar Israel Hayom, yang selama ini dikenal sangat pro-Netanyahu.
Ironisnya, kini Israel Hayom pun turut meliput keretakan hubungan Trump-Netanyahu, sekaligus memperkuat spekulasi yang berkembang.
Adapun penghentian operasi AS terhadap Ansarallah juga dinilai bukan semata keputusan damai.
Banyak pengamat melihat hal ini sebagai alasan strategis untuk memindahkan aset militer besar-besaran ke kawasan, terutama sistem pertahanan udara ke negara-negara Teluk dan Israel.
Meski sebelumnya Trump mengklaim Ansarallah telah “dihancurkan” pada Maret lalu, faktanya lebih dari dua miliar dolar dihabiskan dan tidak ada hasil signifikan.
Sehingga hanya operasi darat yang tersisa sebagai pilihan, sesuatu yang jelas tidak ingin AS lakukan.
Sementara itu, militer AS juga terus mengintensifkan aktivitas intelijen dan pengintaian di wilayah udara Lebanon dalam upaya memetakan kekuatan Hizbullah, sebuah indikasi bahwa konflik regional yang lebih besar masih membayangi.
Isu serangan ke Iran dan peran AS: Benarkah hanya drama politik?
Apakah yang sedang terjadi antara Presiden AS, Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merupakan konflik nyata, atau sekadar bagian dari strategi “polisi baik dan polisi buruk”?
Di tengah dinamika tersebut, muncul kekhawatiran bahwa suatu bentuk serangan terhadap Iran kini semakin mendekati kenyataan.
Baik serangan itu dilakukan sebagai langkah putus asa Netanyahu maupun sebagai bagian dari skenario terencana, Amerika Serikat tampaknya akan tetap terlibat dalam kapasitas tertentu.
Netanyahu, yang saat ini menghadapi tekanan politik domestik luar biasa, telah mengambil keputusan-keputusan ekstrem demi mempertahankan kekuasaan.
Pada Maret lalu, ia membatalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza demi mengamankan kembali dukungan dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, tokoh dari koalisi ultranasionalis.
Keputusan ini memberinya keunggulan untuk menyingkirkan kepala Shin Bet, Ronen Bar, dalam upaya konsolidasi kekuasaan.
Namun, ketidakmampuan menggelar operasi darat besar di Gaza tanpa mengorbankan keamanan Israel di front lain membuat Netanyahu memilih jalur penekanan melalui kelaparan massal.
Ia mengancam akan meluncurkan operasi darat berskala besar, namun banyak pihak memandangnya tidak lebih dari ancaman pembantaian sipil besar-besaran.
Kesalahan strategis Netanyahu adalah menjadikan blokade total bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai posisi politik yang tidak bisa ditawar.
Hal ini menjadi komitmen ideologis koalisi kanan relijius yang mendukungnya, dan kini menjadi batu sandungan utama.
Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat mulai menekan Tel Aviv karena khawatir akan reaksi internasional jika kelaparan massal benar-benar terjadi.
Di tengah kekacauan tersebut, Netanyahu juga memberikan janji baru kepada komunitas Druze bahwa ia akan membela kepentingan mereka di Suriah.
Meski tidak ada ancaman langsung dari Damaskus, janji tersebut berisiko memunculkan ketegangan baru apabila gagal dipenuhi, terutama karena komunitas Druze berperan penting dalam militer Israel.
Sementara itu, ketegangan di perbatasan Lebanon dengan Hizbullah terus membara. Kelompok ini hanya menunggu kesempatan untuk membalas pembunuhan terhadap Sekretaris Jenderalnya, Hassan Nasrallah.
Jika situasi Gaza memuncak dan jalur bantuan tetap diblokir, Hamas dan kelompok bersenjata lainnya kemungkinan akan meluncurkan serangan balik berskala besar, suatu skenario yang oleh sebagian pihak disebut sebagai “opsi kiamat”.
Di sisi lain, kelompok Ansarallah dari Yaman juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti menyerang Israel tanpa adanya operasi darat besar.
Singkatnya, Israel kini menghadapi serangkaian musuh yang seluruhnya telah teradikalisasi akibat kekerasan yang dialami oleh rakyat mereka masing-masing.
Israel tidak mampu menang di semua front, dan tampaknya sedang mencari “jalan keluar”. Iran dipandang sebagai pusat kekuatan poros perlawanan di kawasan, sehingga menjadi target logis bagi mereka yang ingin mengakhiri konflik multi-front.
Namun, Iran merupakan negara kuat yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan senjata konvensional.
Maka, serangan besar terhadap Iran berisiko menyeret kawasan ke dalam perang regional yang menghancurkan.
Pernyataan Trump sebelumnya bahwa Israel akan memimpin serangan terhadap Iran, dengan dukungan dari AS, menjadi isyarat penting.
Ini menunjukkan bahwa skenario perang terbatas sedang dipertimbangkan di Washington. Dan di tengah kebuntuan politik Netanyahu, serangan terhadap Iran bisa menjadi pengalih perhatian besar-besaran yang dibutuhkan.
Target utama dari skenario semacam itu kemungkinan adalah fasilitas nuklir Iran. Serangan ini, apabila hanya menggunakan senjata konvensional, mungkin hanya akan menunda program nuklir Teheran selama beberapa tahun.
Namun, bisa juga melibatkan taktik perang hibrida dan pembunuhan tokoh senior Iran, yang bersifat simbolis namun berisiko memicu pembalasan.
Iran diperkirakan akan merespons dengan meluncurkan rudal ke basis-basis militer Israel, termasuk kemungkinan menyerang infrastruktur penting seperti pelabuhan dan jaringan listrik.
Hal ini bisa melumpuhkan Angkatan Udara Israel, memaksa mereka menggunakan pangkalan alternatif seperti di Siprus.
Skenario semacam ini bisa membuat Hizbullah turun tangan, yang dapat membuat Israel kelimpungan dan memaksa Amerika Serikat melakukan intervensi langsung.
Dalam situasi seperti itu, Hamas pun menjadi variabel yang tidak bisa diprediksi, mengingat penderitaan rakyat Gaza yang luar biasa.
Jika AS dan Israel berasumsi bahwa Iran akan tetap bersikap rasional dan tidak akan memicu perang habis-habisan, maka serangan terbatas mungkin dianggap sebagai langkah strategis.
Beberapa pihak bertanya, mengapa Iran tidak langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalas dan bahkan menghancurkan Israel?
Jawabannya kemungkinan besar terkait senjata nuklir: ancaman kehancuran total menjadi penahan utama dalam konflik ini.
Dengan latar ini, kemungkinan serangan terhadap Iran oleh Israel menjadi lebih masuk akal.
Apalagi, jika ketegangan Netanyahu dengan Trump ternyata hanya sandiwara untuk menunjukkan kepada koalisi garis keras bahwa Netanyahu telah “melawan tekanan AS” tetapi tetap membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza sebagai kompromi.
Namun, skenario paling ekstrem harus tetap menjadi perhatian. Sebab, kondisi Israel saat ini sangat rapuh, sementara ekstremisme Netanyahu seolah tak mengenal batas.
Jika tidak ada intervensi serius, satu-satunya jalan keluar dari kemungkinan perang kawasan adalah pergantian kepemimpinan di Tel Aviv.
*Robert Inlakesh adalah seorang jurnalis, penulis, dan pembuat film dokumenter. Ia berfokus pada Timur Tengah, khususnya Palestina. Tulisan ini diambil dari palestinechronicle.com dengan judul “Cutting Off Communications: Did Trump Really Just Turn His Back On Israel?”.