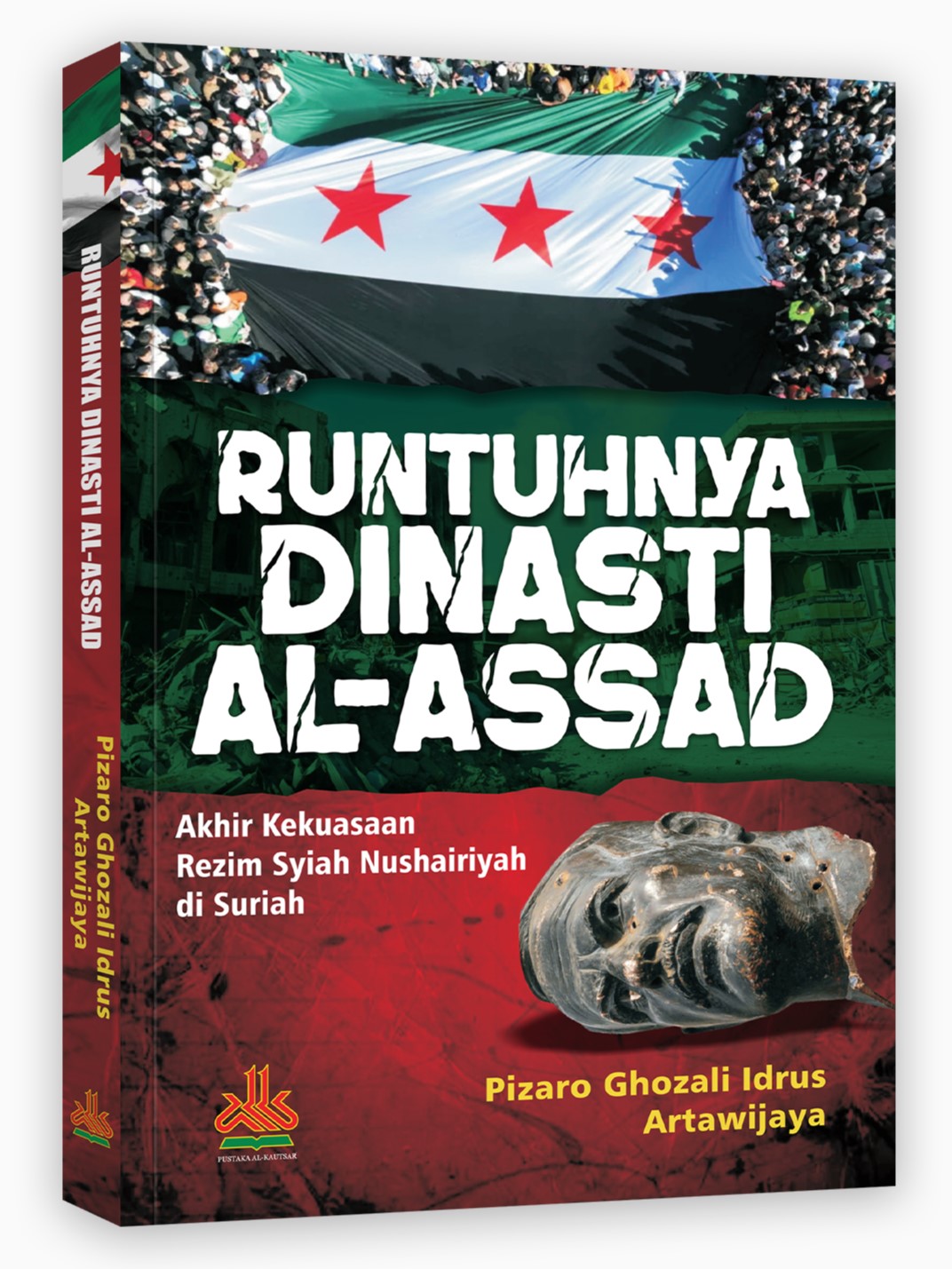Oleh: Dr. Ussama Makdisi*
Krisis kemanusiaan di Gaza, eskalasi ketegangan di Lebanon, dan konflik berkepanjangan di Yaman telah membuka kembali luka lama yang menyertai kelahiran negara-negara Arab modern.
Retakan dalam apa yang disebut sebagai “fasad Arab”—sebuah konsep lama yang diciptakan untuk menutupi dominasi kekuatan Barat—kian nyata terlihat.
Negara-negara Arab yang terbentuk setelah runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah usai Perang Dunia I tidak dirancang untuk memenuhi aspirasi masyarakat asli kawasan.
Sebaliknya, desain geopolitik itu lebih ditujukan untuk melayani kepentingan kekuatan-kekuatan imperialis Barat, khususnya Inggris dan Prancis.
Seorang pejabat di Kantor India milik Inggris bahkan sempat mengakui pada 1918, saat pengaruh Inggris mulai menguat di kawasan Timur Tengah.
“Kata-kata lama sudah usang, dan pertanyaannya kini adalah bagaimana kita dapat mempertahankan hal-hal yang esensial dalam kemasan baru. Ini bisa dilakukan, tetapi diperlukan sedikit penyesuaian. Fasad Arab mungkin harus terlihat lebih kokoh dari yang semula kami bayangkan,” katanya.
Pernyataan itu menggambarkan strategi baru kekuasaan kolonial: mempertahankan kendali atas wilayah jajahan sambil menyulapnya seolah-olah berada di bawah otoritas lokal.
Gagasan “fasad Arab” merupakan adaptasi dari strategi lama Inggris yang dikenal sebagai indirect rule atau pemerintahan tidak langsung—yang sebelumnya diterapkan di Afrika—untuk menetralkan semangat kemerdekaan yang mulai tumbuh.
Janji kosong dan persekongkolan rahasia
Inggris memainkan peran utama dalam membantu bangsa Arab menggulingkan Kekaisaran Utsmaniyah.
Mereka mensponsori Pemberontakan Arab tahun 1916 yang dipimpin oleh Syarif Husain dari Mekkah. Seorang tokoh Hasyimiyah yang sebelumnya bersekutu dengan Utsmaniyah namun kemudian berpihak kepada Inggris demi iming-iming kemerdekaan.
Inggris menjanjikan kepada Syarif Husain berdirinya kerajaan Arab merdeka yang membentang dari Hijaz hingga Palestina.
Namun kenyataannya, janji itu tak lebih dari alat tawar untuk meruntuhkan sisa-sisa kesatuan Utsmaniyah.
Sejarah mencatat bahwa Inggris dan Prancis telah lebih dulu sepakat membagi wilayah bekas Utsmaniyah dalam perjanjian rahasia Sykes-Picot tahun 1916.
Perjanjian ini secara langsung mengkhianati janji Inggris kepada bangsa Arab. Tak heran jika hingga kini istilah “Sykes-Picot” sering dijadikan simbol pengkhianatan kolonial.
Setahun kemudian, Inggris kembali membuat langkah yang memicu kontroversi. Melalui Deklarasi Balfour tahun 1917, pemerintah Inggris menyatakan dukungannya terhadap proyek kolonisasi Zionis Eropa untuk mendirikan “tanah air nasional bagi bangsa Yahudi” di Palestina.
Pernyataan itu disampaikan tanpa memperhatikan kenyataan bahwa pada saat itu, mayoritas penduduk Palestina adalah Arab, sementara komunitas Yahudi hanya merupakan minoritas kecil.
Bahkan dalam teks resmi Deklarasi Balfour, warga Palestina hanya disebut sebagai “komunitas non-Yahudi”, sebuah istilah yang menyiratkan pengingkaran terhadap hak dan identitas nasional mereka.
Janji kemerdekaan yang palsu
Setelah kebocoran Perjanjian Sykes-Picot dan pengumuman Deklarasi Balfour yang memicu kekecewaan di kalangan masyarakat Arab, Inggris dan Prancis mencoba meredam keresahan tersebut.
Mereka mengeluarkan pernyataan bersama pada November 1918, yang dikenal sebagai Deklarasi Anglo-Prancis.
Dalam pernyataan itu, kedua kekuatan kolonial menyatakan bahwa tujuan mereka di Timur Tengah adalah “pembebasan penuh dan pasti atas bangsa-bangsa yang telah lama tertindas oleh Turki”.
Serta pembentukan pemerintahan nasional yang “berasal dari inisiatif dan pilihan bebas penduduk asli”.
Lebih jauh, mereka menegaskan tidak akan memaksakan lembaga-lembaga tertentu kepada masyarakat setempat, dan berjanji hanya akan mendukung terbentuknya pemerintahan yang “dipilih secara bebas”.
Mereka mengklaim akan menjamin keadilan yang setara, mendorong pembangunan ekonomi melalui inisiatif lokal, menyebarluaskan pendidikan, serta mengakhiri perpecahan internal yang sebelumnya dimanfaatkan oleh kekuasaan Utsmaniyah.
Namun, di balik kata-kata manis tersebut, tersembunyi strategi untuk memperkokoh kembali fasad Arab.
Fasad ini mengharuskan hadirnya pemimpin lokal yang secara de facto tunduk pada kepentingan kolonial.
Lima syarat penjajahan gaya baru
Syarat dari “kemerdekaan semu” tersebut terbagi ke dalam 5 poin utama:
- Pemimpin lokal harus menerima posisinya yang tunduk pada kekuasaan Inggris.
- Ia juga harus mengakui bahwa keberlangsungan kekuasaan dinastinya bergantung pada loyalitas kepada Kerajaan Inggris.
- Ia tidak boleh menentang dominasi Inggris di kawasan, termasuk dukungan terhadap proyek kolonisasi Zionis di Palestina—meskipun langkah itu sangat tidak populer di mata rakyatnya.
- Ia wajib menenangkan rakyatnya yang menuntut pembebasan Palestina, atau jika gagal, menindas tuntutan tersebut dengan kekerasan.
- Jika semua syarat itu dipenuhi, barulah “kemerdekaan nominal” bisa diberikan, tetapi dengan banyak pengecualian.
Sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa keluarga Hasyimiyah adalah sosok yang cocok untuk memainkan peran ini.
Meski demikian, banyak penguasa Arab lain juga memenuhi kriteria serupa, termasuk Ibnu Saud di Arabia dan Raja Fuad di Mesir.
Dua putra Syarif Husain—Faisal dan Abdullah—kemudian ditempatkan sebagai penguasa di Irak dan Transyordania.
Faisal menjadi raja Irak setelah sebelumnya diusir oleh kolonial Prancis dari Suriah pada 1920, sementara Abdullah memimpin Transyordania di bawah perlindungan Inggris.
Penulis Arab-Amerika terkemuka, Ameen Rihani, pernah menulis tentang Raja Faisal dalam sebuah buku yang memujinya.
Ia menyebut bahwa pemimpin lokal semacam itu “harus lebih dari sekadar boneka kolonial, tetapi juga kurang dari seorang pemimpin yang benar-benar merdeka.” Itulah wujud nyata fasad Arab pada dekade 1920-an.
Di tengah kemunculan negara-negara Arab semu itu, muncul kontras mencolok dari Turki pasca-Utsmaniyah.
Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk, gerakan Kemalis berhasil mengusir kekuatan imperial yang berupaya memecah Anatolia.
Meski memiliki sisi gelap—seperti penindasan terhadap kelompok minoritas, pertukaran penduduk yang kejam dengan Yunani, serta nasionalisme sekuler yang kaku—Turki berhasil mempertahankan kedaulatannya secara nyata.
Dalam hal ini, Turki jauh lebih berdaulat dibandingkan negara-negara Arab, termasuk Irak di bawah Raja Faisal.
Namun semangat perlawanan tetap menyala. Setelah peristiwa Nakba 1948, gelombang perlawanan dari kalangan militer Arab mulai mengguncang struktur kekuasaan lama yang dianggap menjadi perpanjangan tangan asing.
Revolusi Perwira Bebas yang dipimpin Gamal Abdel Nasser di Mesir menggulingkan Raja Farouk pada 1952. Di Irak, revolusi 1958 berhasil mengakhiri kekuasaan monarki Hasyimiyah.
Tetapi, memasuki era pasca-1967, pengaruh Inggris mulai memudar dan digantikan oleh Amerika Serikat (AS).
Sejak saat itu, Washington mulai menyusun kembali fasad Arab dalam bentuk baru, untuk menjaga pengaruhnya di kawasan.
Fasad Arab 2.0: Warisan lama dalam wajah baru
Hari ini, dunia Arab menyaksikan kelanjutan dari fasad lama dalam bentuk baru: Fasad Arab 2.0.
Struktur dasar dan esensi dari fasad era kolonial Inggris tetap bertahan, namun kini berfungsi untuk menopang hegemoni AS di kawasan.
Jika pada 1920-an Inggris menetapkan syarat-syarat yang ketat bagi para penguasa lokal, kini kendali itu diperluas melalui sirkulasi besar-besaran petrodolar yang kembali ke Barat—membuat kekayaan kawasan justru memperkuat cengkeraman kekuatan asing.
Seperti halnya Raja Faysal dari Irak dahulu, para pemimpin lokal masa kini masih diberi ruang gerak tertentu.
Mereka boleh merancang diplomasi sendiri, membentuk identitas nasional dan dinasti masing-masing, serta memperjuangkan kepentingan domestik mereka.
Namun semua itu hanya bisa dijalankan selama mereka tetap tunduk pada kepentingan strategis AS di Timur Tengah.
Termasuk dalam hal Palestina, meskipun hal ini sering kali bertolak belakang dengan aspirasi rakyat Arab sendiri.
Apa pun posisi resmi mereka, para penguasa ini pada akhirnya hanyalah penonton pasif—atau bahkan mitra aktif—dalam proyek-proyek kekuatan asing yang memandang rendah umat Muslim dan bangsa Arab.
Kebijakan Amerika telah menjadikan Israel, dalam bentuknya yang paling ekspansionis, sebagai poros utama arsitektur dominasi mereka atas kawasan.
Perjanjian Camp David, proses Oslo, hingga yang terbaru, Kesepakatan Abraham (Abraham Accords), adalah bentuk-bentuk penyerahan terhadap tekanan Amerika yang dikemas dalam retorika “moderasi” dan “koeksistensi”.
Sementara dunia Arab terus berkompromi, Israel terus memperluas kekuasaannya.
Namun perlawanan terhadap struktur ini belum padam. Dari Gaza yang terkepung, Lebanon yang bergolak, hingga Yaman yang hancur akibat perang, suara perlawanan masih terdengar.
Meski kerap dibungkam oleh para penguasa yang lebih memilih stabilitas kekuasaan daripada keadilan rakyat.
Para penguasa yang tunduk pada kepentingan imperialisme AS umumnya menolak bentuk-bentuk perlawanan aktif terhadap ketidakadilan Israel.
Mereka juga enggan membuka ruang demokrasi yang sejati di negara mereka. Sebagian telah berdamai dengan proyek ekspansionisme Israel, bahkan terlibat secara ekonomi di dalamnya.
Pan-Arabisme sebagai gerakan politik telah lama menghilang, namun fasad Arab tetap dipertahankan.
Pelajaran yang dapat ditarik tampak jelas: seperti halnya dulu, versi baru dari fasad ini tidak akan membawa kemerdekaan sejati. Justru sebaliknya, ia kerap menjadi penghalang langsung terhadap cita-cita tersebut.
Fasad ini tidak pernah dibentuk untuk membebaskan, dan tidak pernah dikelola demi kepentingan rakyat—meskipun ada sebagian individu yang tulus berjuang di dalamnya.
Namun seperti kolonialisme itu sendiri, tidak ada fasad yang abadi.
Semakin besar represi yang diperlukan untuk mempertahankan Fasad Arab 2.0, dan semakin besar pula kebencian rakyat terhadap kolonialisme Israel—terutama akibat genosida yang tengah berlangsung di Gaza—semakin besar pula tanda tanya mengenai berapa lama lagi fasad ini bisa bertahan.
*Dr. Ussama Makdisi adalah Profesor Sejarah dan Ketua Rektor di University of California, Berkeley. Buku terbaru Profesor Makdisi, Age of Coexistence: The Ecumenical Frame and the Making of the Modern Arab World, diterbitkan pada tahun 2019 oleh University of California Press. Ia juga penulis Faith Misplaced: the Broken Promise of U.S.-Arab Relations, 1820-2001 (Public Affairs, 2010). Buku-bukunya sebelumnya antara lain Artillery of Heaven: American Missionaries and the Failed Conversion of the Middle East (Cornell University Press, 2008), yang memenangkan Albert Hourani Book Award 2008 dari Middle East Studies Association, John Hope Franklin Prize 2009 dari American Studies Association, dan salah satu pemenang British-Kuwait Friendship Society Book Prize 2009 yang diberikan oleh British Society for Middle Eastern Studies. Tulisan ini diambil dari situs Middleeasteye.net dengan judul “Gaza, Lebanon and Yemen have exposed the cracks in the Arab facade”.