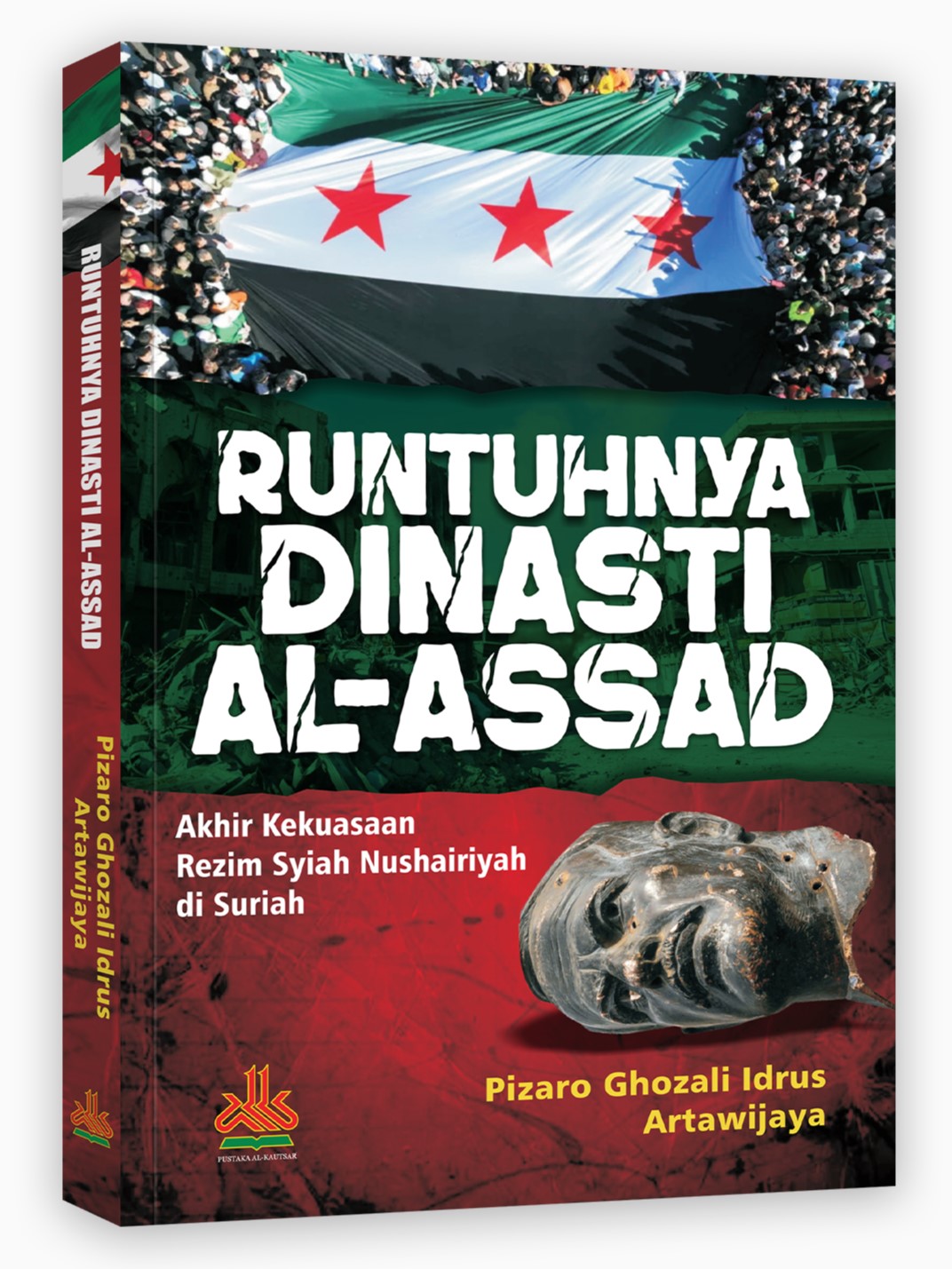Oleh: Nabil Al-Bakri
Baik Ibnu Khaldun maupun Hegel sepakat bahwa sejarah manusia bukanlah alur yang statis. Melainkan arus peristiwa yang dinamis, berkembang melalui berbagai tahapan yang dipengaruhi oleh hukum-hukum sejarah serta momen-momen dramatik yang menentukan arah peradaban.
Dalam pandangan Ibnu Khaldun, sejarah membentang melalui siklus peradaban antara kehidupan nomaden dan masyarakat madani.
Sementara itu, Hegel memandang sejarah sebagai gerak dialektis dari akal dan semangat yang merindukan kebebasan sebagai kekuatan pendorong utama perubahan historis.
Kini, di tengah berbagai gejolak global yang tengah berlangsung, pertanyaan besar muncul: di manakah kita berada dalam aliran sejarah besar ini? Apakah dunia sedang menuju babak baru yang sedang terbentuk dan lahir, ataukah kita masih berada dalam fase transisi dari siklus sejarah yang belum usai? Jika benar bahwa dunia berada di ambang perubahan besar, maka apa sesungguhnya yang tengah terjadi?
Tanda-tanda di cakrawala seakan menunjukkan bahwa kita sedang berada di sebuah titik krusial dalam sejarah, sebuah momen sarat potensi lahirnya tatanan baru yang tidak hanya berdampak pada kawasan tertentu, melainkan pada seluruh dunia.
Ini mengingatkan kita pada situasi menjelang berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, saat tatanan dunia baru dibentuk melalui lahirnya tiga institusi internasional utama: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Semuanya berada di bawah dominasi Amerika Serikat (AS) yang muncul sebagai kekuatan hegemonik global pascaperang, mengusung demokrasi dan nilai-nilai kebebasan serta hak asasi manusia.
Namun kini, lebih dari setengah abad sejak menjadi penguasa tatanan dunia, Amerika Serikat menghadapi kemunduran yang signifikan di berbagai lini.
Di tengah bangkitnya kekuatan ekonomi dan militer baru seperti China, Rusia, dan India, dominasi Amerika kian dipertanyakan.
Yang lebih mengkhawatirkan, kemunduran ini bukan sekadar persoalan eksternal karena munculnya pesaing. Tetapi juga karena pergeseran mendalam dari dalam budaya Barat itu sendiri, khususnya di jantung peradaban Amerika.
Di titik inilah muncul fenomena yang kini dikenal dengan sebutan Black Enlightenment atau “Pencerahan Gelap”, sebuah aliran pemikiran yang digagas oleh Curtis Yarvin (alias Mencius Moldbug).
Aliran ini menolak prinsip-prinsip utama modernitas politik Barat—mulai dari demokrasi, kesetaraan, hingga hak asasi manusia. Bukan lagi wacana pinggiran, ide-ide ini kini mendapat tempat di pusat kekuasaan, bahkan mulai memengaruhi arah kebijakan negara adidaya tersebut.
Pemikiran “pencerahan gelap” bukan sekadar retorika di dunia maya. Ia telah menjadi kenyataan konkret, yang tampak dalam konflik yang sedang berlangsung di Gaza.
Sebuah tragedi kemanusiaan yang banyak pihak nilai sebagai perang paling brutal dan tidak berperikemanusiaan dalam sejarah kontemporer.
Perang ini telah melampaui semua norma hukum internasional dan etika universal, mencerminkan munculnya dunia baru yang lebih keras, penuh kekacauan, dan kehilangan orientasi nilai kemanusiaan.
Konteks dan dampak dari peristiwa seperti “Thaufan Al-Aqsha” menguak kenyataan pahit: runtuhnya slogan-slogan Barat tentang demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.
Bersamaan dengan itu, kebangkitan kembali Donald Trump ke panggung politik Amerika—dan peluang besar kemenangannya dalam pemilu berikutnya—membawa agenda yang dianggap sebagai kudeta terhadap nilai-nilai yang selama ini dijadikan landasan Amerika dalam memimpin dunia.
Kebijakan ekonomi Trump menjadi cerminan arah baru Amerika yang semakin proteksionis, seperti rencana pemberlakuan tarif tinggi terhadap berbagai negara, terutama China, yang menjadi eksportir terbesar dunia dengan nilai ekspor tahunan mencapai 3,5 triliun dolar AS.
Ketimpangan neraca perdagangan Amerika terhadap China yang mencapai defisit 295 miliar dolar memperjelas arah konfrontatif yang akan diambil dalam ekonomi global.
Semua gejala dalam lanskap politik internasional hari ini tampaknya mengarah pada satu kesimpulan: dunia sedang bersiap menghadapi transformasi besar. Dalam konteks ini, kebangkitan ekonomi Tiongkok menjadi salah satu indikator paling mencolok.
Ekonomi, sebagaimana terbukti dalam sejarah, menjadi fondasi utama dalam setiap perubahan besar peradaban.
Seperti halnya ekonomi yang membawa AS ke tampuk kekuasaan global pasca-Perang Dunia II, kini kekuatan ekonomi pula yang tengah mempersiapkan Tiongkok untuk memainkan peran kunci dalam pembentukan tatanan dunia baru.
Konstelasi kekuatan global perlahan bergeser menuju sistem multipolar. Tanda-tanda awalnya terlihat dari pertarungan ekonomi sengit antara AS dan Tiongkok—konfrontasi yang tidak hanya melibatkan dua negara tersebut, melainkan juga berdampak ke seluruh dunia.
Persaingan ini tidak hanya berkutat pada angka dan tarif, tetapi juga meluas ke bidang teknologi, pengaruh geopolitik, dan bahkan nilai-nilai yang mendasari tata kelola global.
Lebih jauh lagi, perubahan ini terlihat dari beragam indikator lain: pertumbuhan ekonomi global yang kini dipimpin oleh kekuatan-kekuatan baru, persaingan teknologi yang semakin tajam, serta meningkatnya konflik bersenjata di berbagai wilayah yang tak mampu diselesaikan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia.
Selain itu, munculnya aliansi-aliansi baru seperti Organisasi Kerja Sama Shanghai dan BRICS—yang kini menyumbang sekitar 37 persen dari total ekonomi dunia—mengindikasikan bahwa tatanan dunia tunggal yang selama ini didominasi satu kekuatan sedang mengalami erosi.
Namun, barangkali aspek paling mencemaskan dari transformasi global ini bukan semata pada ranah ekonomi dan politik, melainkan juga pada level gagasan.
Munculnya arus pemikiran yang menolak total warisan politik modernitas—termasuk negara-bangsa, demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan—menandai titik balik yang serius.
Pandangan-pandangan ini, yang mengutamakan efisiensi, kekuatan, dan kepentingan pragmatis, perlahan namun pasti mulai mendapatkan tempat dalam kebijakan dan narasi publik global.
Transformasi ini tentu tidak akan berlangsung seketika. Ia adalah proses panjang yang bisa memakan waktu satu atau dua dekade.
Namun arah perubahannya sudah mulai terlihat, dan tak dapat diabaikan. Dunia tampaknya bergerak menuju sistem baru yang menempatkan manfaat di atas martabat manusia, dan efektivitas di atas etika.
Akhirnya, konflik dagang antara dua raksasa ekonomi dunia—AS dan Tiongkok—tidak lain hanyalah ujung dari gunung es dari perubahan global besar yang sedang berlangsung.
Dalam pusaran ini, isu Gaza menjadi salah satu titik api yang merefleksikan lebih dari sekadar krisis lokal.
Ia memperlihatkan kegagalan sistem internasional dalam menegakkan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang dulu diagungkan.
Bangkitnya populisme dan nasionalisme, diiringi dengan merosotnya pengaruh ide-ide humanisme global, menandai era baru yang tengah menjauh dari semangat kosmopolitan.
Cita-cita tentang warga dunia yang dijamin hak dan martabatnya, tampaknya makin menjelma sebagai utopia yang sulit diwujudkan—terutama di tengah arus populisme yang kian menguat dalam wujud paling nyatanya hari ini: Trumpisme.
*Nabil Al-Bakri adalah seorang jurnalis, peneliti, dan aktivis politik Yaman. Dia adalah pemimpin redaksi majalah Muqarabat dan mengepalai Forum Arab untuk Studi di Sana’a. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Taḥawwul Kabīr Sayugayyiru Wajhu al-Ālam”.